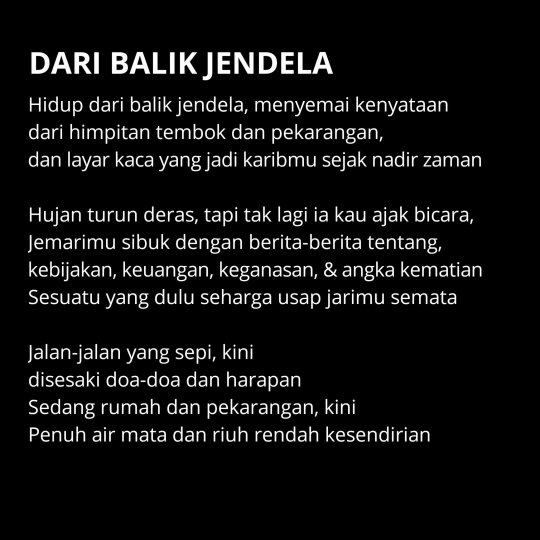Text
Candi Mendut Selatan, 2021
Jalan pulang
Jalan pulang, di mana kau bersemayam?
Sesat nian aku ini
Terbunuh tapi tak mati
Terpasung tapi menari
Nanar sekujur pangkal kaki
Sekarang...
Ingin aku usaikan peran
Racun cemara menyapa lidah
Hunus pedang disongsong dada
Seutas pesan, kepergian.
Jalan pulang
Jalan pulang, di mana kau bersemayam?
2 notes
·
View notes
Text
"Eli... Eli... Lama Sabachtani?"
Bahkan Tuhan-pun bertikai
Dengan diriNya sendiri
Baha
0 notes
Text
Hi again, Tumblr
Lama juga tak mengunjungi Tumblr.
So, welcome back... to myself.
1 note
·
View note
Text
Aku adalah aku
Yang jadi musuh, adalah waktu
Angkuh melangkah, menantang dunia
Berkalang tanah, berkalung nanah
Cita-cita mereka,
Kini kubuang di sudut diri terdalam
Jadi khawatir, dihias getir
Saat Aku harus jadi fakir
Aku tak takut menua,
Pun tak berharap terus muda
Jauh dari angka-angka, Aku
lebih takut binasa saat masih bernyawa
1 note
·
View note
Text
Untuk Sahabat Saya, Erens

Juni 2014.
Seingat saya waktu Piala Dunia 2014, tiba-tiba mas Viki mengajak saya berkunjung ke kost si Erens. Saya manut saja. Ya karena saat itu, suasana ormawa sedang sepi-sepinya. Kampus saya sudah musim liburan, ditambah momennya pas mau ramadhan.
“Ate lapo nang Eren?,” tanya saya.
“Wes ta, melu o ae. Ngancani arek galau,” balas mas Viki.
Kami berangkat sekitar pukul 11 malam. Waktu di perjalanan, saya dikit-dikit kepo sama maksud “galau” itu tadi. Maklum, saya tidak mengenal Erens secara personal-- waktu itu. Jadi ya, perlu beberapa “bahan” buat blending in dengan obrolan mereka.
“Biasa, masalah wanita,” tukas mas Viki.
Sampai di lokasi, Erens mempersilakan kami masuk ke kamarnya. Ya sudah, kami masuk. Beberapa saat kemudian ia menyuguhkan beberapa gorengan & secangkir kopi buat kami. “Hmmm, ini sogokan buat curhat ya?”, dalam hati saya.
Lalu mulailah sesi curhatnya.
Saya tidak ingat secara khusus kontennya. Yang saya ingat adalah raut Erens yang sedang bingung. Bingung “lanjut”, atau enggak. Sedangkan mas Viki berusaha “ngompori” terus supaya mereka lanjut. Saya manggut-manggut di samping mas Viki buat cari celah untuk masuk ke obrolan mereka. Tapi kebanyakan, ya menimpali saja.
Seingat saya, saya hanya menyampaikan beberapa kalimat. Salah satunya di bawah ini.
“Emang lapo awakmu khawatir ambe hal sing bahkan gurung moklakoni? Ojo macak dukun a.”
*
6 tahun berselang, Erens & wanita yang jadi bahan curhatnya itu menikah. Mungkin saja peran saya cuma tritagonis dalam sesi curhat-curhatan malam itu. Tapi Erens, di berbagai kesempatan, bilang kalau dia berhutang banyak kepada saya. Katanya, “Lak gak onok kowe pas iku, paling aku yo gak sido maju.”
Ya kalau memang benar, tentu saja saya ikut bangga kepada diri saya sendiri. Hehe.
-
Anyway, selamat menikah Ren.
0 notes
Text
Still Untitled...
Gotta be a decent man,
to at least survive
But you chose to be a fool
And play, make a mess
Well, gotta have both eyes opened
Everybody's got a fail safe
Take a shot, write your scenes
And preach, dig your own grave
Tell the tale, make your stories
And the world would then see
Roll the dice, playing sorry
You're just another misery
Keep saying I'm sorry,
Write some apology
Running from reality
Dealing with your own sanity
0 notes
Text
Apa Yang Tersisa Dari Kesepian Ini?
Di manakah letak riuh rendah
Saat udara dipaksa tanpa bahasa
Dan ruang-ruang ditata
Jadi sekat-sekat kesepian kita
Selebihnya, yang saling bersinggung
Adalah isi kepala yang jadi tawanan
Dan Jemari yang terus terkurung
Ragam makna-makna dunia
Lalu,
Apa yang tersisa dari kesepian ini?
0 notes
Text
"She was heartache from the moment that you met her."
2 notes
·
View notes
Text
TAMAN KANAK-KANAK
Saya tidak punya ingatan khusus tentang masa-masa TK. Satu yang masih saya ingat adalah jumlah uang saku saya kala itu yang cuma 500 perak. Itupun pasti habis buat jajan di warung depan. Kalau gak buat es, ya beli Ajibon. Itu lho, abon siap saji yang makannya dituang di atas nasi. Ada yang ingat?
Selebihnya... yah samar-samar saja. Pin hijau bergambar televisi buat presensi, nama beberapa teman—wanita terutama, begitu juga beberapa guru di sana. Apa lagi ya? Sepertinya itu saja.
2 hari kemarin waktu jogging pagi, saya iseng-iseng mampir ke tempat itu. Hitung-hitung nostalgia. Untung saja wabah Covid-Covid’an ini membikin jalanan sepi. Jadi saya gak malu untuk moro-moro nyelonong dan mengambil beberapa foto bangunan kecil itu.
Nah, pas asik foto-foto, moro ada seorang ibu yang punya warung depan nyamperin saya.
“Mas, tekan ndi kok moro foto-foto?”
“Oh niki Buk. Kulo alumni mriki. Sampun dangu, angkatan ’98 kaleh Diba, putranipun Bu Yayuk (nama guru saya).”
“Oalah. Aku wes dodolan nang kene suwe. Tapi kok aku gak eleng sampean yo. Sopo jenenge sampean?”
“Rendi, Buk. Dalem kulo teng RW seberang, sanes mriki.”
Kamipun bercakap sejenak, saya ingat sekali dengan beliau—meskipun beliau sudah lupa kepada saya. Bahasan kami ngalor-ngidul dari TK, kelurahan kami, sampai pandemi hari-hari ini. Dari percakapan itu pulalah saya tahu kalau Bu Yayuk, guru favorit saya pas TK dulu sudah lama meninggal. Padahal saya berencana mampir ke rumahnya yang terletak di depan gang TK ini.
“Wes suwe mas. Ket tahun kapan iku. Sampek lali aku,” katanya.
Saya lalu mengintip keadaan di dalamnya. Semua sama. Tempatnya tetap kecil, persis seperti ingatan saya yang samar-samar itu. Taman bermainnya juga tak berubah banyak, mungkin hanya cat-cat untuk menyamarkan karat pada besi-besinya.
Seperti nasib sekolah lain, TK ini ditutup selama wabah. Jadi, biarpun saya ke sananya pas hari aktif, tidak ada proses belajar-mengajar. Sepi sekali.
"Saiki murid'e tambah titik mas," kata ibu tadi kepada saya. Saya hanya manggut-manggut dan diam. Sebenarnya itu bukan hal yang mengagetkan juga sih, waktu tahun saya dulu, peserta didiknya juga sedikit. Jadi definisi "sedikitnya" ibu tadi patut saya debat.
Sedikitnya peserta didik tersebut sebenarnya wajar saja, karena TK Trisula ini sendiri terletak rada menjero alias mblusuk. Jadi secara eksposur mungkin tak terlalu kentara-- di samping fasilitas yang kelewat sederhana tentunya. Memang, sepertinya sekolah ini didesain hanya untuk kalangan warga Kampungdalem saja. Skalanya kecil.
Tak terasa, matahari mulai terbit. Setelah puas bernostalgia, sayapun melangkah pulang. Tidak lupa saya pamit dan berterima kasih kepada ibu warung tadi.
Saat saya berjalan pulang, ada ibu-ibu satu lagi yang menghampiri ibu tadi. Samar-samar terdengar, “Sopo iku mang?” Prediksi saya, si Ibu warung depan tadi bakal menjawab, “Gak ngerti” karena lupa itu tadi. Toh, maklum saja, soalnya memang sudah lama saya gak ke situ.
**
Saya cuman senyum-senyum sendiri sambil terus berjalan keluar. Dalam hati, saya berharap beliau beneran lupa. Terutama lupa kalau sayalah yang pernah ketahuan ngentit Ajibon & beberapa permen dari warungnya, dulu...
Ya. Dulu, 22 tahun yang lalu.
**


0 notes
Text
GELAS KEENAM, 2018
Terpejam di atas tepian dan malam yang jahanam
Sampai kapan, waktu kau paksa diam
Dari dalam, sayup terdengar "Black Hole Sun"
Dan kini tetes-tetes penghabisan
Angin malam telah pulang, menyudahi perjumpaan
Dengan bibir dan pandangan yang mulai buram
Kali ini lampu bar telah senyap, pengeras suara sudah gelap
Subuh, tengah sibuk bersiap
Lalu lalang, manusia,
Lampu kota, satpam, dan pintu masuk penginapan
Kain, sutra, eluhan, dan janji-janji pergumulan
Gelas-gelas, dan masa depan
di sampingnya, mimpi-mimpi berserakan
0 notes
Text
"It Remains the Same" & Sabda Nihil The Comingbacks
Ada sekelompok kecil orang yang sengaja menepi, menjaga jarak dari riuh rendah isu-isu terkini: fasisme polisi, NKRI harga mati, hingga romantisme mahasiswa sebagai “suara rakyat”.
Saya membayangkan The Comingbacks termasuk di dalamnya. Anak-anak yang dicitrakan acuh tak acuh, hobi nongkrong di kofisyop, dan hanya peduli dengan dirinya sendiri. Mereka semena-mena didakwa apolitis dan apatis. Atau setidaknya begitulah kata para orang-orang tua di linimasa yang gemar mengglorifikasi masa-masa tumbangnya orde baru.
Tetapi mereka, surprisingly, selalu mengikuti perkembangan terkini lingkungan sekitar. Anak-anak ini selalu update keadaan, entah dari berita atau linimasa di genggaman mereka, meski jarang sekali melempar komentar atau menunjukkan keberpihakan di sana. Beberapa dari mereka mungkin juga pernah mengudap buku-buku berhaluan kiri sembari mendengarkan Master of Reality-nya Black Sabbath. Bisa saja, mereka juga rutin ikut Kamisan meski tak pernah tertangkap Instastory. Dengan kata lain, mereka sebenarnya politically-conscious.
Jadi bagaimana mungkin, orang-orang yang sadar politik itu lalu (terkesan) tak peduli dengan isu-isu di sekitarnya? Bosan? Tidak berani mengambil sikap?
Atau mereka hanya kelewat sering dikecewakan?
**
Mungkin hal terakhir di ataslah yang menjadi inspirasi dari lagu ini. Jauh dari kesan (menjadi) kritik sosial, tembang ini menyajikan sebuah gambaran jelas tentang apa saja yang terjadi di sekitar tanpa terkesan tendensius, namun di saat yang sama, terdengar sangat nihilistik. Lengkap dengan sajian vokal yang lebih bisa disebut orasi serta beat-beat punk cepat yang tentu saja akan membakar amplifier dan memacu adrenalin lantai gigs sekitar.
Berita baiknya, ia dibalut dengan lirik yang cukup bagus. Bait-baitnya berhasil menangkap semangat kemarahan, sinisme, dan juga, nada-nada keputusasaan sebagian anak muda hari ini dengan artsy. Anak-anak muda yang kelewat dikecewakan oleh romantisme, pola yang sama, dan sistem yang memang didesain agar kita selalu kalah. Setidaknya, itu terlihat di pilpres kemarin yang mengharuskan kita untuk bernalar less evil. Well, fair enough.
“Government was a lie…,” teriak Judi, sang vokalis, yang seolah menjadi seruan untuk selalu menaruh curiga dan tidak berharap tinggi-tinggi terhadap apa-apa yang terjadi di dalam sisten berbasis hierarki dan otoritas, apapun bentuknya.
Apalagi hari-hari ini, saat kita sedang menikmati narasi mahasiswa-pelajar vs negara (aparat), kita secara tidak sadar dibuat merasa mempunyai "power", bahwa ini saatnya mengembalikan demokrasi, dan menuhankan kembali jargon vox populi vox dei.
Ah iya, anak-anak muda nihil ini bisa jadi alarm akan optimisme yang kadung melambung tinggi. Mereka seakan berkata, "Hei, tunggu dulu, ini tidak seindah yang kalian kira." Mereka seperti ingin menahan kita untuk tidak menenggak sebuah candu bernama "harapan".
Apalagi semakin ke sini kita juga semakin tahu jika para dewan mahasiswa yang katanya mewakili suara rakyat, nyatanya juga tunduk pada para seniornya. Mahasiswa sebagai simbol kebebasan berpikir nyatanya juga harus tunduk pada sebuah otoritas, persis seperti para senior yang mereka demo itu. Yang tua tunduk pada oligarki, yang muda jadi hamba organisasi.
Toh, memang seharusnya kita selalu punya alasan untuk ragu terhadap figur-figur publik yang dipandang “sempurna” dan “dituhankan”, bukan? Dari para ketum BEM itu, hingga Gubernur Jawa Tengah. Kepentingan-kepentingan tidak pernah mengizinkan hitam-putih dalam gerakan-gerakan ini, to? Terbukti, demo 30 September kemarin ternyata diwarnai oleh pengunduran diri beberapa BEM. Belakangan, mereka malah menolak RUU-PKS yang awalnya mereka perjuangkan itu.*
Poverty, property, all about the money
Investing, infesting, all about the laundering
Treating, threatening, all we’ve got just rejection
And then, how the dark ages will end?
Dengan gambaran yang lebih luas, mereka juga bercerita tentang bagaimana kita semua sebenarnya ikut “bersalah” - sebuah autokritik terhadap mereka juga, tentunya. Di setiap property akan selalu ada poverty, investing adalah pasangan sempurna dari infesting, dan treating adalah threatening dalam kemasan berbeda. Jukstaposisi ini menjadi sebuah permainan kata sekaligus menyajikan sebuah ironi: bahwa kita sedikit banyak juga bersalah dan berkontribusi menciptakan berbagai carut-marut dunia hari-hari ini.
“Mutant kills the enviroment.” Ya, kita adalah mutan yang selalu membunuh sesamanya. Sepanjang sejarah, Homo sapiens adalah wabah terhadap dunia itu sendiri. Toh memang tercatat bahwa di mana kumpulan sapiens berkumpul, di situ akan selalu terjadi kerusakan lingkungan dan genosida spesies lain. Jika dulu kita saling bunuh dengan senapan, hari ini kita melakukannya dengan sedotan.
Dan The Comingbacks seperti bersabda, "Di dalam sistem yang busuk ini, mari bersama menuju kemusnahan!"
Sick!
**
Tentu saja karya ini meninggalkan beberapa pertanyaan. Di satu sisi mereka terdengar seperti sekelompok orang yang putus asa dan hopeless, tetapi di sisi lain, mereka juga menyalahkan ignorance kita semua dalam menciptakan berbagai konflik dan isu-isu hari ini. Sebuah eksposisi atas kebingungan manusia dalam menentukan nasibnya sendiri dan dunia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa ide besar yang bisa menyelamatkan kita semua? Apakah ada cara mengatasi segala disfungsi yang kadung terjadi?
Ataukah memang semuanya hanya bisa ditutup dengan berbagai racauan kemarahan seperti ini? Bahwa kita memang akan selalu terjebak di dalam kebingungan kita sendiri, lalu dipaksa kembali menjalani hidup, melaksanakan role masing-masing, dan berpikir bahwa semua (akan) “baik-baik saja” atau setidaknya, tidak akan memburuk? Seperti Sisifus yang terus mendorong batu hanya untuk jatuh, apakah segala kontribusi yang bisa kita usahakan pada dasarnya adalah sebuah kesia-siaan layaknya mencari arti hidup itu sendiri? Hingga pada satu titik, kita sadar telah terjebak dalam absurdisme itu sendiri?
Sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sesulit menentukan positioning The Comingbacks menyangkut hal-hal tersebut. Secara pribadi, saya tidak akan merekomendasikan lagu ini untuk kawan-kawan yang sedang merenungi diri. Lagu ini cukup berbahaya untuk didengarkan & diamini. Menelannya secara mentah-mentah bisa membuat anda mempertanyakan segala.sesuatu, mengalami krisis eksistensial, dan mungkin, turut menjadi nihilis seperti mereka.
Saya yakin, anda lebih baik memelihara ilusi "baik-baik saja" di kepala anda daripada merusaknya dengan mendengarkan kebenaran di dalam lagu ini.
-KMPL- (@randy_kempel)
*Personal note: Ah, memang yang paling realistis adalah turun ke jalan atau menuntut atas nama rakyat saja. Tanpa embel-embel apapun. Ya 'kan?
**Tentu anda tidak harus setuju dengan mereka & juga renungan ini. Bukankah terlalu prematur untuk menghakimi sebuah band hanya dari satu karya saja?
3 notes
·
View notes
Text
Mungkin, "Kebebasan" adalah konsep yg asing utk kita. Sedari kecil, batasan selalu dibuat: di rumah, sekolah, & masyarakat.
Kita sedemikian terbiasanya utk diatur, diberi sekat ttg apa yg boleh & tidak, tanpa ada independensi & hak menolak atau setidaknya mempertanyakannya.
Di setiap fase hidup, kita selalu diberi gambaran ttg "Otoritas".
Dulu waktu kecil, otoritas tertinggi ada di kepala keluarga, lalu sekolah memberikan figur "Guru" sebagai sumber tunggal ilmu pengetahuan. Di masyarakat, ada "yang disegani", tokoh agama, hingga negara.
"Bertanggung jawab atas segala yg kita ambil" pada akhirnya hanya ilusi. Karena sejatinya, kita bahkan tidak diberi kesempatan untuk memilih/memutuskan. Sedikit saja kita melangkah keluar dari "batas-batas" itu, kita dipaksa kembali ke dalamnya.
Kita tidak ke mana-mana.
Belum lagi, figur2 tersebut digambarkan sebagai orang2 yg "berjasa". Sehingga, kita takut utk mengkritik atau setidaknya mempertanyakan kesalahan mereka.
Orang tua melahirkan kita, pahlawan akan selalu heroik, tokoh agama tak akan punya cela, & negara memegang hajat hidup kita.
0 notes
Text
YANG BISA DIPETIK DARI PENAMPILAN DIDI KEMPOT KEMARIN
Adalah kekagetan saya, seseorang dari kalangan yang relatif “lebih terdidik” mengetahui bahwa 30-ribu tidak bisa membeli attitude- atau yang kita sepakati sebagai itu.
-
Saya kira kita benar-benar mempunyai satu kesepakatan moral etika dalam konser. Bahwasannya menghargai artist lain adalah seminimal-minimalnya perilaku memanusiakan manusia. Saya kira kita semua, terlepas dari latar belakang pendidikan dan kelas, bisa sepakat dengan hal ini.
Ternyata tidak. Ketika saya bertemu dengan orang-orang “di luar radar” saya, saya kaget. Saya mengira toleransi saya akan perilaku ngehe penonton sudah setinggi itu, ternyata tidak. Ternyata saya masih marah dan mengutuk dalam hati waktu ada penonton yang menyuruh Sal Priadi turun, ternyata kesabaran saya tumbang saat melihat ribuan manusia berjibun dan menghalalkan segala cara untuk menonton artist pujaannya. Dan ternyata, ini yang paling penting, moralitas dalam dunia perkonseran tidak sesempit yang saya pandang selama ini.
Didi Kempot memang ajaib. Terlepas dari sebab-musabab ia mengalami renaissance-nya, ia salah 1 soloist yang memiliki lagu-lagu kelewat bagus. “Layang Kangen”, “Stasiun Balapan”, dan “Sewu Kutho” adalah lagu cinta paling jujur sekaligus menyayat hati yang pernah saya dengarkan. Menyematkan gelar “legenda” kepada Didi Kempot masih tidak bisa menggambarkan betapa besar figurnya.
Fenomena Didi Kempot yang merembet luas inipun hanya membuktikan betapa besar dirinya, musiknya melampaui batas demografi pendengar dan sekat-sekat sosial. Bayangkan lagu-lagu yang selama ini benar-benar segmented itu, yang selama ini hampir tidak pernah mendapatkan tempat di TV, kini dinyanyikan oleh ribuan atau bahkan jutaan orang di Indonesia.
Konsernyapun menjadi begitu heterogen. Menjadi melting pot manusia dari berbagai latar belakang. Ia adalah satu dari sedikit momen di mana kamu bisa menjumpai mas-mas totebag-an dan mbak-mbak racing ada di dalam satu konser dan berirama satu suara.
Dan yang terjadi kemarin adalah fenomena pergesekan kelas... Saya, dan mereka.
Hasilnya tentu tidak benar-benar mulus. Kelas menengah seperti saya yang terbiasa menonton gigs/konser dengan standar moral yang polished atau sopan, harus dihadapkan dengan keliaran audiens dari berbagai orang yang konon datang dari berbagai daerah itu. “Daerah” yang kadang secara angkuh kita sebut “pinggiran”, ���Coret”, atau “Kabupaten”. Mas-mas semiran abang, hingga mbak-mbak gaul tarkam. Ya tho?
Saya kaget, saya terhenyak. Batas-batas norma dan standar kewajaran saya diuji dan akhirnya kalah. Dan saya, akhirnya, marah. Marah kepada mereka yang menurut saya tidak memanusiakan manusia. Marah terhadap perilaku ‘kampong’ yang tidak ada dalam definisi “Menonton Konser yang Baik & Benar” di kamus saya. Tetapi yang paling penting, saya, secara tidak langsung, marah terhadap diri saya sendiri.
Marah karena ternyata saya tidak bisa memahami konteks sosial mereka. Marah karena saya menafikan privilese saya sebagai kaum “terdidik”, dan juga, marah karena saya tidak bisa mengerti mereka sebagai sesama manusia. Inilah yang saya renungkan beberapa hari ini. Apakah memang saya saja yang kurang mengerti, bahwa memang begitulah nilai-nilai yang tertanam di benak mereka sejak kecil?
Tentu saja bukan berarti saya memandang perilaku mereka benar. Tentu tidak. Jika presentasi konser adalah panggung bicara, perilaku mereka adalah sebuah bentuk penghinaan yang kelewat kejam. Dan tentu saja, saya akan terus mengutuk perilaku-perilaku seperti itu di masa depan. Jelas. Sayapun, jika bisa, ingin mengedukasi mereka (jika itu muluk-muluk, ganti kata ‘mengedukasi’ dengan ‘berbicara dengan’), agar setidaknya menghargai siapa-siapa saja yang tampil- terlepas dari mereka tahu atau tidak artist tersebut. Saya masih percaya konsep altruisme dan kebaikan universal- dalam kadar tertentu.
Poinnya, mungkin saya saja yang harus lebih legowo, sabar, mengerti kalau menemukan orang-orang seperti mereka. Kejadian kemarin membuat saya merenung dan memahami mereka, menerima kenyataan bahwa "Lho, ancen ada lho orang-orang kayak gitu." Ya, mungkin saya saja yang terlalu "nyaman" bergaul dengan sesama kelas menengah, mengadaptasi kewajaran-kewajaran, norma-norma, dan model pergaulan mereka, hingga menafikan keberadaan mas-mas & mbak-mbak itu tadi.
Pada akhirnya, mungkin mereka sama dengan kita yang kadang terlalu sombong untuk "mengakuisisi" sebuah figur pujaan. Mungkin saja, mereka merasa bahwa Didi Kempot adalah suara hati mereka sejak dulu, dan tidak rela bila grassroot idol mereka tersebut diaku-akui oleh kita, kelas menengah yang baru kena hype-nya hari ini. Ingat 'kan, seorang warga i n d i e. yang ngetwit, "AKU GAK MAU SAL PRIADI MAINSTREAM!". Mungkin saja, ini adalah "balasan" dari mereka yang menganggap Lord Didi sebagai pahlawan sadbois proletar. Bisa jadi 'kan? Setidak-tidaknya kita tahu, jika perilaku eksklusivitas tidak selalu terbatas pada kelas, hehehehe.
-
Mungkin saja begitu. Toh, jika kecentok lagi, pada akhirnya saya hanya bisa ngomong:
“Yoweslah.”
0 notes
Text
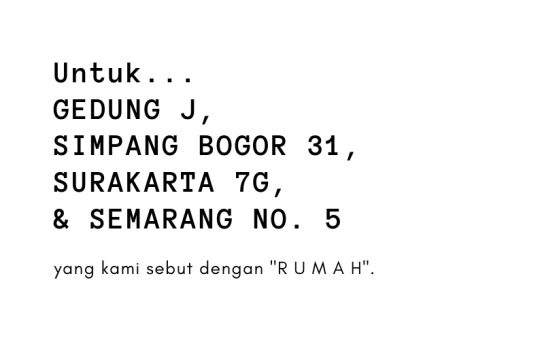
Sebuah intro untuk zine tanggal 31 Agustus 2019 nanti. Zine ini berisi tulisan dari para ketua BEMFA Sastra medio 2012 hingga 2018. InsyaAllah.
0 notes