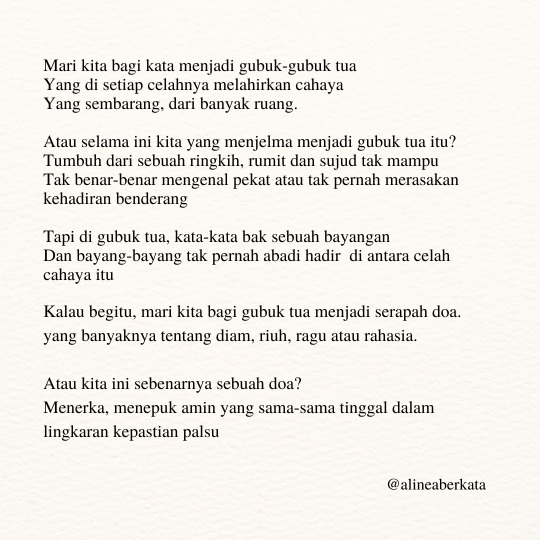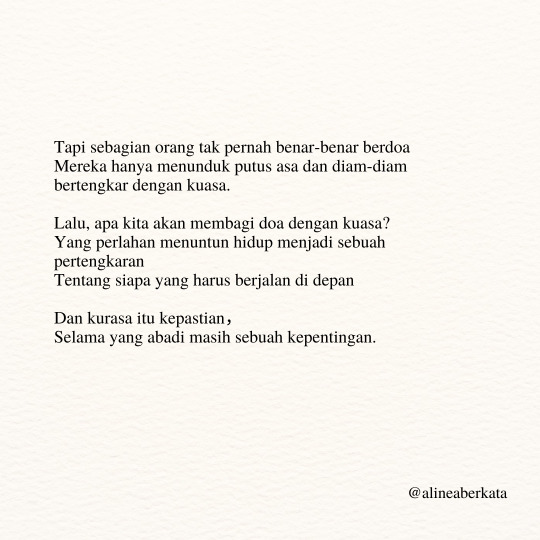Text

Bagaimana cinta membagi ilmu ikhlasnya?
Sebuah kehilangan.
Berbicara sebuah kehilangan yang akan selalu terjadi pada yang hidup, pada yang perasa, pada yang mengharapkan keabadian. Darinya, ada yang semakin kokoh dan fasih menerima, ada yang semakin terluka dan dihinggapi trauma. Dan hidup tak memiliki ruang untuk sebuah kehilangan, ia akan meninggalkan, bergulir sendiri sebagaimana sifatnya yang tak terhentikan. Namun waktu juga pilihan yang baik dari kehilangan itu sendiri, karena selain manusia, waktu juga menggulirkan yang hilang, walau luka tak terlekang.
Malam ini, ikhlas memeluk hangat diriku walau dibarengi basah air mata kelegaan. Setelah lama mengurung diri dari rasa takut ditinggalkan dan kehilangan, akhirnya salah satu ikhlas berbagi maknanya untuk meleburkan yang kugenggam erat. Yang tak bisa lepas adalah musuh dari ilmu ikhlas. Aku mengerti dalam hidup yang tak tentu panjang pendeknya, ikhas yang banyak macamnya, ada yang tersemat dalam perihal mencintai.
Mencintai yang sebetul-betulnya hanya perihal menerima dan kehilangan dan terus berulang. Menerima yang sebetul-betulnya adalah bahagia dari sedih yang tak berkesudahan. Kehilangan yang sebetul-betulnya adalah takdir tuhan.
Sebetulnya perjalanan cinta yang ini serba 'apapun yang terjadi, maka terjadilah' awalnya seperti itu. Terlalu lama bersama membuatku berpikir bahwa kita tak bisa dipisahkan bahkan oleh kuasa tuhan. Aku kehilangan akal setelah kita dapat melewati simpang dan kelokan yang curam, aku minta lebih cinta dan marah jika tak didahulukan, pamrih dan serakah.
Maka ada yang kugenggam erat, yang menjadi cikal bakal kehilangan. Kupupuk sendiri, kusirami, dan tumbuhnya kesepian. Aku melewati yang paling utama, yaitu bersama. Ternyata aku berjalan sendiri, kau tertinggal dalam kejenuhan atas gelanggang yang terbuat dari rasa takutku.
Dan apa yang harus aku lakukan?
Menerima. Melepaskan yang kugenggam, membiarkanmu melebur entah untuk kembali atau pergi. Kembali pada awalnya, 'Apapun yang terjadi, maka terjadilah.'
Aku sudah menerima, walau banyak tanda tanya. Dari sebuah kehilangan dan harapan semu pada manusia. Yang sewaktu-waktu mungkin akan pudar atau semakin jelas karena menyakiti dan mencintai yang tipis batasnya. Dalam proses menerima ini, akan ku buat berarti untuk menyiapkan kehilangan yang menanti.
Dan untuk merayakan sebuah kehilangan adalah dengan mengenangnya.
0 notes
Text
Kita dan empat bulan berikutnya atau selamanya
Selepas pulang
Seringnya aku membayangkan indahnya matamu dan hangatnya pelukmu .
Seandainya cicilan kpr bisa diatasi dengan tabungan rindu dari senin sampai sabtu.
Namun,
Sekiranya kita bisa usahakan rumah itu.
Kita masih terlampau dangkal untuk sebuah mata air, membutuhkan waktu yang hilang dan pergi dalam tujuan yang samar pasti.
Meraba, bertukar kesalahan, saling mengobati lalu berjumawa bahwa kita dapat sehidup semati. Kita terkadang gagal atas pertanyaan tentang baik buruknya aku dan kamu atau menyadari bahwa menyakiti dan mencintai tipis batasnya.
Musim hujan ini, kepalaku mengebul romantis. Membayangkan rintik-rintik yang menembus di jas hujan seaduhai sentuhanmu di sabtu malam. Hasrat bertemu lebih vokal setengah berteriak,
ingin cepat menemui suasana asyik di tulang belikatmu.
Semakin waktu mendekati mimpi kita di empat belas Februari, semakin menyadari banyak hal yang tak satu tuju. Kita payah dalam menyatukan selera, sekadar dari 'I love you beibeh'-nya Changcuters dengan 'Tak ada yang seindah matamu'-nya Kunto aji, terselip bete yang sedikit berkepanjangan dan butuh 'Evaluasi'-nya Hindia menuju 'Kita sadar ingin bersama'-nya Tulus.
Aku ingin disayang dengan amat. Ada ketakutan abstrak mendekati kepercayaan itu lambat laun. Ego kita mulai mengaum bingar tentang ke eksistensiannya bahwa ialah yang satu-satunya harus diobati. Terkadang kita mampu memberi obat penenang atau ikut meringis menjadi korban. Ada dibeberapa kesempatan menyakiti kecil-kecilan, namun sebisa mungkin kita tegur bisik-bisikan. Satu yang masih kita patuhi, baik buruknya aku dan kamu, biar kita yang tau.
Lagi-lagi mencintai bukan perihal 'aku cinta kamu'. Rumit, bingung dan minta banyak uang. Tapi selalu ada satu per satu yang spesial di hatiku. Salah satunya, jam 8 malam atau kemalaman atau ketiduran kita sempatkan masuk ke dalam ruang obrolan 'kita ceritakan apa yang bikin pusing hari ini', konsisten namun suasananya dinamis. Ada hari yang banyak ceritanya, sewaktu-waktu hanya diam menikmati sepi yang berarti 'jangan dimatiin aku cuma kangen kamu'. Ada kata yang menyulut api atau doa-doa peneduh kita. Di ruang itu mulut kamu berbusa mencaci maki atasan yang menyebalkan, kaki kita menendang-nendang minta gaji dinaikkan, tangan kita gemas ingin mengunduli orang-orang yang merusak mood kita seharian. Aku senang. Saat-saat dimana kita bisa merebahkan perasaan satu sama lain. Lalu kita siap-siap tidur atau aku duluan saat mulutmu masih berusaha menidurkan perasaan yang berkecamuk hari itu. Maaf, terkadang ceritamu ikut berbaring menyelimutiku.
Sampai akhirnya kita kembali realistis setelah waktu membiarkan kita berlarut pada rangkaian jatuh cinta. Kita semakin berani menunjukkan sejujur-jujurnya diri masing-masing. Meminimalis pertemuan mengingat harga solar yang memuncak. Ternyata cinta juga butuh modal. Banyak usaha yang cukup menyita waktu dan perasaan. Aku semakin terjatuh dalam keseriusan hubungan ini, sempit peluang untuk melepaskanmu, patah hati dan kehilanganmu mengencangkan kendali atas apa yang akan terjadi di hidupku kedepannya.
Aku selalu meminta, untuk yang ini jangan dipisahkan ya, dan berharap kamu juga begitu. Entah doa apa yang menyertai kita. Semoga 'rumah' ini ada dalam kemampuan kita untuk diusahakan ya.
8 notes
·
View notes
Text
Perihal Barat
I.
Barat selalu berjalan. Entah berapa persimpangan yang telah ia jamahi, entah tempat apa yang ia tuju, entah doa apa yang menyertainya. Hal pasti yang ia ketahui adalah kesedihan selalu mengikuti langkahnya, kemana pun ia berjalan.
II.
Aku selalu menunggu. Di depan jendela sebuah tempat yang lama tak terjemah, entah untuk siapa aku menunggu, yang pasti kesedihan akan membawa seseorang pada tempat ini, tempat yang dimaknai rumah.
III.
Saat itu badai, membawa Barat pada pintu yang harus diketuk lama untuk terbuka. Aku ragu menerimanya dan masih bersembunyi malu di baliknya. Tapi semesta dan waktu tak pernah bisa diajak bekerja sama, saat itu pula Barat berteduh dan aku meluruh.
IV.
Sementara dan selamanya. Barat semakin mahir menemukan jalan keluar dalam labirin yang kubuat saat aku berantakan membangun sekat-sekatnya. Namun Barat bukan manusia yang tak punya rasa malu, ia menukarkan itu dengan sebuah perjamuan. Ia menghidangkan romansa imaji. Dan manusia selalu terpaut waktu, apakah Barat ada untuk sementara atau selamanya?
V.
Barat berkata, aku ini rimbunan detik yang mampir di selasar rumahnya
Yang hinggap di pundaknya saat tegukkan terakhir dari secangkir susu
Angin sore yang saat itu bersenandika menyangkal, katanya aku ini daun terakhir
yang seksama menyaksikan langit menjemput hari dari ufuk timur ke barat
Barat berbisik pelan, kalau aku ini pacarnya.
Kemudian ranting-ranting berat berayun dan burung bercicit kikuk
Aku ada di sana, saat itu sedang menjadi manusia dan memegang kendali atas semburat merah di pipiku.
VI.
Kembali hujan. Aku baru menyadari bahwa Barat lahir dari sebuah badai yang riuh dan aku manusia yang dapat hidup dari banyak salah. Malam itu, rembulan tak enak dipandang dan tumbuh sebuah dinding yang menjadi latar dua kaki yang saling membelakangi.
VII.
Barat kembali tersenyum di penghujung musim hujan. Ia mengajakku pada sebuah perjalanan singkat yang sedikit melibatkan masa lalu. Satu yang kuketahui, Barat tumbuh dari rumah ke rumah. Hari itu juga pertama kalinya kami menggenggam sebuah harapan, dengan tangannya dan tanganku.
VIII.
Hari terakhir musim penghujan. Lagi-lagi aku tersadar, bahwa Barat tetaplah badai. Namun saat itu lebih riuh, lebih berisik dan aku tak mengenalinya. Dinding yang kian hari tumbuh itu sekarang tingginya melebihi pundakku, dinding itu pula yang malam ini melukiskan siluet dua tubuh yang saling memunggungi.
IX.
Teruntuk Barat:
Barat, aku bukan ilalang yang tercipta untuk kemarau dan berlarut dalam sukmanya.
Jemari ini tak ayal bergulat dengan gumpalan imaji bila bersamamu.
Guratan takdir terbentuk saat kau ketuk pintu itu, yang tak sadar menjadi benang merah diantara kita berdua.
Barat yang manis, sudah berapa malam yang kita lewati bersama? Waktu dimana kita dapat menjelma menjadi apapun yang kita butuhkan. Menghabiskan sepanjang hari bersamamu adalah sandiwara kasih sayang terbaik yang kujalani.
Setelah kamu berpamitan pagi itu, aku jadi selalu mengalihkan pandanganku pada ujung jalan yang menjadi awal dimana kamu dapat menemui rumah ini. Barangkali kamu hadir diantara daun yang berguguran itu dan mencoretkan seberkas warna pada semestaku yang meringkuk sendu.
Seperti yang kamu ketahui, bahwa manusia selalu kalah oleh kenyataan. Kamu ditakdirkan untuk selalu berjalan dan aku ditakdirkan untuk selalu menunggu. Hidup ini memang melulu perihal menunggu Barat, setelah itu hanya ada dua jawaban, doa baik atau buruk.
Sudahlah Barat, jangan merasa bersalah atas datangnya kemarau. Musim akan berganti dan kamu akan selalu kusiasati. Tapi apakah kamu akan datang pada penghujan nanti?
X.
Kemarau datang dan Barat kembali berjalan. Kali ini entah kesedihan yang mengikutinya atau ia sendiri yang menjemput kesedihan itu. Dinding sempurna tumbuh, ada sepasang nama di sana dan namaku yang mati.
2 notes
·
View notes
Text

Anak kecil itu menyadari, ada yang sedang merayakan kesedihan diantara wajah-wajah minta pulang. Matanya menelisik seseorang di depannya yang tunduk dan tak berkutik, isakan tertahan dan buliran air mata di balik kacamata berembun itu menyatu dengan rintikan hujan bulan Desember yang mampir di jendela angkutan kota. Menoleh ke kanan dan ke kiri, tak ada yang peduli. Ia mencoba menebak alasan bagaimana air mata itu berjatuhan tanpa sumpah serapah menyalahkan atau sebuah keinginan yang tak tergugu. Dalam sudut pandangnya, menangis selalu perihal itu-itu saja. Tiba-tiba suara racauan tak jelas mengalihkan perhatiannya, di ambang pintu seorang yang usianya tak jauh berbeda darinya menyodorkan tangan, minta diberi uang. Tak ada yang peduli, semua penumpang hanya sibuk menahan geram pada lampu merah yang menyita kesabaran. Pengamen kecil yang wajahnya cemong itu berlalu pergi bersamaan lampu hijau yang berbinar dari kejauhan.
Sore tak pernah punya belas kasihan, pada tangisan yang terpendam atau pengamen kecil yang letih minta makan.
2 notes
·
View notes
Text
Yang Terlewatkan

youtube
Biarlah kita menjadi bayang-bayang yang selalu diburu keputusan. Menyampingkan benar atau salah, kita sepakat menentukan waktu malam yang selalu memaafkan apapun yang tak benar menjadi tempat perasaan ini tumbuh. Lampu redup di ruang yang kedap tak pernah bisa mengungkapkan apa yang ia lihat, bahkan benderang lampu jalanan hanya menyaksikan apa yang akan ia lupakan esok.
Biarlah waktu yang bertengkar, kita jangan. Kita punya waktu malam, yang semakin larut semakin rumit dijelaskan. Apalagi perasaan yang semakin menepis rasa risau. Di mata yang setengah telanjang, deretan nada bersambung padu pada genggaman yang tak seharusnya kita dapatkan juga dekapan yang melawan apa yang tak seharusnya terjadi. Dan ini malam, tempat membenarkan kekeliruan dan menyembunyikan rasa hina.
Bunyi pintu terbuka terdengar sampai ruangan lain yang pintunya menyisakan sedikit celah, perempuan yang sejak tadi sibuk bersolek langsung menoleh ke arah datangnya suara. Senyum tipis tercipta pada wajah yang tetap bersinar dalam remang-remang ruangan, tak langsung menghampiri seseorang yang kedatangannya tengah dinanti itu, ia malah kembali pada cermin di depannya, mematut diri untuk tampil sempurna di hadapan seseorang yang baru saja tiba.
“Kenapa udah dimatiin lampunya?” tanya pria yang sekarang merebahkan dirinya di sofa ruang tengah
“Harusnya aku yang tanya, kenapa mas udah pulang?” Perempuan itu ikut duduk di samping pria yang kini memejamkan matanya.
“Ruwet, gak ada yang waras kalau deket tanggal rilis.”
“Kali ini apa lagi?”
“Biasa, dari subuh kerja gak ada hasilnya yang ada ribut melulu.” Perempuan itu memindahkan kepala pria di sampingnya ke pahanya kemudian mengelusnya dengan lembut.
“Kalian itu pekerja keras semua tapi saking kerasnya sampai kepala kalian pun ikutan keras juga.”
“Mas bener-bener gak paham sama si Eros si Uji, paling klop tapi kalau udah beda maunya ributnya bikin pusing tujuh keliling.” Kali ini pria itu menatap lamat wajah wanita di hadapannya.
“Berapa bulan lagi semuanya rampung?” Mereka bersitatap dengan jarak yang dekat.
“Tiga bulan lagi dan track lagu masih sedikit.” Pria itu masih tenggelam menatap wajah perempuan yang entah kenapa perlahan melepaskan lelah di kedua pundaknya.
“Sedikitnya mas tuh beda sama sedikit orang lain, lihat aja nanti listnya pasti panjang banget.”
“Gimana hari ini, Phi?"
"Ya gitu deh, kaya biasanya. Suntuk banget," balas perempuan itu sambil mengerucutkan bibirnya membuat pria di bawahnya menatap gemas sambil mencubit pipinya.
"Terus kamu maunya gimana?"
"Sama mas Duta terus, kaya gini. Kalau sama mas rasanya gak pernah bosen padahal gak ngelakuin apa-apa."
"Bisa aja kamu, Phi."
Tak ada percakapan lagi, keduanya sibuk memuja rupa masing-masing melupakan sebentar kepentingan yang tak pernah bosan menghantui pikiran mereka. Tangan yang semula terbebas kini saling berkaitan satu sama lain, Duta beranjak dari tidurnya kemudian mendekap erat tubuh perempuan di sampingnya. Harumnya selalu sama dan hangatnya tak pernah ia temukan di tempat lain. Satu kecupan mendarat di pipi Sephia yang memerah.
Perempuan itu menenggelamkan wajahnya pada dada bidang pria yang beberapa bulan ini merengek minta masuk ke rumahnya. Duta selalu menawarkan apa yang Sephia tak punya dan Sephia selalu memiliki apa yang Duta inginkan. Festival musik di penghujung tahun mengantarkan mereka pada malam-malam yang telah mereka lewati. Suara Duta yang biasanya hanya dapat Sephia dengar melalui radio kini dapat ia dengarkan langsung kapan pun terlebih saat-saat sepi semakin semarak di malam hari.
Dering telepon terdengar di dalam saku celana pria yang tengah terbuai dengan kegiatan mereka. Duta mengeluarkan ponselnya yang sudah berhenti berbunyi dan meletakkannya di atas meja, memilih mengindahkan panggilan itu. Mereka kembali bersentuhan, saling menyampaikan rasa kasih sayang dengan caranya masing-masing. Tak ada satu pun yang bisa menghentikan mereka saat bersama.
Dering telepon kembali berbunyi, kali ini cukup lama. Sephia yang merasa terdistraksi lantas mengalihkan pandangannya pada ponsel yang terus berdering.
"Angkat dulu mas, takutnya penting," titah perempuan itu. Perintah tersebut sukses menghentikan pria yang masih betah memeluk erat wanitanya.
'Bundanya Kanaya'
Sebaris nama yang tertera di ponsel itu sontak menyadarkan mereka pada sebuah kenyataan. Kenyataan yang tak akan pernah bisa dilawan gelapnya malam, kenyataan yang perlahan menghanyutkan mereka pada kesengsaraan.
"Halo Pah, bisa pulang dulu sebentar? Kanaya demam dari kemarin, sekarang demamnya makin tinggi aku mau bawa dia ke rumah sakit." Suara di seberang telepon.
...
Alternative Universe
1 note
·
View note
Text
[Tentang Tahun Ini]
Ada beberapa harapan yang belum bisa terlaksana karena keterbatasan ruang, ada tubuh yang terpaksa lepas dari dekapan karena terhalang jarak dan masih banyak hal-hal yang hanya akan menjadi cerita dan angan belaka. Ditahun ini kita punya waktu yang banyak namun dengan rasa sulit yang ikut menetap.
Tuhan sedang tidak bersandiwara kok, Dia sedang mengajari kita tentang sebuah batas. Batas yang memang tak familiar dan tak dapat kita temui sebelumnya. Seperti nyatanya ramai yang menyapa kita setiap hari, terhalang batas juga.
Tahun ini rasanya manusia diberi kelebihan untuk melihat takdirnya sendiri dengan mata telajang. Mungkin barangkali Tuhan sedang mengajarkan kita memeluk ikhlas yang tak berujung.
Terima kasih untuk sama-sama berjalan sampai penghujung, semoga doa yang disertakan sebelumnya dapat terlaksana di tahun berikutnya.
1 note
·
View note
Text
I. Hari Jadi ke Tujuh Belas
Manusia banyak mempelajari pada angka tujuh belas, banyak perihal yang perlahan mengerti pada angka tujuh belas. Semulanya kehilangan menjadi hal sedih biasa yang lambat laun terlupa namun di usia tujuh belas kehilangan dapat menjadi alasan seseorang berhenti di tengah jalan.
Ada yang perlahan menemukan sepi, ada yang berjalan mencari pembenaran di gelapnya malam, ada yang semakin benderang, ada yang baru mengerti artinya pulang dan banyak yang berusaha menjadi berarti.
Tiupan angin kecil pada lilin angka tujuh belas seolah sebagai batas manusia untuk mulai mengerti bagaimana semestinya dunia bekerja. Untuk mengalami kepergian, pencarian, perpisahan, kematian dalam bentuk apapun.
Malam ini, tulislah bagaimana usia tujuh belas di hidupmu.
2 notes
·
View notes
Text
Sebuah Ruang
Jikalau sepertiga malam datang, gemercik sepenggal masa lalu berbisik riang di celah remang-remang. Membawa sebuah kabar tentang bagaimana seseorang menghadapi perihal baik dan buruk di masa lalu. Telinga sayup mendengarkan dongeng dengan peran utama dirinya sendiri.
Demikian dengan tiga belas manusia yang sama-sama berjalan dalam roda kehidupan. Berbagai penggalan cerita yang hampir tenggelam oleh guliran waktu berhasil mereka sematkan pada selembar kertas yang ditulis tepat sepertiga malam. Dilampirkan ke kantor pos yang kemudian dikirimkan pada sebuah alamat yang bernama Ruang di Ambang Pilu.
Ruang di Ambang Pilu merupakan ruangan dengan daun-daun pintu berupa mozaik-mozaik cerita dari tiga belas manusia. Tiga belas manusia yang percaya bahwa nyatanya Tuhan tidak pernah tidur, bahwa nyatanya waktu juga sebuah tempat singgah.
1 note
·
View note
Text
II. [2] Sebelah Dunia Persekot
Tidak akan pernah ada yang tahu takdir akan membawamu kemana, mungkin itu yang sedang dirasakan Juang pada usianya yang kemarin menginjak 20 tahun. Ditemani angin malam dan langit Ibukota yang tak acap bisu, wajah tanpa ekspresi tertutup balutan asap rokok dengan tubuh setengah telanjang itu memerhatikan tubuh lain yang meringkuk di ujung ruangan dengan alas tipis dan tanpa selimut. Suara detik jam semakin terdengar bersamaan dengan suara radio yang semakin sayup, saatnya beristirahat namun matanya enggan terlelap.
Juang dan jalanan. Sepertinya akan terlihat menarik untuk dijadikan sebuah bahan tulisan kalau suatu saat nanti dirinya menjadi orang berpengaruh di dunia ini. Kemudian ia tertawa geli, pikiran aneh seperti itu memang terkadang datang pada jam-jam malam. Bagaimana pula ia seorang anak putus sekolah akan menjadi orang seperti itu, mendapat izin menarik penumpang saja ia senang kepalang, sekarang yang terpenting bukan lagi tentang mimpi dan jadi apa nanti, tapi tentang makan apa besok.
Tubuh yang meringkuk di sudut ruangan itu terbangun dan bersandar ke dinding, Juang kembali mengisap rokoknya dalam-dalam lalu menghembuskan asapnya perlahan.
"Sudah pulang?" tanya perempuan itu sambil merapihkan rambutnya. Juang tak menjawab, kemudian mereka saling bertatapan sebentar dan kembali memalingkan perhatian.
"Aku nunggu kamu dari tadi, eh ketiduran. Malam ini malam terakhir aku ganggu kamu, esok aku pindah ke indekostku. Ini, sesuai perjanjian, dibayar di muka. Makasih udah banyak bantu."
Perempuan itu menaruh segulung uang yang diikat dengan karet. Juang tak langsung menerima uang itu, ia sedikit tersedak ludahnya sendiri selepas perempuan itu selesai berbicara. Pada detik itu uang tak lagi berarti baginya, netra Juang menatap tak setuju keputusan perempuan yang sekarang melamun di hadapannya, tak sadar bahwa Juang memikirkannya lebih dari siapapun, semenjak perjanjian persekot itu.
...
Terik matahari siang itu membakar kulitnya juga menyilaukan pandangannya ditambah berisiknya orang yang berlalu lalang dengan masing-masing obrolan. Inilah fase hidup Juang setelah puluhan malam di jalanan, tak ada yang lebih baik memang tapi terminal memberikannya makan untuk satu hari kedepan. Juang berjalan menelusuri warung-warung yang menjadi tempat menunggu pemberangkatan. Baru beberapa menit matanya sudah perih terkena pasir yang berterbangan karena banyaknya kendaraan yang keluar-masuk.
"Baru dateng lu?" tanya seorang pria gemuk yang sebelah kakinya diangkat ke kursi.
"Iya bang, kemarin gue narik sampe malem," jawab Juang yang lalu ikut duduk di sebelah pria gemuk itu.
"Ngopi dulu aja." Pria itu memesan kopi untuknya.
"Yang lain mana bang?"
"Semuanya jalan, kagak ada angkot kosong. Tapi ada kerjaan buat lu, nanti jam 12 Bu Ati nyuruh lu buat angkatin belanjaannya ke warung."
"Enggak sama abang?"
"Dia nyuruhnya sama lu, naksir kali tuh apa-apa Juang mulu." Pria gemuk yang Juang sebut abang itu tertawa.
"Yee amit-amit deh."
Juang menggapai gelas plastik berisi kopi hitam yang biasa ia minum setiap hari di warung itu, warung yang makanannya dapat dimakan sebelum dibayar, ya walaupun Mpok Siti pemilik warungnya sangat teliti dalam mencatat hutang para pengutangnya. Bajunya sedikit basah karena keringatnya bertambah banyak, rambut yang sudah lama tak ia pangkas diikat kecil dengan karet gelang bekas bungkus nasi kuning tadi pagi. Hari ini mungkin ia akan pulang malam lagi karena siang saja belum ada angkutan umum yang dapat ia jalankan.
"Copet!" teriakan seorang perempuan dari belakang membuat suasana di sana menjadi ricuh. Beberapa orang ada yang mengejar pelakunya dan sebagiannya lagi mengamankan barang berharga yang mereka bawa. Sebenarnya hal tersebut sudah biasa terjadi bahkan mungkin Juang juga kenal dengan pencopet itu, ia sedikit tak tertarik dan tak memiliki niat untuk membantu perempuan malang itu, Juang kembali menegak kopinya.
...
Langit hampir menghitam tapi terminal semakin ramai ini adalah waktu yang tepat mendapatkan cuan juga menguras kesabaran karena macetnya yang luar biasa tak dapat ditahan. Sejak jam tiga sore, Juang mendapatkan izin jalan walaupun harus terus berganti dari angkot satu ke angkot yang lain. Kalau menurut orang, menjadi supir angkutan umum itu mudah dan remeh, mereka keliru. Memang pekerjaannya tak memerlukan nilai Ujian Nasional tapi tetap saja rasanya sulit sekali kalau sebagai pendatang dan tak punya kenalan. Harus lebih kerja keras mencari mana yang mau gantian, adapun yang mau paling hanya satu rit atau dua rit saja.
Beruntunglah Juang mempunyai wajah yang tampan, membuatnya sedikit mudah mendapatkan penumpang setia atau belas kasihan orang sehingga angkotnya selalu penuh sekali jalan.
Malam tetap berjalan Juang masih melaju kencang. Wajahnya yang penuh peluh itu sedikit bersinar karena uang ongkos menggunung di saku celananya. Hari yang baik walau harus banyak bersabar. Malam ini pun ia tak perlu membeli makanan karena tadi Bu Ati membekalinya nasi dan lauknya, sedikit tak enak hati dan seperti ada yang mengganjal karena Ibu-ibu pemilik warung itu selalu baik kepadanya, tapi untuk bertahan hidup apa saja ia terima sekarang.
Juang meregangkan lehernya yang pegal setelah mengemudi, sekarang waktu sudah hampir tengah malam sebagian pedagang menutup tokonya dan bersiap pulang namun tidak untuk supir-supir yang sedang melingkar berkumpul dengan minuman keras di tengah meja. Jujur saja ia pernah mencoba minuman itu, mau bagaimanapun ia harus beradaptasi dengan lingkungannya. Setelah itu ia tidak tertarik dan langsung menghindar dari acara malam mereka. Kalau memang ia ditahan tak boleh pulang, paling Juang hanya diam menyendiri di samping warung itu sambil merokok.
Hari ini pun seperti itu, ia duduk di kursi kosong warung yang tutup sambil mengeluarkan bungkus rokok di saku jaketnya tak lupa sambil melamun juga. Sepertinya semakin umurnya bertambah melamun adalah kegiatan yang wajib dilakukan. Juang mengambil uang hasil menarik angkot tadi dan menghitungnya lalu memisahkannya mana untuk setoran atau untung miliknya. Cukup banyak dan mungkin dapat menghidupinya dua hari kedepan. Seorang perempuan dengan tas besar di tangannya datang dari arah samping. Perempuan itu menunduk membuat wajahnya tertutup rambutnya yang sedikit berantakan.
"Kalau tidur di sini, gak akan diusirkan?" ucap perempuan itu setelah lama duduk di pinggirnya.
Orientasi.
"Gak, inikan terminal pasti banyak yang tidur juga nunggu jemputan." Kemudian ia mendengar hembusan napas yang berat dari perempuan itu.
"Ternyata pergi dari rumah itu bukan hal yang mudah yah," lanjut perempuan itu.
"Hm tergantung. Kenapa? Kabur dari rumah?"
"Mana ada kabur dari rumah, kalau harus memilih ya mending di rumah saja, enak, kalau lapar makan kalau ngantuk tidur di kasur." Perempuan itu sekarang memperlihatkan wajahnya.
"Enggak juga,"
"Berarti kamu yang kabur dari rumah," Perempuan itu terkekeh.
"Sok tahu. Terus kenapa kesini kalau enggak kabur?"
"Aku ini orang kampung apalagi tujuannya kalau tidak mengadu nasib, tuntutan juga harapan yang buat aku pergi ke tempat yang katanya menjanjikan ini,"
"Cih harapan, yang mana harapannya itu cuma omong kosong doang." Juang beberapa kali menatap wajah perempuan itu di tengah lampu yang remang.
"Tadinya aku gak setuju tapi kenyataan memang selalu menang, baru aja aku sampai eh dompetku hilang dicopet orang," Perempuan itu tersenyum tragis.
Komplikasi.
"Yang tadi siang dicopet?"
"Iya, kamu tahu?" Juang hanya berdeham karena sedikit malu tak membantu.
"Aku boleh minjam uangmu dulu tidak, untuk beli makan."
Resolusi.
Semuanya memang sesuai alur yang ia tebak, perempuan itu datang padanya untuk meminta bantuan, seperti itu dan selalu begitu. Juang mengalihkan pandangannya pada deretan bus yang terparkir di lapang sana. Tak langsung menjawab, memberikan kesan yang membingungkan bagi lawan bicaranya yang menunggu kepastian. Juang menginjak puntung rokoknya dan bangkit.
"Ini, gak usah minjem pake aja lagian kapan lagi kita ketemu. Uang ini buat ongkos pulang, di sini enggak aman buat cewek." Ia memberikan sedikit uangnya lalu berlalu. Namun belum jauh melangkah, tangannya ditahan perempuan itu.
"Aku boleh nginap di tempatmu?" Juang terkejut dengan pertanyaan itu, ia melepaskan pegangan perempuan tadi.
"Udah gue bilang pulang, gak ada yang lebih baik di tempat ini."
"Tapi aku udah janji sama Ibu, mana mungkin aku pulang dengan tangan kosong. Aku janji satu hari aja, aku bisa ganti dengan nyuci baju kamu atau apapun yang bisa aku lakuin."
Juang memejamkan matanya, memang benar kalau kita memiliki niat membantu orang kita juga harus siap untuk direpotkan kedepannya. Ia menggaruk kepalanya yang tak gatal.
"Gak, terserah apapun urusan lu tapi enggak dengan ikut gue." Ia langsung meninggalkan perempuan itu tanpa menatapnya.
Perjalanan pulang malam ini banyak menimbulkan dilema, ia terus memikirkan perempuan tadi. Kesal namun kasihan, selalu seperti itu. Tapi ia tak mau terus menjadi solusi dari banyak masalah orang, apalagi saat ia masih hidup di jalan. Banyak sekali orang yang telah ia bantu dan itu malah membuat dirinya kehabisan waktu untuk dirinya sendiri.
Memasuki gang tempat indekostnya, ia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Ini sudah tengah malam, ia bersiap jika orang di belakangnya itu berniat jahat padanya. Juang masih berjalan walau rasa was-was menghantui pikirannya. Jarak gang dengan indekostnya memang jauh, itu bukan gang utama menuju indekost berlantai tiga yang setiap ruangannya kecil dan sedikit kumuh namun harganya paling cocok dengan dompetnya saat ini. Ada barang ada harga. Juang harus masuk lagi ke gang lain lalu gang berikutnya sampai masuk ke gang kecil yang ukurannya pas dengan tubuh kurusnya.
"Hei cantik, mau kemana nih, sini sama abang aja biar anget." Kata itu terlontar bersamaan dengan siulan dan tawa dari pos ronda membuat dirinya menyeritkan dahi, apakah orang-orang itu menganggap dirinya seorang perempuan?
Namun, Juang salah. Setelah mengabaikan omongan dan sedikit menjauh dari pos ronda itu, teriakan terdengar dari arah belakang. Ia langsung membalikkan badan dan berlari saat melihat perempuan yang berada di terminal tengah menjadi sasaran para laki-laki hidung belang.
"Bangsat!" Emosinya menggebu tak tertahan, sebuah pukulan keras mengenai wajah salah satu dari mereka.
Juang juga salah langkah, ia langsung mendapat balasan dari pria lainnya. Pukulan mendarat di pipi dan perutnya yang langsung membuatnya jatuh, ia merasakan asin di sudut bibirnya, teman dari pria itu menyusul menendang kakinya. Dengan rasa ngilu dan sakit di sekujur tubuhnya ia sekuat tenaga bangkit dan berniat melarikan diri, tak ada peluang melawan mereka, tangannya menghalang kaki-kaki kejam itu dan segera menarik tangan perempuan yang sedari tadi menangis sambil berusaha mendorong pria-pria yang mengeroyoknya.
...
Hening. Sepanjang perjalanan itu hening, hanya ada angin malam yang berlalu membuat tubuhnya mati rasa. Kini perempuan terminal tadi ada di sampingnya, memboyong tubuhnya, terkadang perempuan itu sesegukan menangis pelan lalu mengusap air mata dengan punggung tangannya. Ujung bibirnya yang terluka terangkat sedikit, selalu berakhir seperti ini setiap dirinya membantu manusia lain.
"Lu ngikutin gue dari tadi?" Juang membuka pembicaraan.
"Maaf, ini salahku, aku bener-bener gak tahu kalau berakhir kaya gini, nanti aku obatin kamu di rumah kamu, aku gak maksa nginap aku di luar aja gak apa-apa. Sekali lagi aku minta maaf," Perempuan itu kembali menundukkan wajahnya.
"Jangan nangis, lu harus kuat kalau mau menetap di sini."
"Maaf, aku harus kaya gimana biar kamu maafin aku."
"Sebenernya gue kesel, lu nyusahin dari awal. Gue cuma minta lu gak usah minta maaf terus, udah kejadian."
Juang dan perempuan itu masuk ke dalam indekost yang lumayan ramai, berbeda dengan kebanyakan tempat lain, indekost ini memang sejak awal tidak menawarkan kenyamanan. Bebas, tidak ada aturan, berisik dan bermacam bentuk orang keluar dan masuk. Lantai pertama adalah lantai sedikit normal karena diisi oleh keluarga-keluarga kurang mampu dengan sebagian pekerjaannya kriminal. Lantai dua, dimana indekost Juang berada, tetangganya kebanyakan pekerja malam, baik itu wanita, pria atau waria, ini juga alasan kenapa dirinya memilih di lantai dua karena malam hari akan terasa sepi. Dan terakhir lantai tiga, selalu berisik dan membuat kesal karena penghuninya pembuat onar, judi, minuman keras, dan kekerasan sudah menjadi rutinitas di lantai tiga.
Sejak mengetahui lingkungan tempat tinggalnya, Juang memilih menjadi orang yang tak peduli dan menutup mata. Tak hanya ia tapi semua penghuni indekost ini, lagipula mereka disatukan juga dengan permasalahan yang sama, yaitu ekonomi.
"Ey Mas Juang kenapose itu mukanya begindang?" ucap Mice tetangganya yang sudah pasti bersiap mangkal. Menurut Juang, Mice adalah tetangganya paling baik dan waras di sini.
"Pergi Mice? Tumben mepet pagi,"
"Iya nich, soalnya eike lagi gak enak body, kalo butuh obat bawa aje di kamar eike. Eh ini sape cakep bener?"
"Bukan siapa-siapa, yaudah gue masuk dulu Mice,"
"Siapa apose siapa, yaudah eike capcus dulu ya, bye." Mice meninggalkan mereka berdua dan suasana kembali sepi.
Juang memperhatikan wajah perempuan itu yang terlihat shock," Jangan kaget, hal kaya gitu bakal banyak lu temuin dan jangan sok suci, dia sama kaya lu kok sama-sama nyari duit." Kemudian keduanya masuk ke dalam ruangan yang jauh dari kata besar.
"Lu mungkin kaget dengan banyak hal yang baru terjadi hari ini, tapi bersyukurlah lu udah disuruh kuat dari hari pertama. Gak ada yang enak layaknya yang sering lu sebut rumah, gak ada yang aman seperti orang tua yang selalu lindungin lu," ucap Juang sambil bersandar pada tembok, ia melihat perempuan itu menjadi diam tak seberani yang ia lihat di terminal.
Juang bangkit, ia mau merebus air untuk membersihkan luka-lukanya, belum sempurna Juang menyeimbangkan tubuhnya, perempuan itu menahannya.
"Mau apa? Kamu bisa suruh aku." Juang memejamkan mata.
"Tolong rebus air." Perempuan itu mengikuti perintahnya.
"Nama lu siapa? Dan darimana?"
"Namaku Ratih dari Solo. Kalau kamu?"
"Oh, Juang." Kembali sunyi, mereka hanyut dengan pikirannya masing-masing. Perempuan bernama Ratih itu langsung membersihkan luka tanpa mengobatinya karena tak tersedia obat di ruangan itu.
"Lu boleh tinggal di tempat gue untuk sementara,"
"Aku cuma numpang sehari aja Juang, esok aku bakal cari tempat,"
"Gak semudah itu, Tih. Atau lu pulang aja,"
Ratih menggelengkan kepalanya."Aku usahain."
"Terserah. Emang enggak ada yang lebih baik dimana pun lu tinggal, tapi percayalah lu bakal tetep hidup walau enggak makan dan cuma minum air keran."
"Aku percaya sama kamu Juang," Kini Ratih sedikit lebih percaya diri.
"Jangan nyerah, mungkin besok akan lebih parah dari ini. Gue yakin dengan pilihan lu ke sini, lu bisa melakukannya."
"Makasih Juang. Satu hal yang paling aku syukuri adalah bertemu kamu."
"Tapi semuanya gak gratis, air yang lu rebus itu butuh satu rit narik angkot, sekali lagi gue bilang, enggak ada yang enak di sini,"
"Gak apa-apa, aku janji semuanya bakal aku bayar kalau aku udah dapat kerja," Tatapan Ratih sedikit bersemangat.
"Janji, harus dibayar di muka dan tuntas."
"Kamu tetap orang baik walau perhitungan, makasih Juang."
Mereka saling bersandar di tembok dan terjaga menunggu mentari menampakkan diri. Waktu tak membiarkan mereka terlelap barang sedetik pun, jauh dalam berisik di kepala masing-masing, sama-sama memikirkan bagaimana mereka bertahan hidup esok hari, bagaimana mereka dapat mengisi perut yang kosong setelah seharian bekerja keras yang terkadang upahnya tak sebanding dengan keringat penuh harap. Mulai esok mereka akan sama-sama tenggelam membelah bilangan ganjil dan genap pada kalender untuk tujuan yang sama, menuntaskan perjanjian persekot.
...
0 notes
Text
II. [1] Rentan
Tak akan ada yang pernah tahu dan tak akan ada keputusan pasti perihal hidup. Manusia hanya sebuah anyelir dalam genggaman yang akan layu dalam tiga hari ke depan. Segala rencana yang sulit ditentukan pada sepertiga malam adalah randa tapak malang yang tumbuh saat musim hujan, tak pernah benar-benar tumbuh, berharap tegar dan indahnya sekadar angan-angan belaka. Terangnya lampu di tengah ruang makan itu menjadi saksi dimana kedua insan yang sama-sama berusaha mengikis rasa canggung yang malah kian menggunung. Kedua bibir itu terkatup rapat, tak ada celah, tak ada suara apalagi sebuah bincang. Sorot mata keduanya bergerilya mencari objek yang dapat dipandang agar mereka tak dapat bersitatap.
Pria itu beberapa kali kedapatan mengatur napasnya sambil memejamkan mata, seandainya denting jam yang menggantung di atas pintu itu membisu mungkin akan terdengar jelas bagaimana jantungnya hebat berdetak. Si wanita pun masih betah menunduk, menatap piring yang memantulkan cahaya dari lampu di atasnya, pria di depannya terkadang memergoki wanita itu menggigit bibirnya frustasi. Ini bukan pertama kali mereka bertemu juga bukan pertama kali mereka membisu, banyak malam yang telah mereka lewati bersama juga banyak pagi yang mewakili perpisahan mereka. Dan malam ini adalah puncak pertanggungjawaban, bagaimana mereka akan mengambil keputusan dari berisiknya beradu mulut, bagaimana mereka memihak dari banyaknya membandingkan dan bagaimana akhir dari mencari jalan tengah. Tak ada jalan keluar juga jalan tengah, mereka masih konsisten hilir mudik dengan pikirannya masing-masing kemudian hening, fajar semakin mengikis malam dan lampu dimatikan, keduanya berjalan beriringan pergi tidur untuk sama-sama berpisah esok pagi, namun malam tak akan terulang lagi. Dan itu keputusan.
...
Pernahkan kamu lupa jalan pulang?
Bukan pulang pada sebuah bangunan, namun berteduh pada seseorang. Mobil hitam yang terus dirindangi rintik hujan itu berhenti di pinggir sebuah jalan besar yang menghubungkan kota perantauannya dengan kota yang akan ia tuju. Kemudi malah menjadi tumpuan kepala yang semerawut berantakan, jauh dalam batin pengemudi itu menerka akankah hari ini adalah waktu yang tepat untuk pulang atau haruskah ia menunggu lagi jalan pulang lainnya. Tapi kapan, saat kabar duka datang atau saat kehadirannya dibutuhkan?
Sore hari setelah semua barangnya terkemas rapih, Sewindu yang semalaman mempersiapkan kepercayaan dirinya berjalan menelusuri gerbang tempat tinggal sementaranya. Tak ada kata pamit atau kata sampai jumpa, lagipula tak ada makhluk hidup yang ikut bersemayam dengannya di sana, ia hampa meninggalkan tempat itu. Sedari tadi siang, hujan membungkus jalanan kota yang semakin rapat oleh kendaraan karena ada beberapa tempat yang tergenang banjir. Lantunan lagu pada radio ia putar dengan selektif, khususnya untuk hari ini tak ada lagu sendu yang mendayu, hari ini semuanya harus bersorak riang, paksa pikirannya yang tak selaras pada keadaan hati.
Ribuan tempat terlewat sekilas dari jendela, mungkin tempat itu tak akan lagi ia lihat untuk hari mendatang. Sewindu menatap bibirnya yang terkatup rapat dari kemarin sore kemudian ia menarik ujung bibirnya menggunakan tangan yang lemas, tarikan napas pelan menyadarkannya bahwa pulang ini untuk keluarganya bukan untuk roman atau kisah percintaannya yang usang. Sewindu hanya seorang pemuda kesepian yang banyak memikirkan kata orang perihal percintaan.
Lampu merah memberhentikan perjalanannya sebentar, saat itulah pengamen yang berteduh di pinggir jalan mulai bekerja membawa alat mereka. Sedikit rasa syukur menggenggam hatinya karena ia tak perlu seperti mereka yang tangannya kebas untuk sepeser uang receh. Netranya menangkap sosok kecil di trotoar yang menunduk sambil menggenggam gitar yang sudah tak berbentuk, ia kembali bernapas, mengapa semua objek yang ia lihat hari ini membuatnya menjadi orang yang mudah terbawa perasaan. Lampu berubah hijau, perjalanannya pun berlanjut.
...
"Windu pulang." Suaranya menggema diantara kidung puji-pujian dari musola, menandakan sebentar lagi malam tiba. Seorang perempuan baruh baya yang tubuhnya tertutupi kain mukena menghampiri dirinya dengan wajah sukacita, hal tersebut tentu membuat hati Windu menghangat. Sebuah pelukan langsung ia dapatkan setelah beberapa tahun lamanya hanya menjadi angan-angan saja. Windu perhatikan wajah Mamah yang kulitnya semakin terkikis waktu, perempuan itu sudah banyak melewati masa.
"Sudah makan?" Lagi-lagi pertanyaan yang tak pernah berubah.
Kedatangannya membuat meja makan terasa ramai, Papah yang barusan baru pulang dari musola kini menanyakan banyak hal kepadanya, belum lagi hadirnya Kakak dan Kakak iparnya.
"Sombong banget kamu Win, tak pernah pulang. Mungkin kalau kerjamu tak dipindahkan kayaknya udah lupa sama kita," Kalimat tersebut datang dari mulut Kakaknya.
"Sibuk, enggak ada waktu. Sekalinya libur buat istirahat."
"Dasar budak kapitalis!"
Perkataan Kakaknya memang benar adanya, selama ini Windu hanya fokus mengejar karirnya. Bukan tanpa alasan, Windu sudah merasakan dimana uang adalah solusi dari banyaknya masalah. Maka dari itu Windu harus melakukan banyak hal di usianya sekarang agar nanti ia tak kesusahan seperti yang pernah ia alami sebelumnya. Walau pada kenyataannya hal tersebut banyak merubah dan membuat dirinya lupa bagaimana Sewindu dulu bersikap.
...
Malam mulai larut tapi Windu masih betah mengesap sebatang rokok di jendela kamarnya, asap rokok mengepul bercampur dengan angin malam. Perhatiannya penuh pada rumah di depan sana. Tanpa sadar sebuah motor datang dari arah kanan dan berhenti di teras rumah yang sedari tadi ia perhatikan. Sewindu terkejut saat ia melihat jelas paras wanita yang tadi ada dalam boncengan motor, ia semakin menyorotkan pandangannya pada dua orang yang sedang berpamitan di bawah sana, ia sampai melupakan rokok yang ada di sela-sela jarinya.
Wanita itu Asa, namun Sewindu tak langsung mengenalinya. Wanita itu semakin dewasa dengan tak banyak perubahan fisik karena Windu masih tahu itu Asa, tapi bukan Asa-nya Sewindu. Penasaran dan sedikit kecewa memenuhi hatinya, rasanya seperti menyadarkannya akan memiliki sesuatu yang sudah lama ia lupakan namun saat sudah menemukannya hal itu sudah bukan miliknya. Sekarang Sewindu mengalihkan perhatiannya pada sebuah gitar di atas meja belajarnya, ia tersenyum kecil mengingat sudah lama ia tak memainkan gitar itu setelah masa pendewasaannya di Ibukota. Rokok yang masih mengepul itu disimpan dalam sebuah asbak, jari-jarinya mengalun pelan menciptakan irama dari lagu yang akhir-akhir ini sering ia dengarkan.
Di suatu waktu seperti hari ini
Kupandangi dirinya dan kusedih
Kulihat ada sesuatu di sana
Sesuatu di saat dia pandangi langit
(Bintang Kosong-Nugie)
Sebait lagu belum tuntas sebuah panggilan dari bawah sana menginterupsi fokusnya.
"Kak Windu!" Asa memanggilnya sambil tersenyum manis.
...
Di ujung malam pada bulan sembilan tepat di bawah awan yang sempurna menghitam tanpa kehadiran lautan bintang, Sewindu bersulang atas segala anyelir yang memabukkan pada malam-malam dahulu. Asa berada di sampingnya, wajahnya menguning tersorot lampu jalan. Di antara sadar dan lelap, ia dapat melihat seseorang yang hanya menjadi panduan sunyinya selama ini. Selepas panggilan itu, Asa menyambutnya hangat, mereka berbincang sebentar dan wanita itu mengajaknya jalan mencari makanan.
"Kenapa kak? Ada yang aneh ya di wajahku?" tanya Asa karena sadar terus ditatap Sewindu.
"Eh enggak, Sa. Aku cuma masih kaget lihat kamu udah gede," balas Sewindu yang masih berusaha memalingkan pandangannya.
"Masa kecil terus sih kak, Kak Windu juga sekarang kelihatan tambah dewasa."
"Kelihatan dewasa apa tua nih?"
"Dewasa kak, ya walaupun beda tipis." Kemudian keduanya tertawa, melupakan waktu yang masih menjadi sebuah tanda tanya.
"Kak Windu jarang pulang sih, jadi gak tahu kan gimana aku tumbuh sampai segede ini,"
"Walau begitu aku masih ingat kamu loh, Sa. Anak kecil yang pernah nem-" Asa langsung menutup mulut Sewindu dengan tangannya, pipinya bersemu merah.
"Jangan cerita itu, aku malu kak," pintanya dengan wajah memelas. Sewindu hanya membalasanya dengan tawa mengejek.
"Tadi itu siapa Sa, yang anterin kamu?"
"Itu Kak Juna, pacarku."
Sewindu sama sekali tidak terkejut dan tebakannya benar,"Dih, anak kecil udah punya pacar."
"Katanya udah gede, gimana sih. Lagian Kak Windu emang gak punya pacar?"
"Tergantung."
"Kok tergantung?"
"Kalau kamu mau jadi pacarku ya berarti punya, kalau enggak ya jawabannya pacarku masih on the way,"
"Yaampun masih aja sering gombal, Kak Windu memang enggak berubah."
Iya, Sa. Kalau didekat kamu.
Mungkin Asa-lah yang menyelamatkan Sewindu dari kehilangan arah atas dirinya sendiri. Bagaimana ia dan Asa bercerita banyak hal saat dahulu, Asa sangat mengenal dirinya lebih dari yang ia ketahui sendiri. Perbincangan itu tak mempunyai ujung, keduanya terus bertukar cerita yang tak orang lain tahu dan tak mau orang lain tahu. Beberapa gelas teh hangat yang terus diisi ulang juga satu malam di kota tempatnya pulang tak begitu buruk pikir Sewindu. Ketika Asa pergi membawa makanan terakhir mereka, layar ponsel Asa yang masih menyala sedikit mengundang perhatian Sewindu.
Kak Juna besok gak perlu jemput Asa ya. Aku besok pergi sama Papah.
Kening Sewindu mengerut, ia memang mengajak Asa berangkat bersama, namun wanita itu belum kunjung menjawab.
0 notes
Text
[13] Satu Yang Tak Bisa Lepas
Tubuh itu bergetar hebat diikuti dengan kursi yang didudukinya ikut terguncang, matanya ia pejam secara paksa menimbulkan kerutan di dahi yang telah dipenuhi keringat dingin, tangannya menggenggam tangan lainnya bermaksud menguatkan. Giginya ia gertak dengan keras, napasnya tak beraturan, suara berisik timbul dari bibirnya yang kini sudah memucat. Orang-orang disekitarnya hanya melihatnya ingin tahu lalu pergi dengan abai, bahkan orang di meja sebrangnya memotret tubuh itu tanpa permisi kemudian tertawa pelan.
Tentang Dian
Sebuah suara menyapa telinganya bersama hembusan angin yang menerpa wajahnya. Sekarang bibirnya yang jadi korban gigitan, suara napasnya terdengar jelas akibat dari napas yang semakin tak beraturan, air matanya menetes di antara kerutan paksa di kelopak matanya. Tiba-tiba sebuah pelukan datang dari arah sampingnya.
"Jangan takut Dian, aku ada di sini sama kamu," ucap seseorang itu yang malah membuat pemuda bernama Radian itu semakin kencang menangis.
"Pergi! Sana pergi jauh," teriak Radian sambil melepaskan tangan yang memeluknya. "Lu tuh gak nyata! Bisa gak sih bikin gue tenang sekali aja, gak usah datang lagi dan seolah lu tuh masih hidup."
Dengan teriakkan dan tangisannya itu, Radian sukses menjadi pusat perhatian orang-orang. Radian sadar dengan semua aksi yang ia lakukan di tengah keramaian ini, tapi ia sama sekali tidak dapat menahan semuanya, ia kehilangan kontrol akan dirinya sendiri. Mungkin esok hari sosok Radian dengan kegilaannya ini akan menjadi bulan-bulanan masyarakat di sosial media karena ia yakin orang yang berbondong-bondong melihat hanya menjadikannya bahan hiburan semata.
...
Enam bulan yang lalu.
Aku masih di sini Alin, menanti harap yang yang sudah pasti tak tergapai. Di bawah pohon cemara yang akarnya semakin tua dimakan masa. Akar itu meliuk membentuk pangkuanmu yang sering kali menjadi sandaranku kalau hujan tengah menimpa hariku.
Malam ini juga hujan Alin, langit benar-benar menghitam karena tak seorang pun menemani rintik yang semakin deras berjatuhan. Kilat petir dengan gemuruhnya tak ingin nampak, menambah kesan pilu pada diriku yang malam ini masih diam terbujur kaku di depan jendela kamar. Aku terus mengalihkan pandanganku ke ujung jalan yang sepi di bawah sana, barangkali kamu datang dengan payung kuning kesukaanmu, melukiskan secarik warna pada bumi yang malam ini meringkuk sendu.
Apa kamu tahu Alin? Kabar hilangnya pesawat di penghujung bulan Oktober itu membawa papahku pulang dan kembali pergi. Papahku Alin, yang kamu cintai atau mungkin sempat kamu cintai. Yang kau pilih sore itu di bawah pohon cemara yang pucuknya ramai bersenandika. Aku kira sore itu kamu mau menggenggam kembali tanganku yang sedikit dingin karena beberapa hari kebelakang kau tak kunjung menemuiku lagi, tetapi nyatanya kamu mengucapkan kata-kata yang masih lekat dalam ingatanku.
"Dian maaf," ucapmu sore itu sambil menundukkan wajah cantikmu. Aku tak langsung menjawab, memalingkan pandanganku ke arah lain berusaha menyeka air mata yang memaksa mengalir.
"Kenapa?" tanyaku dengan suara parau.
"Aku tak punya pilihan lain selain itu, aku juga punya mimpi sepertimu."
"Mimpi? Dengan menghancurkan keluargaku?" kataku dengan emosi yang meradang, aku lihat kamu juga ikut tersulut.
"Udah aku bilang, aku gak punya pilihan lain selain menerima ajakkan papahmu. Aku ini bukan orang yang berada, enggak sepertimu Dian yang bisa dengan mudah mendapatkan apapun yang kamu mau." Kini aku dapat melihat wajahmu dengan jelas, tapi rasanya memuakkan.
"Tapi Lin ini tuh jalan yang salah! Masih ada cara lain yang bisa aku bantu."
"Cara apalagi? Aku juga berusaha di sini, aku enggak semata-mata melakukan hal ini Dian."
"Astaga Lin, Aku gak pernah nyangka kamu mau melakukan hal sebodoh itu." Aku memegang kepalaku frustasi. Kamu pun diam membisu dan kembali menundukkan kepala.
"Besok, aku pergi."
"Dan mulai besok jangan temui aku lagi," pasrahku sambil meninggalkanmu yang menangis tersedu-sedu di bawah pohon cemara itu.
Terkadang aku bingung dengan perasaanmu, apa kamu benar-benar menangis karena meninggalkanku atau menangis karena bimbang memikirkan mana yang lebih menguntungkan untukmu, aku atau papah.
Keesokan harinya aku berbohong Alin, aku turut mengantarkanmu ke bandara tanpa sepengetahuanmu. Kamu begitu cantik menggunakan dress merah muda itu dengan senyuman bahagia yang terpancar jelas di wajahmu, tanganmu tak tinggal diam, menggandeng tangan papahku yang gagah dengan seragamnya. Hari itu baru pertama kalinya aku menelan rasa manis dan pahit bersamaan.
Aku muak dengan rasa yang tak kunjung reda ini Alin, di satu sisi aku sangat membencimu. Rasanya aku ingin memutarkan takdir yang bersemayam dalam darahku atau membelokkan alur yang selama ini tengah berjalan. Tuhan benar-benar pandai menulis skenario kehidupan sampai aku bermimpi menjadi Tuhan. Aku telah gila, Lin.
Semenjak kamu pergi hari itu, aku jadi menutup mataku kalau melihat wajah papah di rumah. Tak ada lagi sapa hangat yang aku layangkan padanya. Kamu seharusnya beruntung Lin, karena aku tidak memberitahu ibu tentang hubungan gelapmu itu. Aku sendirian berjalan di jalan pilu ini Lin, memikul duka-duka yang malah semakin meradang dan nyatanya bukan hanya duka saja di sini, ada juga kaidah rindu di dalamnya yang semakin membuat perasaanku limbung tak tentu arah.
Seperti yang aku lihat sekarang, hujan semakin deras, langit sempurna menghitam, tak ada gemuruh apalagi rembulan. Mungkin hujan adalah bentuk iba Tuhan pada orang-orang yang patah hati dan kehilangan. Kalau saja kamu bisa terbang dan melihatku langsung di balik jendela lantai dua ini, kamu akan melihat deraian aliran air di wajahku yang pucat pasi.
Satu hari setelah kabar papah akan pulang besok, pundakku yang memang lesu semakin merunduk berbanding terbalik dengan ibu yang bersiap ke pasar membeli beragam bahan yang akan diraciknya menjadi makanan yang membuat perutku kenyang. Sering kali aku membayangkan bagaimana peran ibu digantikan olehmu jika papah benar-benar menjual hatinya, aku kembali meringis dengan jutaan ranting pohon cemara yang menusuk ulu hatiku. Aku juga mendengar kamu ikut pulang dari studimu di Ibukota sana, ada bisikkan rindu yang memaksa diutarakan kepadamu namun bisikkan itu aku tepis susah payah dengan tamengnya ibu.
Hari itu aku sedang menalikan sepatu, bersiap berangkat sekolah, di dapur tercium aroma khas masakan ibu. Kabar hilangnya kontak pesawat yang dikemudikan papah sontak membuat aku dan ibu berpandangan kaku, kalau diingat lagi hari itu seluruh sarafku seperti terputus dalam hitungan detik. Walau aku sudah terlanjur membenci papah, rasa sesak karena kehilangan itu masih tercipta di hati ini Alin. Kehilangan itu semakin terasa ketika sekelebat wajahmu terlintas di kepalaku. Kini papah benar-benar pulang bersamamu.
Beberapa hari berlalu, peti mati datang ke rumahku diikuti rangkaian bunga ucapan belasungkawa. Aku tak kuat melihat isi peti itu, ibu menjadi bisu Alin, jiwanya ikut mati dalam peti itu. Orang-orang berdatangan mengucapkan turut berduka cita. Aku yang menguatkan diri menyapa beberapa dari mereka dan menyiapkan acara pemakaman dengan kedua mata yang sembab.
"Radian, turut berduka cita. Semoga papahmu diterima amal baiknya di sana," kata salah satu kerabatku.
"Iya tante, terima kasih sudah datang."
"Kalau boleh tahu, kecelakaannya tuh bagaimana? Kok bisa sih, kan papahmu bisa dibilang udah terbiasa terbang."
"Iya Dian, kok bisa sih kaya gitu," ucap yang lainnya.
"Ih ibu-ibu gak tahu ya itu ada di sosial media penjelasannya," sambar yang lainnya.
"Tapikan itu masih diselidiki. Kita gak tahu gimana kebenarannya."
"Ibu tahu gak sih, si Mbah Kangkung pernah meramalkan ini."
"Masa sih bu, hari gini masih percaya gituan. Apa mungkin ini tuh konspirasi ya?"
Aku hanya diam saja Lin, mendengarkan celotehan asal yang keluar dari mulut orang tua sok tahu itu. Terkadang aku bertanya apa orang benar-benar datang kesini untuk turut berduka cita atau hanya ingin sekadar tahu alasan kematian seseorang dan berdiskusi di depan peti matinya. Pertanyaan seperti itu selalu aku dapatkan tidak hanya sekali dua kali, sepertinya aku adalah narasumber gratis untuk memenuhi keingintahuan mereka tanpa memikirkan keluarga yang berduka. Sepertinya sudah menjadi kebiasaan acara pemakaman menjadi salah satu tempat wawancara yang sekaligus menyediakan konsumsi.
"Radian, turut berduka cita," ucap seorang temanku.
"Turut berduka cita, Radian." Susul yang lainnya dari belakang. Baru aku mau menjawab keduanya.
"Eh Dira? Apa kabar? Udah lama kita enggak ketemu."
"Merisa? Baik nih mer, apa kabar kamu? Ih sumpah yah selesai kelulusan semuanya pada berpencar."
Aku hanya diam dan terasingkan melihat mereka yang bertukar kabar di depanku. Apa kematian seseorang juga adalah ajang reuni dadakan? Aku semakin heran Lin.
Aku masuk ke dalam rumah, figura foto papah yang gagah dengan seragamnya terpampang jelas di depan petinya. Di samping peti itu ibu menangis dalam diam sambil mendekap foto papah yang lain. Tiba-tiba flash kamera menyorotiku dan ibu disusul orang yang datang dengan keadaan tangannya memotret peti papah. Aku bisa menebaknya Lin, kecanggihan teknologi membuat orang-orang melakukan apapun demi mendapatkan ketenaran dan perhatian orang lain dengan mudah. Itu pamanku Lin, seorang jurnalis abal-abal yang selalu memotret dan membagikan segala informasi fenomenal lewat aplikasi WhatsApp yang informasinya tak pernah benar. Sepertinya kematian papah akan mendatangkannya rezeki bagi banyak orang karena kabarnya menarik untuk diperbincangkan.
Alin, setelah acara pemakaman itu orang-orang pulang meninggalkan aku dan ibu yang masih berkabung di rumah. Malamnya hujan menyerobot berdatangan membasahi tenda yang belum dirapikan. Papah sudah kembali ke bumi setelah lama mengudara. Ibu masih diam mendekap foto papah di ruang tengah. Aku berdiam kaku di kamar sambil bulak balik menyuruh ibu beristirahat. Lampu dirumahku rasanya meremang dan sunyi ikut bertamu melewati pintu depan yang belum tertutup karena menunggu tukang yang membereskan tenda.
Padahal Lin, biasanya aku sering berdua dengan ibu, tapi suasana ini terlalu asing dan menyesakkan. Bayang-bayang papah masih lekat di kepala ini Lin, ikatan batin yang menjalin ini memang susah untuk diputuskan. Bahkan aku lupa dengan kabarmu yang sudah ditemukan atau belum, yang sudah berpulang atau masih mengawang.
Tiga hari setelah kejadian itu, ibu masih belum beranjak dari sana. Dapur masih sepi dari peradabannya. Aku hanya memakan mie instan karena hanya itu yang dapat aku masak sambil sering kali membujuk ibu memakannya juga. Kakiku masih lemas digerakkan Lin. Aku masih belum kembali hidup seperti sediakala.
Hujan terus mengguyur rumahku setiap malam dengan aku yang menatapnya di balik jendela kamar. Belum satupun rembulan menemuiku setelah papah berpulang. Aku masih berharap kamu hidup dan bertamu ke rumahku, biarlah kedatangan itu bukan untukku, tapi untuk papah.
Setiap hari aku berharap, semakin lama juga wujudmu nyata. Aku sering melihatmu berlalu lalang kebingungan di depan gerbang rumah. Entahlah itu kamu atau bukan tapi yang jelas aku semakin gila Lin.
...
Radian terbangun dari tidurnya yang lelap, ia memandangi keadaan ruangan yang sekarang terang benderang dengan beberapa lampu yang masih menyala. Ia menatap ke arah pinggir, tirainya masih tertutup. Ia merenggangkan badannya dan bangkit duduk. Radian mengingat percakapan panjangnya dengan seseorang di balik tirai itu kemudian ia tersenyum. Senyum itu tak memudar sedetik pun saat ia meraih kertas di meja samping tempat tidur.
'Lin akhirnya aku berhasil menuliskan takdir seseorang, Ruth benar-benar hidup! Sekarang aku sudah menjadi Tuhan.'
2 notes
·
View notes
Text
[12] Rumah Untuk Ruth
⚠Cerita di bawah mengandung konten kekerasan seksual dan gangguan mental⚠
...
Sebuah tangan merengkuh tubuh mungilnya dari belakang lalu mendekapkan kepalanya pada dada yang bidang, tangan yang lainnya mengusap pelan pipi Ruth yang memerah. Ruth memberontak ketika bibirnya dikecup lembut oleh pria tua di hadapannya. Namun sia-sia karena sekarang badannya lemas tak bisa digerakkan ketika tangan bajingan pria itu memegang alat kelaminnya secara kasar. Air mata Ruth mengalir seiring dengan tubuhnya yang telanjang, digerayang bebas oleh pria tua itu, Ruth mencoba berusaha meminta tolong tetapi suaranya habis dikerongkongan. Raut wajah yang tadinya riang karena diiming-imingi mainan kini berubah menjadi raut takut tak berkesudahan. Sentuhan menggelikan dari gesekkan badan pria itu dengan tubuhnya membuat Ruth menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah, pria tua itu malah tersenyum kemudian melepaskan semua pakaiannya.
Pintu hotel itu terbuka lebar dan menampilkan sosok laki-laki dengan wajahnya yang terkejut, Ruth yang tadinya pasrah dibawah kungkungan pria tua sekarang kembali memberontak dengan sisa tenaganya berharap laki-laki itu menolongnya. Namun, hari itu keberuntungan tidak berpihak pada Ruth karena laki-laki itu malah ikut bergumul bersama pria tua menjamah tubuhnya. Kedatangan pria itu malah membuat keadaan semakin menyakitkan, tangannya diikat di atas kepala. Syal rajut kado ulang tahunnya kini dipakai untuk membekam mulutnya yang berteriak. Beberapa detik kemudian rasa sakit semakin tidak bisa ditolerir ketika sebuah benda dipaksa masuk kedalam bagian bawah tubuhnya, sambil sesekali tangannya disunduti rokok yang asapnya pekat mengepul seperti nasibnya ke depan.
Ruth terbangun dari tidurnya, keringat bercucuran di balik baju tidur bersamaan dengan napasnya yang tak beraturan. Ia memegang dadanya yang terasa sesak, bayangan menakutkan itu kembali menghantuinya bahkan saat ia tertidur. Ruth mengusap wajahnya secara kasar kemudian memijat dahinya pelan. Cahaya matahari menembus kamarnya yang bernuansa warna-warni, sepotong roti dan segelas susu sudah tersedia di meja belajarnya dengan sebuah note yang menyatakan semua orang rumah sudah pergi beraktivitas di luar sana, menyisakkan Ruth dengan dunianya di rumah.
Alarm dari ponsel mengejutkan Ruth yang masih mengatur napasnya. Sebelum bangkit dari tempat tidur ia memerhatikan sekeliling kamarnya, dinding berwarna biru muda, kasur putih yang dibalut seprai merah , dan lukisan warna-warna cerah lain yang menghiasi ruangan itu. Bisa dibilang ruangan ini adalah zona paling nyaman untuknya, tak ada kegelapan, tak ada manusia apalagi pria dewasa, tak ada barang rajutan dan tak ada ketakutan yang terkadang membuat Ruth bergetar hebat dan berakhir tak sadarkan diri.
Ia bangkit dari tempat tidurnya lalu membuka lebar jendela kamar, hari ini udara tak begitu segar tapi tak apalah yang penting cuacanya cerah, cukup membangkitkan semangatnya. Setelah menghabiskan sepotong roti dan susu, ia menyiapkan peralatan melukisnya dari loker mini di ujung kamar, kalau diperhatikan ruangan ini lebih tepat menjadi ruang kelas anak TK di banding menjadi kamar seorang remaja tujuh belas tahun. Ruth pergi ke toilet untuk membersihkan kuasnya yang kemarin ia pakai. Tetapi air di toilet di kamarnya kosong. Tangannya berkeringat dingin memikirkan dirinya yang harus keluar kamar, ia takut, benar-benar takut kalau harus meninggalkan ruangan ini. Dengan bimbang ia meraih gagang pintu, setelah dipegang ia kembali melepaskannya. Di kepalanya ia terus meyakinkan kalau di rumah ini hanya ada dirinya seorang dan berusaha menepis ketakutannya. Pelan-pelan pintu terbuka dengan mata Ruth yang ikut mengintip. Lenggang dan sunyi yang Ruth lihat pertama kali, langkah kecil Ruth menapaki lantai rumahnya, netranya menelusuri seluruh sisi rumah sambil berjaga-jaga. Sampai di kamar mandi ia langsung mencuci kuasnya, baru Ruth tersenyum memandangi kuasnya yang sudah bersih, suara seorang pria mengagetkannya dari ambang pintu kamar mandi.
"Ruth?" tanya pria itu dengan raut wajahnya yang terkejut.
Kaki Ruth melemas kemudian terjatuh karena tak kuat menompang badannya, kuas yang ia pegang tadi sudah hilang dari genggaman dan digantikan dengan cengkraman kuat yang membuat tangannya memerah. Mata Ruth terus terpaku pada pria di ambang pintu, napasnya mulai tak beraturan. Saat pria itu melangkah, ia langsung melemparkan sembarang barang yang ada di dekatnya pada pria tersebut lalu bangkit dan pergi berlari tergesa-gesa dengan tubuhnya yang masih bergetar. Pintu kamar ia tutup dengan kasar dan menguncinya, Ruth menangis histeris dan meneriakkan kata-kata tak jelas kemudian berlalu lalang mengacak-acak semua barang di kamarnya. Cat warna tumpah di mana-mana bahkan mengenai pakaian Ruth, cermin dan semua barang yang terbuat dari kaca pun pecah berserakan melukai kakinya. Pintu kamarnya diketuk keras dari luar membuat Ruth semakin tidak terkendali membenturkan kepalanya ke dinding.
"Sayang! Ini mamah buka pintunya, nak," teriakan mamahnya di balik pintu membuat ia menghentikan kegiatannya. Ruth melirik ke arah pintu yang berusaha di buka paksa, ia berjalan pelan meraih pecahan kaca di ujung ruangan. Ketukan pintu semakin mengeras begitu juga dengan kepala Ruth yang semakin berisik dan berantakan, pecahan kaca itu menembus tangannya, mengeluarkan cairan merah kental yang mengantarkannya pada sebuah rumah.
...
Rumah Ufuk Selatan
Tulisan yang ia lihat melalui jendela ruangan yang sekarang ia tinggali. Sudah tiga hari ia berada di tempat ini sendirian dan sudah tiga hari juga ia hanya menatap tulisan itu. Setelah kejadian beberapa minggu yang lalu, orang tuanya sepakat membawa Ruth ke tempat yang aman menurut mereka padahal Ruth sendiri tak tahu rasa aman itu seperti apa. Menurut Ruth, di dunia ini tak akan ada namanya tempat aman kalau masih ditempati manusia. Ruth benci dengan seonggok daging yang hidup kesana kemari untuk memenuhi kepentingannya sendiri yang dinamakan manusia itu, termasuk dirinya sendiri. Rasanya sesak jika Ruth melihat orang lain begitu juga ketika ia mengetahui dirinya masih bernapas dan harus menjalani hari-harinya.
"Selamat pagi Ruth, gimana tidurnya semalam, nyenyak gak? Ini sarapanmu dihabiskan ya," ucap seorang perempuan sambil membawa nampan. Perempuan itu Mbak Anna yang selalu mengantarkan sarapan dan kebutuhan lainnya ke kamar Ruth.
"Pagi Mbak Anna," balas Ruth singkat.
"Akhirnya kamu balas ucapanku juga, Ruth ini ada titipan dari seseorang."
"Dari siapa?"
"Mbak pun gak tahu itu dari siapa tapi di sana tertulis nama kamu. Terima aja dulu mungkin sewaktu-waktu kamu butuh."
"Makasih."
"Sama-sama, Ruth," kata Mbak Anna yang kemudian pergi dari ruangan.
Ruth memegang benda titipan itu, satu buah buku dan pulpen. Ia membolak-balikkan mencari nama pengirimnya tapi buku itu masih baru dan bersih tanpa tulisan apapun. Ia hanya menyimpan buku dan pulpen itu di meja samping tempat tidurnya. Ruth kembali memerhatikan setiap hal yang ada dan terjadi di tempat ini melalui jendela. Ia pikir setelah kejadian yang sering ia alami, ia akan dibuang oleh orang tuanya ke rumah sakit jiwa. Sedikit bersyukur kalau Ruth berakhir di tempat ini, walaupun ia tak tahu jelas ia berada di mana.
Suara pintu terbuka menandakan teman sekamarnya sudah pulang dari aktivitasnya. Ruth sama sekali belum tahu bagaimana rupa teman sekamarnya itu karena dari hari pertama Ruth sudah membatasi ruangnya dengan tirai yang tersedia di sana. Diam-diam Ruth memperhatikan teman sekamarnya itu, biasanya setiap malam banyak kertas berserakan di lantai dan terkadang ia dapat melihat di balik tirai cahaya kerlap-kerlip berwarna kuning, entah apa yang dilakukannya.
"Belum mau keluar dari sana?" Suara seseorang di balik tirai, perhatian Ruth teralihkan. Ia sekarang bingung mau menjawab pertanyaan laki-laki itu atau tidak.
"Jawab, enggak, jawab, enggak, jawab." Hitung Ruth pelan-pelan menggunakan jarinya. Saat Ruth mau membuka mulutnya.
"Alin kalau kamu gak mau keluar, seenggaknya kamu makan." Lanjut laki-laki itu. Ruth menghela napas, ternyata orang itu tidak berbicara dengannya. Eh tapi siapa Alin? Apa ada orang lain lagi di ruangan ini?
Ruth kembali memerhatikan lagi tulisan di seberang sana, sering kali ia membacanya tapi ia tak mengerti Rumah Ufuk Selatan berarti apa, bukannya lebih familiar dengan ufuk timur atau ufuk barat. Ia membawa buku titipan tadi dan menuliskan kata-kata itu. Rumah berarti tempat tinggal, ufuk berarti kaki langit dan selatan merupakan arah mata angin, ketiga kata itu tidak menyimpulkan apapun tapi Ruth yakin ada suatu arti di dalamnya atau ini hanya pikirannya saja yang bosan, sehingga hal sepele saja ia pikirkan.
"Nama kamu Ruth kan?" Suara laki-laki itu kembali terdengar. Ruth yang sedang mencoret bukunya berhenti sebentar, membalas pertanyaan laki-laki itu.
"Iya."
"Udah nerima bukunya dari Mbak Anna?" tanya laki-laki itu lagi.
"Oh jadi ini dari kamu?" Ruth mengalihkan pandangannya pada tirai.
"Ya gitu deh, kali aja lu bosen di kamar terus."
"Makasih."
"Radian, nama gue Radian."
Hening. Ruth bingung mau berbicara apalagi, sudah lama ia tidak berbincang dengan orang lain. Dengan terpaksa ia memutuskan pembicaraannya itu, Radian pun tidak bertanya lagi setelahnya, Ruth menulis nama laki-laki itu di bukunya. Terdengar suara pintu tertutup, menandakan Radian pergi dari ruangan ini, menyisakan Ruth yang kembali merasakan sepi.
...
Di luar langit sudah mulai gelap, tapi lampu belum juga dinyalakan, yang Ruth dengar katanya ada pemadaman serentak hari ini. Ruth sudah gelisah, keringat dingin bercucuran di dahinya, ia menenangkan diri dengan mengatur napasnya. Ia sendirian di ruangan ini karena Radian belum balik ke kamar dari siang tadi, sebenarnya setelah percakapan minggu lalu tak ada yang berubah dari ia dan Radian, tetap menjadi teman sekamar yang saling membisu. Namun, sekarang ia sangat membutuhkannya karena Ruth sangat takut gelap.
Dengan mengandalkan senter dari ponselnya Ruth masih bisa menahan semua ketakutan dan berisiknya bisikan yang ia dengar. Ia juga keheranan mengapa ia masih bisa mengendalikan dirinya di situasi seperti ini sendirian dan di tempat entah berantah. Setengah jam kemudian ia mendengar pintu ruangan terbuka dengan suara napas yang memburu.
"Ruth, maaf gue baru balik." Suara Radian terengah, sedikit membuat Ruth merasa tenang.
"Aku gak apa-apa kok," lirih Ruth.
Tiba-tiba ruangannya menjadi terang berkat lampu-lampu milik Radian. Ia dapat melihat bayangan laki-laki itu sibuk menempatkan benda dengan segala bentuk dan cahayanya.
"Nih simpen di sana." Sebuah tangan dengan benda putih bulat muncul di celah-celah tirai. Ruth mengambil benda itu dan membawanya ke kasur dan mengamati benda seperti bulan itu.
"Jangan takut, gue punya banyak lampu biar terang." Kata Radian yang dapat ia lihat bayangannya sedang duduk di kasur sepertinya.
"Kamu tahu aku takut gelap?" tanya Ruth dengan keningnya berkerut.
"Mbak Anna yang bilang."
"Oh."
"Tapi sebenarnya gue udah tahu dari tahun lalu."
"Hah? Kamu kan baru ketemu aku seminggu yang lalu."
"Alasan ini mungkin emang terlalu konyol kalau dicerna oleh akal. Gue mau nanya, apa yang lu tulis pertama kali dibuku itu?"
"Rumah Ufuk Selatan."
"Bener-bener di luar nalar. Lu percaya gak kalau takdir lu udah ditulis rapih dalam sebuah buku?"
"Maksudnya?"
"Ada seseorang yang nulis semua hal tentang lu di buku dan beberapa hal itu sama dengan kenyataannya."
"Aku gak percaya. Enggak ada manusia yang bisa nulis takdir seseorang, apalagi di dalam buku. Dian, walaupun aku kaya orang gila tapi aku gak gila beneran." Bukan mendapatkan jawaban, Ruth malah mendengar suara tangis di balik tirai itu. Tangis yang tertahan. Ruth ingin sekali menenangkan laki-laki itu dengan membuka tirainya tapi ia terlalu takut.
"Kenapa kamu nangis?" tanya Ruth khawatir.
"Kenapa lu manggil gue Dian?" tanya Radian di sela tangisannya.
"Bukannya nama kamu Radian."
"Gak, gue gak apa-apa." Suasana kembali hening, Radian masih terisak kecil di sana.
"Sekarang lu masih bertanya-tanya lu ada di mana kan?" tanya Radian.
"Bisa jadi."
"Gue juga gak tahu pasti ini tempat apa, mungkin tempat rehabilitasi tapi bukan, ya menurut gue tempat ini hanya Rumah Ufuk Selatan. Dan lu pasti baru denger dan merasa aneh dengan namanya, kan?" Tanya Radian meyakinkan.
"Iya."
"Gue gak pernah denger filosofi yang jelasnya, tapi seseorang yang gue bilang tadi pernah menjelaskan tempat ini bahkan sebelum gue datang. Mau percaya atau enggak, lu mau denger?" Radian membenarkan posisi duduknya menghadap pada Ruth dilihat dari bayangannya.
"Boleh."
"Berawalan dari kata rumah, menurut gue rumah itu banyak artinya sesuai persektif setiap orang, bahkan dalam bahasa Inggris rumah itu ada dua kata house dan home. Walau keduanya sedikit memiliki arti yang berbeda, house diartikan bangunannya dan home tempat yang ditinggali tapi kita dapat ngambil simpulan rumah, house dan home itu adalah suatu tempat yang kita singgahi entah untuk sementara atau selamanya, entah membuat kita nyaman atau kacau balau."
"Sebentar, di sini ada banyak orang kan? dan ada banyak kamar? kenapa harus rumah bukan lebih tepatnya kaya pondok atau asrama?"
"Mungkin tempat ini mempunyai harapan untuk jadi rumah buat yang tinggal di sini, karena kebanyakan orang yang tinggal di sini gak punya rumah." Ruth hanya mengangguk dan mempersilahkan Radian melanjutkan penjelasannya.
"Kata kedua ufuk berarti kaki langit atau bisa disebut juga garis pembatas antara bumi dan langit. Bumi terkenal dengan hingar bingarnya kehidupan dan langit sering menjadi tempat menyepi sama halnya dengan hidup dan mati. Dengan begitu tempat ini tuh jadi garis pembatas antara hidup dan mati, karena beberapa orang yang berakhir di sini pernah ngerasain gimana rasanya hampir mati." Penjelasan Radian sedikit membawa Ruth pada kejadian beberapa bulan yang lalu.
"Gimana? lu ngerasa terganggu dengan kalimat terakhirkan? Gue juga ngerasain itu semua Ruth walau dalam hal yang berbeda." Ruth bisa melihat bayangan Radian yang sekarang berbaring.
"Dan yang terakhir selatan, arah mata angin. Barat dan timur itu adalah tempat bumi berputar. Sedangkan selatan dan utara tempat adanya kutub. Anggap aja gini kehidupan itu berputar sama halnya dengan bumi. Tapi ada saatnya bumi pengin rehat, kemana?"
"Selatan dan utara? Karena biasanya kita butuh tempat baru untuk sejenak beristirahat," jawab Ruth yang ikut
"Bener. Terus kenapa harus selatan? Kok gak utara? Lu pernah dengerkan kalau kutub selatan adalah satu-satunya tempat di bumi yang enggak dimiliki oleh siapapun atau negara manapun. Nah tempat ini pun kaya gitu, tempat untuk kita sendiri, tempat yang gak orang lain kenal yang buat kita nyaman untuk rehat sebentar."
"Dan berakhir dengan namanya, Rumah Ufuk Selatan. Rumah singgah bagi setiap orang yang hampir mati. Ini bukan rumah sakit yang seringnya memaksa kita buat sembuh, bukan juga tempat rehabilitasi yang memaksa kita buat bercerita. Dan bukan tempat yang memberikan persektif negatif di masyarakat bagi orang-orang yang pernah singgah di sini." Penjelasan akhir Radian yang membuat keadaan kembali hening.
"Kamu juga sakit, Dian?"
"Iya, apalagi setiap ada orang yang manggil gue Dian."
"Eh, aku minta maaf. Aku gak tahu."
"Gak apa-apa, itu waktu dulu. Ruth di sini kita sama-sama berjuang melawan dengan yang bahkan kita sendiri gak tahu apa yang harus kita lawan. Suara yang berisik di kepala, bayangan masa lalu yang mengerikan dan bikin kita berakhir berdarah-darah, ketakutan yang bisa bikin kita lupa kita juga butuh hidup."
"Terus apa yang bikin kamu sembuh?" tanya Ruth yang kini sedang berbaring sama dengan Radian.
"Alasan. Dulu seseorang yang gue ceritain tadi, beliin gue buku, katanya kalau gue lagi ada harapan gue tulis harapan dan keinginan gue di buku itu dan ketika lu capek lu bisa lihat tulisan itu lagi. Tadinya susah emang tapi lama-lama harapan itu bisa jadi dorongan yang bikin gue untuk segera sembuh."
"Jadi kamu beliin aku buku, buat bantuin aku sembuh?"
"Gue cuma berusaha aja, karena sebenarnya yang bikin lu sembuh ya diri lu sendiri. Udah jam dua belas nih, gue udah ngantuk. Selamat malam, Ruth."
Ruth melihat bayangan Radian yang berubah posisi membelakanginya. Di luar terdengar suara rintik hujan yang semakin lama kian membesar. Ia membenahi posisi tidurnya sambil terus menatap bayangan Radian di balik tirai, ada rasa penasaran dengan sosok yang mengajaknya berbicara tadi. Kalau dilihat dari sini Radian memiliki ukuran badan yang lebih kecil darinya, ingin rasanya Ruth mengintip Radian atau bahkan berjabat tangan dengannya sebentar. Tapi Ruth belum benar-benar sembuh dari yang Radian sebut tadi.
Sebenarnya Ruth juga merasakan ada hal berbeda saat ia tinggal di sini, dimulai dari pengendalian dirinya, keberaniannya berkomunikasi dengan Mbak Anna dan larut dalam obrolan dengan seseorang yang baru Ruth kenal. Lama-lama mata Ruth terpejam dan tanpa sadar ia memeluk lampu bulan Radian yang membuat wajahnya ikut bersinar. Selang beberapa menit, diam-diam Radian yang sebenarnya masih terjaga meninggalkan selembar kertas di buku Ruth, kertas yang selama ini menjadi takdir Ruth dan kertas yang Radian tulis bersama seseorang.
'Ruth, Maaf.'
0 notes
Text
[11] Sorak Sorai dan Parau
Seberapa penting kah suara bagi manusia?
Entah itu suara yang dapat terdengar atau pun suara yang dapat dipermainkan seperti yang Bahtera kenal sejak kecil yaitu kotak suara. Bagi Bahtera selama dunia ini belum menemukan titik teradilnya, suara masih sangat penting digunakan namun tak penting untuk didengar. Berkali-kali sorak sorai menjadi latar belakang Bahtera tumbuh, di umurnya yang ke-lima tahun ia sudah ikut turun ke jalan melihat orang berlalu lalang berbicara bebas atau terkadang berteriak menuntut hak mereka di depan sebuah bangunan mewah yang pagarnya berduri besi.
Orasi penuh ambisi dari pria tua di atas tumpukan kayu itu menimbulkan reaksi Bahtera yang saat itu merupakan salah satu balita yang ikut aksi unjuk rasa, terdiam sebentar kemudian menangis tak nyaman. Di dalam tangisannya ia bertanya, untuk apa mamahnya siang bolong begini ikut berkumpul dengan banyak orang yang berteriak kencang pada bangunan tinggi yang pemiliknya seolah tuli dan bisu? demi keadilan, kata seorang buruh yang memberikannya sebotol air mineral di tengah hiruk piruk aksi unjuk rasa tempo itu.
Dengan bergulirnya waktu yang meninggalkan manusia tanpa jejak, bukti keadilan itu tak kunjung nyata. Bahkan beberapa buruh yang wujudnya masih lekat dalam ingatan Bahtera sudah berpulang sebelum haknya terpenuhi. Kini aksi itu telah diregenerasi oleh wajah-wajah baru dengan tujuan yang berbeda, ada yang benar mempertaruhkan haknya, ada yang ditunggangi kelompok politik tertentu, bahkan ada yang menjadikan demonstrasi sebagai pundi-pundi rupiah.
Namun Bahtera masih tetap berdiri kokoh di antara wajah palsu itu, bodo amat dengan berapa ribu uang yang sering ditawarkan sebagai imbalan bungkam. Ia tak tergiur dengan permainan kuno itu, lagian untuk apa bertahun-tahun berjuang di jalanan kalau yang ia dapatkan hanya sepeser uang yang seharusnya memang miliknya sebagai rakyat. Ya Tuhan sesusah itukah meminta pertanggung jawaban dari kematian kakaknya?
Dua belas tahun yang lalu saat umurnya menginjak lima tahun, kakak sulungnya merenggang nyawa di rumah tepat Bahtera meniup lilin angka lima. Seharusnya ia dapat mendengar riuh suara tepuk tangan yang meriah namun sayangnya kala itu sirine ambulan yang memprioritaskan nyawa kakaknya menulikan telinga Bahtera kecil yang tak mengerti apa-apa. Jerit tangisan mamah membuat Bahtera terasingkan di hari bahagiannya, seandainya saja Bahtera tak menghembuskan napas untuk mematikan lilin itu mungkin kakaknya masih ada di sini bersamanya.
Serangan jantung akibat kerja berlebihan adalah sebuah alasan kematian yang masih menyesakkan untuk diterima Bahtera dan keluarga. Bahtera selalu bertanya, apakah manusiawi menyuruh kakaknya bekerja lembur tiga hari berturut-turut hanya untuk mendapatkan satu hari cuti di ulang tahunnya. Sebenarnya luka lama itu akan lekas terikhlas kalau seandainya tidak terulangi lagi, kalau seandainya pelaku dari kejahatan itu tak bebas bermuslihat di balik meja jabatan.
...
Sebuah gas air mata dilemparkan ke arah massa, orang-orang yang tak terima itu balik menyerang dengan melemparkan batu dan menerobos pagar yang menjadi batas massa berdemo. Polisi berhamburan dari barisannya mencoba menahan massa yang membludak masuk, sesekali terjadi baku hantam dari keduanya. Bahtera melihat ke depan, seorang polisi telah mengincarnya dari tadi karena celana seragam Bahtera terlalu mencolok dengan pendemo yang lain. Ia langsung pergi dari area demo yang saat itu sudah kacau balau, gas air mata dilemparkan kemana-mana, aparat keamanan memukul tanpa ampun beberapa pendemo yang membuat kegaduhan, ban yang dibakar berserakan menimbulkan asap hitam pekat yang dapat mengganggu penglihatan dan pernapasan, Bahtera lari dengan cepat tak tentu arah mencari tempat persembunyian yang tepat untuk menghilang dari kejaran polisi. Sekarang Bahtera memasuki perumahan yang cukup jauh dari tempat demo, aparat itu masih ada sosoknya dibelakang sana. Ia melihat di ujung jalan ada satu rumah yang pagarnya sedikit terbuka, tak berlama-lama lagi ia langsung masuk ke rumah itu tanpa memikirkan pemiliknya, dari balik pagar ia dapat mendengar polisi itu berlari terus menerus tak menyadari keberadaanya.
"Ngapain kamu di situ?" tanya seseorang dari arah dalam.
Mata Bahtera terbuka lebar langsung menatap orang yang bertanya sambil mengatur napasnya. "Ikut sembunyi bang, bentar lagi juga gue keluar." Pria yang menurut Bahtera secara penampilan lebih tua darinya mengambil paksa banner bekas demo tadi di tangannya. Membaca kalimat pendek yang tercetak di sana. "Jangan dirusak bang, bikinnya mahal gue gak punya uang lagi."
"Masih kecil udah ikut demo, emang lu ngerti atau dibayar?" tanyanya meremehkan, pertanyaan itu sedikit membangkitkan emosi Bahtera.
"Kalau gak tahu apa-apa gak usah asal ngomong!" tegas Bahtera pendek, sekarang sesak menyergap tubuhnya antara kehabisan napas akibat berlari tadi atau emosinya yang tersulut oleh kata-kata pria di depannya. "Nama lu?" tanya pria itu mengembalikan bannernya.
"Bahtera, eh bang gue boleh minta minum gak?" jawab Bahtera tersenggal-senggal karena pernapasannya tak berjalan dengan baik. "Masuk," kata pria itu.
Bahtera memasuki rumah yang cukup luas namun sunyi seolah tak berpenghuni, ia duduk di sofa abu-abu di ruang tamu. Pria pemilik rumah itu pergi ke belakang rumah membawa minuman untuknya, tak ada rasa malu dalam diri Bahtera karena haus semakin menggerogoti tenggorokannya. Ia perhatikan ruang tamu sederhana bernuansa putih abu itu, menurutnya rumah ini sangat merepresentasikan kesepian, satu lampu hias yang berdiri di ujung ruangan, lukisan-lukisan abstrak yang Bahtera tak mengerti, tak ada foto manusia di bingkai foto juga tak ada tanaman yang setidaknya dapat menghidupkan suasana. Pria itu datang dari arah dapur membawa satu teko dan dua cangkir di nampannya dan kemudian duduk di sampingnya.
"Ini minum dulu." Suruhnya.
"Ini gak ada sianidanya kan?" tanya Bahtera pada pria itu sambil memicingkan matanya.
"Gak tahu diri banget sih lu, dah minum aja emangnya tampang gue keliatan kaya kriminal gitu?" omel pria itu.
"Bang sekarang penjahat itu enggak bisa dilihat dari penampilannya. Noh liat diluar sana bajunya aja rapih make dasi tapi kelakuannya lebih bejat."
"Kenapa lu ikut demo? mana bolos sekolah lagi."
"Menurut wikipedia, unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Masa gitu aja kagak tahu bang."
"Ya gue juga tahu kaya gitu mah, maksudnya tujuan demo lu tuh buat apa. Gue lihat di banner lu boikot-boikot perusahaan gitu sedangkan lu kan keliatannya belum kerja."
"Lu percaya gak sih bang kalau gue udah demo hampir dua belas tahun lamanya?"
"Dih malah balik nanya. Tergantung, kalau lu jujur menjelaskan gue percaya karena gue juga tahu keadilan di sini emang susah didapetin."
"Gue mau cerita, dua belas tahun lalu kakak gue meninggal dunia karena peraturan yang gak manusiawi. Dikira gue sehabis kejadian itu bisa bikin kapok perusahaan tersebut tapi nyatanya manusia gak seberharga itu dibanding profit, tahun berikutnya dan sampai sekarang banyak orang-orang yang senasib dengan kakak gue. Peraturan itu tetap berjalan padahal udah dilaporkan beberapa kali, massa udah bersuara, dibuktikan dengan orang yang berguguran, dan tahun ini dalang dibalik semuanya asik-asik aja nongol di papan kampanye." Tutur Bahtera.
"Nyokap bokap lu mengijinkan lu?"
"Awalnya nyokap gak apa-apa lagian dia yang pertama kali bawa gue ke jalan tapi sekarang dia selalu khawatir sama gue, pas waktu itu gue pernah pulang babak belur dihajar aparat. Kalau bokap gak tahu sih gue belum pernah ketemu dia dari kecil tapi dia sering ngirimin gue duit padahal gue gak tahu gimana bentukannya."
"Kok lu berani sih padahal bisa aja sewaktu-waktu akhirnya lu gak bisa pulang."
"Biarinlah bang, ini tuh mungkin salah satu cara gue minta maaf sama kakak gue."
"Gue setuju cara minta maaf itu banyak bentuknya tapi dunia ini gak akan menemui titik adilnya karena manusia sendiri mempunyai egonya masing-masing. Dengan begitu lu bakal memberikan seluruh hidup lu buat minta maaf, seriusan lu mau idup kaya gitu?"
"Bang lu tuh gak akan ngerti, lu bayangin kejadian ini membentuk sebuah belenggu di keluarga gue. Mamah belum ikhlas sama sekali, setiap sore dia masih sering nanyain kakak gue udah pulang atau belum atau ngamuk setiap denger sirine ambulan. Kakak kedua gue kesana kemari banting tulang buat nyeimbangin finansial keluarga karena bokap gak tentu ngirimin uang, hasil dari kerjanya pun gak banyak dan terkadang itu buat dia stres. Semuanya jadi berantakan gara-gara ulang tahun gue." Amarah Bantera mulai memuncak.
"Tapi rasa bersalah itu gak akan bisa ngebalikin keadaan, gue gak bisa bantu lu, orang lain gak bisa bantu lu, uang gak bisa bantu lu, yang bisa bantu adalah diri lu sendiri. Apa yang harus lu lakuin? berdamai dengan keadaan itu. Berlarut dari rasa bersalah itu kesalahan besar, itu cuma bikin lu bergerak di tempat walaupun lu udah berusaha melangkah sejauh mungkin."
"Terus apa yang harus gue lakuin menurut lu?"
"Hilangin rasa bersalah itu mulai dari sekarang, jaga yang sekarang masih ada, kakak kedua lu dan mamah. Selama ini keluarga lu hanya bergelut dengan masa lalu sehingga lu gak bisa natap sesuatu secara positif, coba dimulai dari diri lu sendiri karena biasanya positive vibes itu bisa nular."
"Dan mulai gak ikut unjuk rasa lagi gitu?"
"Enggak, gue cuma mau membenahi tujuan lu bukan untuk menghentikan, kalau memang harus diadili ya adili lah tanpa harus menyakiti lu."
Dalam suatu kasus terkadang mengungkapkan kebenaran untuk suatu keadilan memang menyakitkan namun kesalahan yang diketahui banyak orang dan tak kunjung diadili karena kurangnya materi lebih menyakitkan.
Bahtera mengambil cangkir air minumnya di meja, percakapan singkat yang membuat emosinya terkuras. Pria di sampingnya sekarang sedang memandangi deretan lukisan di dinding. Bahtera mengeluarkan ponselnya di saku hoodie yang ia pakai, banyak panggilan tak terjawab dari mamahnya membuat ia bersiap untuk pulang.
"Bang makasih minumnya juga makasih mau denger cerita gue. Kapan-kapan gue bakal bales kebaikan abang, gue pamit pulang yah mamah udah nelepon."
"Sama-sama Bahtera, gue juga bilang makasih karena akhirnya gue nerima tamu lagi setelah sekian lama tinggal di sini, tapi kayanya kita gak bisa ketemu lagi deh minggu besok gue pulang ke Bandung dan gak akan balik lagi kesini."
"Hidup itu lucu ya bang, baru aja ketemu dah pisah lagi. Gue duluan ya bang dah."
Bahtera meninggalkan rumah itu, ada rasa yang berbeda dalam dirinya seperti rasa lega sehabis menangis kencang. Setelah lumayan jauh dari rumah pria tadi ia kembali melihat kebelakang, ada hal yang lupa ia tanyakan, nama pria itu. Seandainya mereka memperkenalkan diri masing-masing dulu walaupun tak dapat berjumpa lagi ia bisa berkomunikasi dengan pria itu lewat media sosial. Sebenarnya ia tadi intip sebentar kertas di laci ruang tamu yang terdapat nama seseorang, Sewindu Danindra. Namun ia pikir lagi mungkin itu hanya judul lagu yang disukai pria itu.
Sebuah mobil hitam menutupi jalan masuk ke dalam rumahnya. Baru saja Bahtera mengucapkan salam, badannya membeku diikuti raut wajah terkejut. Di depannya ada seorang pria tua menggunakan kemeja khas kantor yang rapih dengan kacamata tertengger di telinganya, pria yang sering ia lihat dan yang selalu ia benci kapanpun melihatnya. Wajah dan tubuh pria itu persis dengan sosok pendamping seseorang di papan reklame kampanye.
"Bahtera, ini bapak," kata pria tersebut.
3 notes
·
View notes
Text
[10] Sulap Badut Darian
Aku, sepatu hitam yang bagian depannya menganga lebar menelusuri gang-gang sempit, banyak usaha yang aku kerahkan agar melindungi tuanku dari kotoran ayam atau benda kecil tajam yang berserakan. Walaupun terkadang, genangan air masuk menembus kaus kaki putih yang masih bersih dan menimbulkan noda hitam. Sering kali aku meminta maaf pada kaus kaki itu lalu dibalas dengan raut wajah yang sebal juga terkadang batu kecil ikut singgah di dalam yang membuat jalan tuanku tak nyaman. Setiap lima meter sekali aku dibenarkan agar lubangnya tidak semakin membesar, tanpa berisyarat sebenarnya aku pun tak enak hati kalau saat ini aku tak lagi berguna.
Sekarang aku, sepatu butut berada di Rusunawa Angsana yang menjadi tempat tinggalku selama 5 tahun terakhir, seharusnya aku sudah menikmati waktu senja di rak sepatu bukan masih berjuang ke sana kemari menemani tuanku. Namun aku mengerti, nasib baik dan buruk ku tergantung siapa yang memilih untuk membeli diri ini, setidaknya tuanku ini masih sangat menyayangiku, ia terus merawat tubuh ringkih ini dengan baik padahal aku sudah tak layak digunakan lagi.
Sulap Badut Darian, plang yang bisa dilihat oleh siapapun yang melewati lorong kecil lantai dua Rusunawa Angsana. Di sanalah aku dan tuanku tinggal, ruangangan 3x6 meter persegi bercat putih, memang tidak terlalu luas tapi aku betah menyinggahinya. Tuanku membuka tali temali yang ada pada tubuhku dengan cekatan kemudian membukanya dan memerhatikan lubang yang semakin membesar di sana, terlihat wajah murung dan helaan nafas dari tuanku. Tangannya mengelus sebentar bagian depan tubuhku kemudian aku disimpan di dalam rak yang bersih tanpa debu, semua sepatu di sini berseri karena mendapatkan tuan yang baik hati dan selalu peduli dengan tempat tinggal kami.
Dari rak ini aku bisa melihat tuanku, melakukan segala kegiatan dari yang penting sampai tidak penting. Darian namanya, laki-laki berumur tujuh belas tahun yang terkadang tertawa sendirian menatap ponselnya, yang membuat teman-temannya tertawa atas celetukkan dari mulutnya. Matanya menyipit dan tersenyum lebar setiap harinya, orang yang mengenalnya akan mengira kalau dia manusia yang terlahir tanpa kesedihan, tapi buatku yang mengenalnya, Darian tetap manusia yang menangis tersedu-sedu kalau harinya tidak baik-baik saja. Darian juga memiliki amarah disela-sela keputusasaannya.
Satu orang lagi yang menghuni ruangan ini, Abah. Sekarang ia sedang pergi menghibur anak-anak di pesta ulang tahun atau sedang berkeliling saja mencari pundi-pundi uang dari tawa anak kecil. Abah adalah bapak yang bijak dan konyol bagi kami para sepatu yang memerhatikannya setiap hari. Aku kadang tertawa kalau abah sedang berlatih sulap di rumah terlebih kalau sulapnya gagal dan ia berupaya tetap tersenyum dengan topeng badutnya. Mungkin sempitnya rumah ini tak sebanding dengan rasa syukur yang selalu terucap dari kedua penghuninya.
Aku melihat Darian keluar rumah dan balik lagi dengan setumpuk jemuran yang sudah mengering. Kedatangannya disusul dengan suara rintik hujan yang semakin membesar, bulan Januari memang saatnya hujan bersinggah di Iangit ibu kota ini, doaku semoga airnya dapat bermanfaat bagi semua makhluk yang hidup di bumi ini, tak menjadikan sebuah bencana yang terjadi setiap tahun, kasihan temanku yang lain kalau mengungsi lagi bersama tuannya atau bahkan hanyut dalam aliran air yang terjang atau tertimbun dalam balutan tanah yang hitam.
Sekarang lilin temaram menerangi sisi-sisi ruangan 3x6 meter ini, listrik mati saat petir menggelegar, aku dapat melihat Darian sedang melipat pakaian dengan gusar, tatapan khawatir ia layangkan pada pintu dan jendela sepertinya ia mengkhawatirkan Abah yang belum pulang. Aku pun khawatir karena hujan yang semakin deras ditambah kilatan petir yang membuatku ngeri, tapi Abah tak kunjung datang.
Setengah jam kemudian Abah datang dengan konstum badutnya yang basah kuyup, Darian yang sedari tadi menunggu langsung memberikannya handuk dan membantu Abah membuka konstum itu. Sering kali aku ingin ikut membantu keduanya, namun aku hanyalah sebuah benda mati yang dapat bergerak kalau digunakan. Darian memberikan Abah teh hangat dengan cangkir besar kesukaan Abah, sekarang ia sudah berganti baju menggunakan kaus santai.
"Abah darimana tadi?" Merupakan pertanyaan Darian setiap harinya.
"Tadi Abah keliling Ian, belum ada panggilan lagi dari si Bos," jawab Abah sembari meminum teh hangatnya.
"Kenapa Abah gak langsung pulang aja kalau gak ada panggilan, apalagi ini musim hujan," tuturnya sambil menatap serius wajah Abah. "Atuh Ian, kalau abah diem aja kita makan sama apa," balas Abah diselingi kekehan.
"Ian diterima kerja di bengkel Mang Iwan. Mulai hari ini Abah kalau gak ada panggilan diam di rumah, biar Ian yang cari uang," jelas Darian sambil bersandar di badan kursi. Penjelasan Darian itu sukses membuat perhatian Abah berpusat padanya.
"Kenapa harus kerja? Belajar kamu gimana? Kamu teh udah kelas 12 Ian, sebentar lagi ujian, belajar yang bener cari uang mah biar urusan Abah aja," kata Abah lembut, aku hanya hanyut memerhatikan percakapan keduanya.
"Ian gak akan kuliah, Bah. Mau langsung kerja dan Alhamdulillahnya Ian besok mulai kerja."
"Kenapa gak mau kuliah? Kamu kan rajin belajar, sayang atuh kalau ilmu kamu enggak diteruskan."
"Ian gak mau bikin susah Abah. Cukup kemarin-kemarin Ian liat Abah sesak napas pakai kostum itu keliling. Ian udah besar Bah, udah seharusnya bertanggung jawab buat Abah dan Ian sendiri." Darian bangkit dari sandarannya dan menatap balik abah.
"Apa yang kamu pikirin? Uang? Ian rezeki mah gak akan kemana. Sok aja usaha dulu nanti juga uang mah ngikutin atuh. Kamu tahu Ian apa keistemewaan manusia selain mempunyai akal? Ia bisa lihat masa depannya sendiri dari 15% usaha yang dilakukan sekarang, sisa persenannya biar jadi rahasia Gusti Allah." Aku bisa melihat abah mengusap punggung Darian penuh kasih, meredamkan amarah anaknya.
"Bah, mau kuliah atau enggak itu pilihan. Ian juga pengin kuliah tapi Ian mau mengumpulkan dulu uangnya. Ian mau Abah realitis aja dengan pekerjaan Abah yang begitu, terkadang mau makan pun susah apalagi bayar uang bulanan yang biayanya gak kecil." Darian semakin meninggikan suaranya, sampai aku lihat jam dinding menghentikan gerak jarumnya.
"Ian kerjaan Abah memang gak bisa menghasilkan banyak uang, tapi tahu gak kalau Abah begitu mencintai pekerjaan Abah. Kenapa Abah mencintainya? karena ada namamu di dalamnya, Sulap Badut Darian. Kenapa Abah menamainya begitu? Agar Abah selalu bisa membuat kamu terhibur tanpa membayar kaya orang-orang." Aku hanya memperhatikan abah yang mengusap air mata yang berjatuhan dari pipi Darian.
"Kalau itu memang itu pilihan Ian, ya sudah lakuin aja dengan sepenuh hati. Abah cuma mau titip, cintai apapun yang kamu lagi lakuin biar kamu tahu bagaimana rasa ikhlas yang sebenarnya." Tangan Darian memegang wajah Abah yang sudah banyak kerutan di dahinya kemudian memeluk tubuh abah dengan hangat dan abah pun membalasnya.
Aku juga sebenarnya ikut memeluk Abah dan Darian dari jauh. Abah dan Darian berhasil membuatku menjadi hidup, aku adalah metafora abah bagi Darian. Dengan tubuh yang tak lagi muda dan tak layak digunakan kita sama-sama berusaha untuk Darian. Sampai akhirnya kita menemui jodoh yang memang sudah kita ketahui, yaitu kematian.
Listrik tak kunjung menyala sampai dini hari, beberapa menit yang lalu suara kumandang Azan menggema dari jauh. Abah sudah siap menggunakan kostum badut yang sudah kering, kepalanya menggunakan rambut palsu berwarna-warni. Darian menyiapkan sarapan yang seadanya namun dapat membuat ia dan Abah tak kelaparan sampai siang nanti. Abah duluan pamit pergi, katanya sekarang ada dua acara ulang tahun yang harus ia hadiri. Selesai dengan berbagai persiapan, Darian membawaku dari rak, sepenglihatanku matanya sembab akibat menangis semalaman. Kemudian aku pergi bersama dengan tuanku menjelajahi jalan penuh genangan air, tak apa tuan kali ini aku akan berusaha keras melindungimu seperti Abah. Darinya aku belajar memeluk rasa kesedihan yang lama-lama akan melembut. Terima kasih tuan, sudah menemaniku dengan menelusuri banyak cerita pada sudut-sudut kota yang semakin ramai ini.
0 notes
Text
[9] Di Balik Pintu Malik
"Sekiranya punya tujuh belas tahun" Senandung seorang pria tinggi tengah mengelap kaca jendela rumahnya.
"Tujuh puluh tahun bang, bukan tujuh belas tahun. Kalau tujuh belas tahun mah umur abang." Koreksi adiknya yang sedang menyiram tanaman di dekatnya.
"Tujuh belas tahun! Segini nih satu belas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas. Kamu yang salah," ucap pria itu sambil menunjukkan ketujuh jarinya tak beraturan.
"Abang pinter sekarang udah bisa berhitung tapi gak ada angka satu belas dan di jari abang itu cuma tujuh bukan tujuh belas,” sanggah adiknya itu sambil memerhatikan pria yang lebih tua darinya sedang sibuk berhitung menggunakan jarinya.
"Enggak jari ini abang tujuh belas udah kok, di lagunya juga tujuh belas kalau banyak gajahnya akan gak cukup," balas pria itu yang masih saja menampilkan jari yang sekarang jumlahnya semakin banyak.
Perempuan dengan rambut pendek itu menghampiri kakaknya, meninggalkan selang air yang masih mengalir di antara tanaman-tanaman.
"Nih jari abang tujuh nah ditambah jariku sepuluh jadi tujuh belas. Terus di lagu itu tujuh puluh, umur gajahnya bukan jumlah gajahnya." Jari mungil perempuan itu melengkapi angka yang sedari tadi menjadi perdebatan di antara keduanya. Pria di hadapannya hanya mengangguk-angguk tanda mengerti.
Perkenalkan namanya Malik Hanafi Nugraha, tahun ini umurnya menginjak tujuh belas tahun, ia merupakan kakak laki-laki yang penuh kasih sayang dari seorang adik perempuan yang cerewet menurutnya. Malik senang sekali membersihkan rumahnya, dia juga pandai mengerjakan pekerjaan rumah seperti membenarkan lampu rumah, mengecat tembok, menjemur pakaian dan terkadang memasak. Ia tidak mengenal dunia luar karena kata ibu di luar sana banyak orang yang jahat, padahal Malik sendiri belum tahu orang jahat itu seperti apa. Namun, setiap minggu keluarganya akan mengajaknya berlibur ke rumah neneknya atau terkadang ke tempat wisata.
Malik baru pergi ke sekolah dua tahun yang lalu, sebelumnya ia hanya belajar dirumah dengan satu orang pengajar yang direkomendasikan oleh dokter terapinya. Sekolah dan rumahnya hanya berjarak satu kilometer, kata ibu agar ia dapat terkontrol dengan baik. Pergi sekolah ia diantar oleh ayahnya dan pulangnya dijemput oleh ibu tapi terkadang ibu mendampinginya di sekolah. Menurut Malik, ibunya keterlaluan baik karena membagi seluruh waktunya untuk dirinya. Pernah suatu hari Malik berbicara kepada kedua orang tuanya ia ingin pergi dan pulang sekolah sendiri seperti adiknya, ibu malah menjawab dirinya merasa bosan karena harus berdiam diri di rumah jadi ia memilih pergi ke sekolahnya yang ramai, padahal setahu Malik orang-orang banyak yang menghindar untuk mengunjungi sekolahnya.
Sekolah Luar Biasa Pelita Asih, tempat dimana Malik menempuh pendidikannya, bagaimana akhirnya ia merasakan kehadiran seorang teman, mengerti caranya interaksi dengan individu lain, mengenal banyak pengajar dengan karakteristik yang berbeda. Kalau dulu ia mendengarkan cerita adiknya tentang pengalamannya di sekolah, sekarang Malik lah yang cerewet menceritakan kesehariannya semalaman suntuk. Malik ingat jelas saat pertama kali menggunakan seragam sekolah, ia bulak balik bercermin sambil merapikan pakaiannya. Sesampainya di gerbang sekolah ia dapat melihat banyak orang berlalu lalang membuat keberanian Malik menciut, jadi ia hanya bersembunyi dibalik badan ibunya yang lebih kecil dari badan Malik. Tangannya bergetar hebat ketika Ibunya meninggalkan kelas, ia perhatikan ada tiga orang di dalam ruangan itu, mejanya dibentuk setengah lingkaran sehingga menyisakan banyak ruang, di bangku paling ujung ada anak laki-laki yang meraung kencang sambil menangis membuat meja dan bangku jadi tak beraturan, di sebelah anak laki-laki itu ada perempuan menggunakan kerudung putih polos, perempuan tersebut sedang mencoret kerudungnya sendiri dengan spidol warna-warni, dan di sebelahnya ada anak laki-laki dengan badan gemuk yang sibuk dengan kotak makannya dilihat dari samping mulut laki-laki tersebut penuh dengan noda cokelat. Malik hanya menggigit kukunya sambil bersiap kalau di antara tiga orang itu melakukan hal buruk kepadanya, ada perasaan takut yang Malik sendiri tidak tahu. Namun, tiba-tiba sebuah uluran tangan yang gemuk memberikannya sepotong brownies cokelat, melalui brownies itu terbentuklah empat sekawan dari kelas bintang.
Kata banyak orang, Malik itu berbeda. Ia merasakan itu, terlebih selalu ada perlakuan yang berbeda dari orang kepada dirinya dengan adiknya. Ia sering melihat adiknya bulak-balik pergi sendirian ke luar rumah untuk main atau sekolah. Tetapi jika ia ijin untuk bermain sepeda di luar rumah, Ibu langsung menasihatinya kalau di luar sana sangat berbahaya. Terkadang ia bertanya pada dirinya sendiri, seberbahaya apa sih diluar sana sampai Ibu marah kalau Malik diam-diam membuka kunci gerbang padahal ia hanya mengambil paket saja. Malik pernah bertanya mengapa adiknya yang lebih kecil dari dirinya diperbolehkan keluar yang katanya bahaya, jawabannya ada dalam kalimat pertama pada paragraf ini yaitu, karena Malik berbeda.
Sewaktu-waktu kalau ibunya sedang beribadah dan Malik bosan, ia pergi ke gerbang depan hanya untuk diam sambil mengintip keadaan di luar sana melalui celah-celah pagar, di tangannya ada pedang mainan berjaga-jaga kalau bahaya menimpanya. Di malam hari pikirannya jatuh pada pemandangan langit yang ia lihat melalui jendela kamarnya, apakah ada bintang yang dibedakan sepertinya? namun, itu hanya sekelebat pikiran yang menjadi pertanyaan yang tak kunjung terjawab.
Kata orang, Malik adalah manusia special. Tapi ia selalu kembali bertanya, special yang bagaimana. Tanpa orang-orang tahu dirinya juga mengerti, bahwa nyatanya Malik hanya seorang manusia yang dilahirkan dengan keterbatasan, lebih tepatnya retardasi mental. Ia tak bisa sepintar dengan anak seusianya, Malik tak bisa menjaga dirinya sendiri, banyak hal yang tak ia ketahui karena ia sulit menerima dan memahami sesuatu, termasuk hal mudah menurut orang normal.
Tadinya dalam kepala Malik apapun yang diucapkan Ibu dan keluarganya benar tentang Malik adalah manusia luar biasa. Namun, setelah ia bersekolah ia dihadapkan dengan suatu realita yang ada yang memang harusnya ia terima dari dulu agar ia mengerti bagaimana mengikhlaskan suatu takdir buruk. Pelan-pelan otaknya semakin bekerja dengan baik mengikuti intuisi yang selama ini bekerja sebagai petunjuknya. Kepedulian seseorang yang sering Malik lihat, tangisan Ibu yang dulu ia kira karena ia tidak mau nurut padahal kenyataanya ibu lelah menghadapi pandangan masyarakat tentang Malik, kata-kata orang yang sering ditujukan ibunya seperti 'Maaf bukannya mau menyinggung', 'Aku mau nanya kondisi anak kamu tapi kamu jangan marah ya' atau 'Amit-amit' kata yang lebih sering ia temui setiap Malik berpas-pasan dengan orang lain.
Terbesit dalam hati, Malik selalu bertanya, mengapa Tuhan menakdirkan keburukan? kenapa Malik terlahir seperti ini? bukannya ini membuat kehadirannya di dunia menjadi kesusahan bagi sebagian orang?
Tapi Malik tetaplah manusia yang memiliki keterbatasan berpikir, pikiran diatas hanya sekilas bayangan yang akan ia lupakan beberapa jam kemudian. Tapi tahu kah orang-orang? Bahwa cita-cita Malik saat ini dan untuk selamanya adalah menjadi manusia biasa pada umumnya.
...
Hari itu hari sabtu, kali ini ibunya tidak lagi mendampingi Malik di sekolah, seperti sekolah pada umumnya hari sabtu merupakan hari dilaksanakannya kegiatan ekstrakulikuler. Malik mengikuti klub sepak bola, kata wali kelasnya bermain bola merupakan salah satu terapi sederhana yang dapat meningkatkan perkembangan Malik. Malik menuruti kata wali kelasnya itu walaupun ia kira olahraga itu akan sulit ia pahami dan hanya menjadikannya beban dalam klub tersebut. Sampai akhirnya ia terpilih menjadi pemain tetap dalam klub itu dan jadi salah satu pemain yang banyak penggemarnya terutama kaum hawa di sekolahnya. Sekarang kalian harus mengerti meskipun murid di sekolahnya memiliki keterbatasan secara fisik, mental, sensorik dan intelektual mereka semua masih memiliki rasa, begitu juga dengan cinta yang dapat tumbuh dimana saja. Seperti rasa yang ia rasakan di sekolah ini, tak ada perlakuan yang berbeda di antara murid, tak ada yang mengucapkan sayang tapi dengan tatapan kasihan, semua berjalan seperti semestinya layaknya hidup orang normal di luar sana.
Waktu menunjukkan pukul 12.00 siang, latihannya sudah beres dari setengah jam tadi tapi ibu belum menjemputnya. Sekarang Malik berada di pos satpam menunggu jemputan bersama teman-temannya, perlahan teman-temannya pamit pulang yang menyisakan dirinya dan Pak Wendi yang sedang menyapu daun-daun yang berserakan di gerbang.
Satu jam kemudian ibu belum datang juga sekarang Pak Wendi sedang membenarkan antena teve yang rusak sambil mengajaknya berbincang ringan. Setengah jam kemudian ibu tak kunjung hadir, ia sudah kenyang disuguhi segala macam camilan oleh Pak Wendi yang saat ini sedang menghubungi Ibu dan keluarga Malik walaupun nihil, tak ada yang bisa dihubungi. Karena Malik sudah bosan, satu ide terus muncul dikepalanya sedari tadi, bagaimana kalau hari ini ia pulang sendiri saja, ia hafal dengan jalan pulang dan uang bekalnya masih utuh. Setelah berpikir lama dan kebetulan Pak Wendi pergi ke belakang, ia langsung berlari keluar gerbang berniat pulang sendirian, mungkin ini kesempatan Malik untuk mengenal dunia yang sebenarnya.
Kaki tinggi itu berjalan menelusuri trotoar jalan yang ramai dilihat hari ini merupakan malam minggu, mata Malik menatap kesana kemari dengan takjub kalau ada hal yang menurutnya menarik. Langkah kakinya pendek, laju jalannya pun pelan bahkan ia akan berhenti pada suatu hal yang baru pertama kali ia lihat, terkadang tubuh Malik terombang-ambing atau tertubruk dengan badan lainnya. Tujuan pulang Malik terabaikan begitu saja saat ia malah memasuki pasar tradisional yang ramai pengunjung. Sekarang langkah kaki tersebut semakin cepat diikuti matanya yang antusias melihat etalase ikan hias.
"Wah hebat ikan," kata Malik sambil menunjuk ikan di dalam akuarium itu dengan mata yang berbinar melihat ikannya.
"Mau beli apa?" kata si penjual yang tiba-tiba hadir di antara Malik.
"Iya ikan buat Malik, yang mana?" pinta Malik kepada penjualnya.
"Adik maunya yang gimana? di sini segala ada. Gini deh kamu punya uang berapa?" tanya penjual ikan hias itu sambil menunjukkan ikan yang ia jual.
"Bukan adik, Abang Malik ini! Nih uang aku punya." Malik melepas tas dari gendongannya, mencari uang bekal yang sering ibunya simpan di dompet dan menyerahkan selembar uang lima ribu.
"Oh yang ini aja ya, kalau yang kamu mau mahal. Bentar dibungkus dulu," jelas penjual itu. Malik hanya mengangguk dan melihat-lihat lagi ikan hias yang dipajang di toko itu terkadang tangannya jahil masuk ke dalam akuarium.
"Nih dikasih bonus deh sama makannya." Penjual itu sudah beres membungkus ikan hias Malik pada sebuah plastik besar yang langsung Malik ambil dengan cepat.
"Makasih, Pak," kata Malik yang langsung pergi dari sana sambil memerhatikan ikan hias miliknya di dalam plastik dan dibalas anggukan oleh penjual ikan itu.
Jalan yang dituju Malik sekarang tak berarah, ia hanya terombang-ambing di antara hiruk piruk pasar yang semakin ramai. Ikan hiasnya menyita perhatian Malik dibanding ketakutan yang biasanya ia rasakan ketika menemui orang baru. Terkadang ada beberapa sekilas suara yang menyapa indera pendengarannya seperti 'Orang idiot. Bicara kok sama ikan.' dan tertawa terbahak-bahak dengan orang sekitarnya, Malik yang melihat itu hanya menatap orang-orang itu kebingungan dan terus melanjutkan perjalanan tanpa tujuan yang bisa jadi membahayakannya.
Satu jam Malik menelusuri pasar itu dan sepertinya ia masuk ke bagian dalam pasar yang kebetulan belakang pasar ini merupakan pemukiman warga. Semakin dalam semakin sepi, sekarang kakinya mulai bergetar baru menyadari dengan apa yang ia hadapi. Kukunya ia gigit kencang sambil melihat suasana pasar yang tak nyaman baginya, orang yang ia temui melihatnya aneh, bayangan-bayangan menakutkan menghantui pikirannya, Malik masih terus berjalan namun tak menemukan jalan keluar.
"Woi si dungu ada disini!" teriak seorang laki-laki dari jauh yang kemudian menghampirinya diikuti tiga orang di belakang.
"Hahaha dari mana lu idiot kok nyasar dipasar?" kata suara lain yang Malik dengar.
"Anjing, liat mukanya bego banget." Suara lainnya.
"Hajar aja kali ya? Kesel bet gue liat mukanya," kata laki-laki yang tadi teriak sambil mendorongnya hingga tersungkur, ia masih menggenggam erat plastik ikan ditangannya.
"Jangan gak boleh jahat kata ibu guru, Malik baik orangnya. Jangan ya!" peringatan Malik pada segerombol laki-laki itu saat tubuhnya berhadapan dengan tanah yang kotor.
"Bu guru bu guru, lu tuh bego! gak usah sok ngajarin gue anjing. Otak lu tuh cetek kaya anak tk," kata orang yang sekarang menendang badannya yang masih terjatuh. Laki-laki lainnya menjambak rambut Malik bermaksud agar ia melihat wajah laki-laki itu.
"Liat gue idiot, manusia kaya lu tuh sampah gak bisa ngapa-ngapain, idupnya nyusahin orang aja. Nih kepala lu, otaknya cuma seciul kek otak ayam," kata laki-laki yang menjambaknya yang disusul tawa oleh segerombolan anak muda itu. Tiba-tiba semua orang itu menendang badannya yang telah berlumuran tanah.
"Ampun, Malik salah apa? jangan injek ikan Malik, kasian. Aw sakit berhenti! Malik gak akan bilang ibu tapi kalian berhenti." Permintaan Malik percuma karena hanya dianggap hembusan angin yang berlalu, mereka terus melakukan tindakan kekerasan pada tubuhnya, nyeri yang hanya ia rasakan sekarang. Beberapa kali Malik meminta tolong pada orang yang lewat tapi tetap saja mereka hanya membalasnya dengan tatapan tak acuh. Jeritan kesakitan menggema di lorong pasar yang sepi ditambah dengan tangisannya yang semakin kencang.
Sebuah pisau mendarat di papan kayu tepat melewati segerombolan anak muda yang sedang menganiayanya itu. Malik melihat seseorang dari kejauhan yang melempar pisau itu, laki-laki dengan tubuh mungil mendekat ke arah mereka.
"Oh udah merasa jagoan ya lu pada. Pergi atau gue abisin satu-satu?" kata laki-laki bertubuh mungil di depannya dengan nada mengintimidasi. Entah kenapa segerombolan anak muda itu pergi meninggalkan tubuh Malik yang masih terdiam kaku di tanah. Laki-laki mungil itu mencabut pisaunya yang menancap di papan kayu dan menghampirinya.
"Berdiri. Mau diem aja disitu sampe digebukin lagi?" suruhnya sambil mengulurkan tangannya kepada Malik. Ia langsung menerima uluran itu dan berusaha menyeimbangkan tubuhnya yang ngilu. "Ikan Malik mati. Malik mau pulang," pinta Malik pada laki-laki itu.
"Ikutin gue, gue anterin pulang tapi sampai pintu keluar aja." Baru beberapa langkah pergi dari sana. Tangan seseorang merangkul Malik.
"Sini gue aja yang anterin sampai rumah," kata seseorang yang merangkul Malik dari belakang. Yang otomatis menjadi perhatian laki-laki kecil di depannya. Laki-laki mungil itu langsung berbalik memberikan tatapan galak, netranya sibuk menelisik dari atas sampai bawah pada orang yang merangkul Malik . "Oh ya, hati-hati." Finalnya.
"Makasih Zale, kalau gak ada lu ni anak udah mati," kata seseorang itu sambil melihat bordiran nama di seragam laki-laki mungil dan hanya dibalas anggukan kemudian pergi meninggalkan Malik dengan orang yang merangkulnya.
"Nama gue Juang, jangan takut walaupun muka gue kaya preman, gue gak akan bertindak bodoh kaya orang yang bikin lu bonyok. Ayo gue anterin pulang, lu bisa tunjukin jalannya," tutur laki-laki di sampingnya yang hanya dibalas anggukkan oleh Malik.
Selama perjalanan tak ada pembicaraan di antara keduanya, Juang hanya menatap jalan yang dilaluinya, Malik sibuk membayangkan wajah Ibu yang khawatir di rumah karena ia tak kunjung pulang. Semburat kemerahan menghiasi jalan yang sekarang dipenuhi kendaran, suara klakson dan bincangan orang menjadi latar keduanya, membelah trotoar yang jalannya kecil karena sebagian ruang diisi pedagang kaki lima. Malik perhatikan Juang dari samping, kulit pucat yang terlihat kotor, pipinya kurus seperti orang yang tidak makan dengan teratur, badannya juga tak sekuat yang Malik kira, Juang juga menjinjing tas besar seperti orang pulang kampung.
"Maaf, gue telat bantuin lu," ucap laki-laki itu yang tak Malik jawab.
"Ck lu gak cape dapet tatapan gini dari orang-orang? lu tuh manusia juga sama kaya gue kaya mereka, lu bukan badut yang menjadi pusat perhatian dan bahan tawa orang-orang." Malik kembali tidak menjawab membiarkan Juang terus berbicara.
"Gue tahu abis kejadian ini lu marah sama Tuhan, kenapa Dia menciptakan lu dengan keadaan begini. Tapi lu harus inget seluruh bagian tubuh dan apapun yang menjadi milik kita sejak lahir itu namanya takdir bukan kaya karya seni yang bisa dikritik dengan berbagai cara." Malik bisa merasakan emosi Juang yang semakin meningkat dari perkataannya.
"Mungkin lu gak bisa memahami kata-kata gue, tapi gue ngerti di dalam hati lu juga pengin jadi kaya manusia normal kan? maka dari itu hilangin istilah normal dalam kepala lu, manusia itu gak ada yang beda. Semuanya dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lakuin apa yang lu mau dan lu sukain tanpa memedulikan kata orang, saat itu lah lu tau apa yang terbaik buat diri lu sendiri," ujar Juang dengan tatapannya yang tajam pada Malik.
Malik hanya menunduk memerhatikan jalanan, Juang tak lagi berbicara sekarang. Terkadang rangkulannya melemah karena Juang sempoyongan tak kuat menahan beban badan Malik, semburat kemerahan sekarang berganti dengan awan hitam, cahaya yang berasal dari lampu toko menerangi jalanan yang mereka lewati begitu juga dengan lampu temaram jalan yang sudah dinyalakan. Satu belokan lagi menuju gerbang perumahan Malik tapi muka Juang sudah memerah dan memintanya untuk rehat sebentar di depan rumah makan. Malik hanya ikut duduk bersama Juang melihat orang-orang hilir mudik masuk rumah makan.
"Makan gak ya?" bisik Juang yang bisa Malik dengar.
"Juang belum makan?" tanya Malik pelan-pelan karena jujur setelah laki-laki itu mengomelinya ia sedikit takut.
"Enggak. Ayo lanjutin aja nanti orang tua lu makin khawatir kalau belum pulang." Laki-laki itu bangkit dari duduknya dan melakukan perengganggan sebentar sebelum memapah Malik kembali.
"Sebentar Juang, Malik beli mau makan." Pinta Malik dan langsung masuk ke dalam rumah makan itu dengan kakinya yang pincang meninggalkan Juang.
Malik perhatikan Juang diam-diam di kaca rumah makan sambil menunggu pesanannya, pemuda dengan kaos hitam kebesaran itu seperti mayat hidup jika dilihat dari jauh. Ia sedikit risau tadinya, takut tiba-tiba laki-laki itu menyerangnya seperti anak-anak di pasar. Tatapan Malik jatuh pada lauk yang disajikan di rumah makan itu, hari ini ia sudah bertemu dengan orang yang berbeda, segerombol anak yang menakutkan, laki-laki mungil dengan tatapan galak yang membawa pisau, dan seorang laki-laki seperti mayat hidup yang mengantarkannya pulang. Semua kejadian ini mengisi gambarannya tentang dunia luar, Ibu benar di luar banyak hal berbahaya untuknya tapi Ibu juga keliru karena sebaiknya hal berbahaya ini Malik hadapi saja, daripada terus menghindarkan Malik dari dunia realita.
Malik menjinjing keresek makanan yang tadi ia pesan dan menghampiri Juang yang tengah duduk, mengajaknya kembali berjalan. Kali ini di tangan kurus Juang sudah menggenggam botol air mineral yang isinya hampir habis. Kedua laki-laki itu akhirnya sampai di depan rumah dengan pagar putih.
"Semoga lu selalu bahagia ya Malik, berdamailah dengan kejadian tadi. Udah sana masuk bersihin badan lu, gue pamit ya." Pamit Juang dan berlalu dari hadapannya.
"Juang ini buat kamu, makan." Kata Malik membuat langkah Juang terhenti dan menatap Malik. Ia memberikan keresek makanan itu ke tangan.
"Hati-hati pulangnya, makasih Juang." Tambah Malik dan langsung masuk ke dalam pagar rumahnya. Ia perhatikan laki-laki dengan tas gendong besar itu tertegun sebentar kemudian kembali berjalan sampai sosoknya hilang di pertigaan jalan. Malik tersenyum pada bintang yang baru bermunculan di atas sana dengan wajahnya yang masih kotor.
Pada akhirnya Malik membuka pintunya, pintu yang selama ini terkunci rapat dan melindunginya dari sesuatu yang tak seharusnya Malik hindari.
0 notes
Text
[8] Rembulan dalam Selembar Angpau
Mentari mulai menampakkan diri di atas toko kelontong di persimpangan jalan kota Singkawang, bayangan lampion menghiasi jalanan sekitar toko yang saat itu masih tertutup rapat. Di depan toko tersebut hadir seorang laki-laki yang sedang santai duduk di kursi panjang, kedua tangannya memegang ujung buku yang tengah ia baca.
"Koh, toko buka kapan?" suara anak kecil menyapa kedua telinganya dari samping.
"Enggak, tutup," jawabnya tanpa mengalihkan atensinya dari buku.
"Aku tahu itu tutup, kalau buka pun aku tak tanya kau, Koh. Kapan bukanya?" Anak kecil itu kembali bertanya padanya.
"Hari ini tutup," jawabnya dengan singkat.
"Tumben sekali tutup biasanye Koh Tjan buka terus," kata anak kecil itu yang kini masih setia duduk di sampingnya.
"Ayolah koh layani aku saja, malas aku kalau harus beli ke pasar. Kau tak kasihan padaku koh bedengkang begini harus pergi ke pasar, " pinta anak kecil itu sambil terus menepuk pundaknya.
"Mok kong, nyi an tjhiu!" balasnya sambil berlalu masuk ke dalam toko mengabaikan bocah kecil itu. (Jangan ngomong, kamu sangat bau)
Mikhail, laki-laki yang tadi membaca buku di depan toko, menghampiri Mamanya di dapur yang letaknya berada di belakang toko. Ia melihat Mamanya dengan serius membuat makanan yang nantinya akan dibawa pergi, karena niat membacanya sudah hilang gara-gara bocah tadi sekarang ia membantu Mamanya saja memasukkan beberapa makanan yang sudah jadi.
Pada tanggal lima bulan lima dalam penanggalan lunar sudah menjadi kebiasaan kalau keluarga Mikha akan turut serta dalam Acara Duan Wu Jie atau dapat disebut juga Peh Cun dalam bahasa Hokkien dan lebih dikenal sebagai Hari Bakcang oleh etnis tionghoa di Indonesia. Acara tersebut biasanya diselenggarakan di pinggir sungai Kapuas yang dimana dirinya akan mengunjungi rumah bibinya yang berada di Pontianak.
Hari ini adalah hari dimana diselenggarakannya acara tersebut, begitulah alasan kenapa toko kelontong milik Koh Tjan atau Papanya masih tertutup rapat. Walaupun sering ikut serta, namun Mikha sama sekali tidak terlalu tertarik mengikuti acara tersebut, lebih tepatnya ia tidak suka acara yang melibatkan orang banyak. Kepribadian yang tenang dan sudah terbiasa menyendiri membuat dirinya susah menjalin interaksi dengan orang yang tak ia kenal. Tapi Mikha juga bukan tipe orang yang akan selalu diam di dalam rumah, setiap minggu pasti ia pergi keluar rumah untuk mencari beberapa objek yang bisa ia potret untuk memenuhi roll filmnya menggunakan kamera analog miliknya atau sekadar baca buku di Cafe sepi dengan musik yang mendayu-dayu.
...
Kini Mikha sudah duduk manis di kursi belakang mobil, pandangannya menembus kaca jendela mobil memerhatikan jalanan yang tidak terlalu ramai sambil sesekali memotret objek yang ia rasa menarik walaupun banyaknya ia hanya melihat trotoar dan ribuan tiang listrik yang timbul-hilang. Suasana di dalam mobil pun hening hanya sesekali terdengar obrolan singkat dari kedua orang tuanya, sekarang lagu Berawal dari tatap yang dinyanyikan oleh Yura Yunita tengah mengudara di dalam mobil membuat Mikha sesekali bersenandung mengikuti nada lagunya.
Setelah menempuh perjalanan yang panjang dengan waktu tempuh tiga jam, mobil keluarga Mikha menepi di sebuah rumah berwarna putih yang memang sering ia kunjungi, beberapa sanak saudara yang sampai lebih dulu tengah kumpul di luar rumah sedang bersiap pergi ke acara Peh Cun. Lantas Mikha turun dari mobilnya dan menyapa saudara-saudaranya.
...
Semakin sore matahari semakin bersinar, cahayanya membias di tengah sungai Kapuas yang saat itu ramai dengan orang-orang pun dengan langit yang melukiskan semburat warna jingga. Ratusan warga tionghoa yang mengikuti perayaan itu sudah siap dengan pakaian dan sepitnya masing-masing, panitia sibuk kesana kemari menyiapkan acara yang akan dimulai beberapa menit lagi, berbanding terbalik dengan Gege dan Meimei Kota Pontianak yang duduk manis menyambut orang-orang penting yang datang di perayaan Peh Cun itu, di sebuah kapal wisata yang sudah di dekorasi dengan ornamen khas kebudayaan tionghoa.
Setelah sampai di tempat acara, Mikhail memilih menepi pada sebuah dipan di bawah pohon yang saat itu sepi, berbanding terbalik dengan keadaan beberapa meter dari dipan tersebut yang ramai. Netra Mikhail memerhatikan dari jauh bagaimana acara itu berjalan, setiap menitnya penonton yang diduga warga sekitar tumpah ruah di pinggir Kapuas.
Tepat pukul dua siang hari, tradisi perayaan Peh Cun dimulai. Suara Gege dan Meimei menyapa siapa saja yang berada disana, menjelaskan rangkaian acara yang akan dilaksanakan, Mikha sedikit menyipitkan kedua matanya berusaha melihat seseorang yang berbicara di panggung sana saat ia mendengar suara yang familiar baginya diantara kedua suara tersebut. Setelah mengetahui dan meyakinkan bahwa seseorang itu yang ia kenal dirinya hanya membuka buku yang sedari pagi selalu ada di tangannya, di antara keramaian Peh Cun tahun ini Mikha memilih menimbun dalam-dalam dirinya pada lembaran imaji dengan beralaskan dipan dan beratap dedaunan yang warnanya setengah menguning.
Suara langkah kaki beradu tongkat sedikit mengalihkan pendengarannya tapi Mikha memilih terus menggulir matanya di antara tulisan, hingga sebuah tubuh yang tak Mikha ketahui itu kini mendudukkan diri di sebelahnya. Ia masih tak mau menghiraukan pergerakkan orang di sebelah walau dari dalam hatinya ada rasa kesal karena kehadiran orang itu mengganggu waktu sendirinya tapi tak apalah lagi pula ini tempat umum semua orang berhak duduk dimana saja.
Pergerakkan dan suara tepuk tangan mendadak dari orang di sebelah Mikha membuat ia terkejut dan berhasil menjatuhkan bukunya. Mikha menghembuskan napasnya dalam-dalam mencoba meredam rasa kesal. Mikha memerhatikan seorang perempuan itu yang sekarang sedang meraba-raba, mencoba mencari bukunya.
"Maaf saya gak bermaksud buat menjatuhkan barang kamu, saya kira tadi gak ada orang," kata perempuan di hadapannya sambil menunduk memberikan bukunya.
Mikha terpaku menatap mata perempuan tersebut, mata hitam legam namun tetap bersinar itu mengingatkannya pada rembulan yang berlayar melewati jendela kamarnya tujuh tahun lalu. Kerudung merah yang hanya disampirkan di kepalanya, baju putih dengan tali pita di lengan, rok hitam yang tidak sampai menutupi mata kaki dan tongkat pendek yang di genggam erat oleh tangannya, itulah deskripsi menurut penglihatan Mikha tentang perempuan di hadapannya. Sebetulnya ada pertanyaan yang hinggap di kepalanya saat perempuan itu tergesa meraba mencari buku.
'Apa perempuan tersebut tidak bisa melihat?'
Namun pikiran tersebut terhempas begitu saja ketika ia bertatap mata dengan mata indah perempuan tersebut, menurut Mikha tak ada yang salah dengan penglihatannya. Rasa kesal yang tadi singgah sebentar dalam hatinya kini tergantikan dengan rasa penasaran dalam benaknya, sungguh Mikha seperti melihat kembali rembulan yang berlayar malam itu.
"Ini bukunya, sekali lagi saya minta maaf," tutur perempuan itu sambil memberikan bukunya yang dari tadi belum Mikha terima.
"Mikha, nama saya Mikhail," ucap Mikha tanpa sadar.
"Eh? hai Mikha nama saya Rainun," balas perempuan itu.
...
Berkat perkenalan tanpa sadar Mikha, membawa keduanya larut dalam percakapan yang belum pernah Mikha temui sebelumnya. Jujur Mikha adalah seseorang yang susah sekali dekat dengan orang lain, apalagi dengan orang yang baru ia temui. Berbeda dengan sekarang, tatapan serius yang ia layangkan pada Rainun, lebih tepatnya pada matanya. Sebenarnya ia menganggap Rainun adalah seorang rembulan yang ia temui tujuh tahun yang lalu dibanding menganggapnya sebagai seorang manusia.
"Kau tahu Mikha, kenapa bapak menamaiku Rainun? katanya namaku diambil dari bahasa arab ainun yang berarti mata karena katanya mataku indah dari sejak lahir. Tapi lama-lama itu terdengar seperti ejekkan bukan? kalau nyatanya aku tak bisa melihat tapi namaku berarti mata, indera penglihatan," papar Rainun yang Mikha dengar dengan lamat.
"Tapi benar kata bapak, matamu indah. Bersih, legam dan bercahaya seperti rembulan yang berlayar kala itu yang melintasi jendela kamarku."
"Aku tahu itu Mikha, banyak yang bilang seperti itu. Lagi pula keindahan mataku membuktikan bahwasannya Tuhan Maha Adil. Di luar sana banyak orang yang pandai melihat namun merasa kurang dengan bentuk matanya sendiri."
"Tapi yang terpenting adalah penggunaannya, Nun. Seberapa pentingnya suatu hal kalau tidak digunakan dengan benar, hal tersebut hanya sia-sia. Dengan begitu manusia sebenarnya tak butuh kesempurnaan fisik kalau tubuhnya sendiri digunakan untuk melakukan kejahatan, menyakiti orang lain atau kegiatan yang merugikan lainnya."
"Bapakku juga pernah bilang, Mikha. Syarat utama suatu makhluk digolongkan manusia adalah hatinya. Tapi ketika berbicara itu aku belum mengerti apa-apa, saat itu aku hanya bisa menggerutuk pada Tuhan, untuk apa Dia menciptakan mata yang indah kalau tidak bisa digunakan."
"Eh Nun, kau pernah menggerutuk Tuhan?"
"Aku juga pernah bodoh sebelum mengerti, Mikha. Kau juga pasti pernah menggerutuk Tian-shi mu bukan?"
"Lantas apa yang membuatmu mengerti ucapan bapak?"
"Aku baru mengerti setelah malam berikutnya, setelah kawanku meminta maaf. Sebenarnya pagi itu suara tak bertanggung jawab menyapa telingaku, katanya untuk apa aku cantik kalau buta, kalau aku sendiri tak bisa melihat kecantikanku. Perkataan itu memanasi hatiku yang memang saat itu belum bisa menerima diriku sendiri."
"Apakah masih ada orang yang seperti itu di masa sekarang?"
"Dengarkan ceritaku dahulu Mikha, baru kau bisa bertanya setelahnya. Dan malam hari itu setelah aku membuatkan secangkir kopi untuk bapak, aku dapat mengerti. Omongan manusia itu bermacam-macam layaknya jenis kopi, kalau kita mau manis ya tambahkan gula, kalau kita ingin pahit ya biarkan saja tanpa gula. Begitu juga dalam hal berbicara, kalau kita mau berbicara seadanya tapi menyakiti orang ya silahkan, kalau mau memuji orang ya boleh saja. Sekarang aku bertanya apa yang membuat keduanya sama?"
"Em...Mungkin, kedua hal tersebut sama-sama dilakukan dengan kemauan dan kesadaran?"
"Iya betul, keduanya didasari kemauan dan kesadaran. Orang yang mengejekku sebenarnya tahu perkataanya begitu menyakiti orang namun sayang, dirinya tak mengikuti kata hati. Bapak benar, yang mendasari manusia atau tidaknya seseorang adalah hati."
"Bapakmu adalah orang yang bijak ya Nun?"
"Semua bapak juga bijak Mikha, karena mereka memiliki pengalaman hidup yang lama lebih dari kita."
"Sebagian Nun, bukan semuanya. Banyak anak tidak beruntung sepertimu dan aku."
"Kalau begitu aku sangat bersyukur. Maaf Mikha aku hanya mengambil contoh dari diriku sendiri, selama ini aku hanya hidup berdasarkan 'katanya' karena aku tidak bisa melihat 'nyatanya'. Kalau bapak kamu?"
"Papaku sangat baik, Nun. Selalu membuatkanku Bakcang special setiap Peh Cun yang ia buat sendiri sampai begadang malam-malam."
"Apa tahun ini dia membuatkanmu?"
"Iya tapi belum aku makan, ini masih ada."
"Ngomong-Ngomong aku membawa sesuatu untukmu," kata Rainun sambil tangannya sibuk mencari sesuatu di kantung roknya.
"Angpau? ini bukan Cap Go Meh, Nun. Hari ini perayaan Peh Cun."
"Benarkah? Kalau begitu selama ini aku salah merayakan."
"Tapi tak apa, aku terima saja."
"Jangan dibuka sekarang Mikha, dan jangan berharap lebih dengan isinya."
"Iya mau berapa pun aku terima, kamu pernah makan bakcang Nun?"
"Tentu saja pernah, memang kenapa?"
"Tunggu sebentar."
Mikha pergi dari dipan itu meninggalkan Rainun yang sedang duduk kebingungan karena tidak merasakan kehadiran Mikha, Rainun kira mungkin Mikha mau ke kamar mandi sebentar. Mikha lari menerobos kerumunan orang yang masih betah menyaksikan acara, dan dengan kecepatannya kini ia kembali ke tempat dimana Rainun berada dengan membawa sesuatu di tangannya.
"Nun, ini bakcang buatan Papahku. Nih pegang buat kamu."
Sebenarnya Papah Mikha membuatkan dua buah bakcang kemarin malam, katanya satu lagi harus Mikha berikan pada seseorang yang ingin ia doakan baik-baik saja untuk tahun ini. Tadinya Mikha akan memakan keduanya, semenjak perkenalannya dengan Rainun beberapa jam kebelakang, ia berubah pikiran dan memberikannya pada perempuan tersebut.
"Nun, coba kamu raba. Bakcang itu mempunyai empat sudut yang keempat sudut itu mengandung maksud yang sebaiknya dimiliki manusia." Mikha lantas memegang tangan Rainun sambil memandu perempuan itu untuk meraba ke empat sudut yang ia ucapkan tadi.
"Sisi pertama dinamakan Zhi zu yang berarti merasa cukup. Yang sebelah sini sisi kedua dinamakan Gan en yang berarti penuh syukur. Sebelah sini dinamakan Shan Jie yang berarti berpikir positif dan sisi terakhir bernama Bao rong berarti merangkul sesama."
"Kalau begitu, bagaimana dengan orang yang memakannya apakah akan memiliki sifat itu juga?" tanya Rainun dengan sungguh-sungguh.
"Tidak Nun, itu hanya filosofi saja. Baik buruknya manusia tergantung apa yang kata bapak kamu bilang tadi, tergantung hatinya."
"Rainun, ayo pulang!" teriak seseorang dari jauh.
Rainun pun bersiap pergi dari sana, tak lupa ia pamit kepada Mikha sambil mengucapkan terima kasih karena sudah mau berbincang dengannya juga dengan bakcang yang diberikan padanya. Ia menatap kepergian Rainun, tangan kanan perempuan tersebut memegang erat tongkat yang selama ini memapahinya berjalan dan di tangan kirinya memegang bakcang darinya. Mikha tersenyum melihat punggung yang kini semakin jauh dari pandangannya, banyak harapan dan doa yang ia ucapkan diam-diam dalam hati, petang ini rembulannya kembali pergi dan ia tak tahu kapan ia dapat menemuinya lagi.
Perayaan Pen Cun sudah selesai, orang-orang berhamburan pulang dari tempat acara, begitu juga Mikha. Ia memasukkan angpau merah pemberian Rainun ke dalam sakunya, kemudian pergi meninggalkan dipan itu.
Percakapan sore itu menyimpan kesan tersendiri di benak keduanya. Menurut Rainun sore itu ia berbincang dengan malaikat yang memberitahunya sifat yang sebaiknya ia miliki dan bagi Mikha percakapan itu adalah percakapan dirinya bersama rembulan yang memperlihatkannya bukti sebuah ikhlas yang sederhana.
0 notes