#kritikfilm kritik
Text
ARTIKEL FILM: Menengok Kritik Film Indonesia Masa Lampau
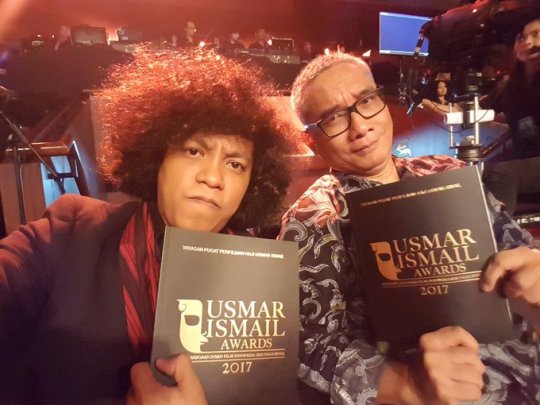
image credit: Twitter Arie Kriting @Arie_Kriting, 29 April 2017, 08.00 PM.
Oleh Ade Irwansyah
Kehadiran film di negeri ini tidak dimulai oleh kritik, melainkan iklan. Pemutaran film pertama di Indonesia (waktu itu masih disebut Hindia Belanda) pada 5 Desember 1900 diawali dengan iklan di koran. Ini wajar. Sebab, kritik film baru dimulai ketika film selesai. Tidak mungkin kritik film hadir lebih dulu dari filmnya.
Sejak permulaan abad ke-20, perhatian pers pada film sudah ada. Asrul Sani menulis di jurnal Prisma tahun 1990, “kritik film di Indonesia sejak semula selalu berada di tangan wartawan dan dengan demikian tidak lepas dari pekerjaan wartawan: yaitu melaporkan sesuatu yang baru, dalam pengertian si penulis lebih banyak menekankan aspek kebaruannya daripada aspek kelanggengannya sebagai hasil karya seorang sineas.”
Karena kritik diperlakukan tak ubahnya berita, “kritik-kritik awal tentang film lebih banyak memberitakan isi cerita film tersebut dan nama-nama pemainnya.”
Beberapa wartawan terkemuka awal abad 20 juga terjun jadi sineas, sebagai penulis skenario hingga sutradara. Sekadar menyebut contoh, Albert Balink seorang sineas yang membuat film Pareh (1935) dan Terang Boelan (1937) dulunya adalah wartawan De Locomotief (Semarang) yang sering menulis tentang film. Lalu ada pula Andjar Asmara. Ia pernah menjadi wartawan berbagai koran dan majalah terjun ke dunia film di tahun 1940. Ia jadi sutradara perusahaan film JIF (Java Industrial film) di Jakarta.
Sosok lain adalah Kwee Tek Hoay, sastrawan sekaligus wartawan terkemuka. Ia tergolong kritikus yang kerap menulis tajam. Film Resia Borobudur (1928) dikritik keras begini, “tidak perloe moesti orang djoestain dengan begitoe kasar, karena penonton jang ada poeja pengertian soedah tentoe mendjadi jemoe.” (Panorama, taon ka-3, no 136, 20 Juli 1939). Yang dimaksud “djoesta” adalah bagian dialog yang berpanjang-panjang hingga menjemukan. Seperti Balink dan Andjar Asmara, Kwee Tek Hoay juga kemudian menjadi sineas. Film yang ceritanya ia tulis antara lain Boenga Roos dari Tjikembang (1931), diangkat dari novelnya.
Selepas merdeka penuh akhir 1940-an, film Indonesia memasuki masa keemasan tahun 1950-an baik sebagai karya seni maupun kritiknya. Di masa ini untuk pertama kalinya sejak lahir di bumi Nusantara film diapresiasi lewat penghargaan dan perayaan bernama Festival Film Indonesia, tahun 1955. Di tahun 1950-an pula puncak pencapaian film sebagai karya seni terjadi. Banyak kalangan menilai film terbaik Indonesia sepanjang masa adalah Lewat Djam Malam karya Usmar Ismail, rilis tahun 1954. Filmnya berkisah tentang seorang bekas tentara bernama Iskandar (A.N. Alcaff) yang gagal menyesuaikan diri dalam masyarakat setelah bergerilya sekian tahun. Sitor Situmorang, dalam kritik filmnya, memuji film itu “… sudah sampai pada taraf yang dicapai oleh sastra dan puisi Indonesia modern dan seni lukis, dalam hal sikap kejiwaan terhadap kejadian dan perasaan manusia sekarang…”
Kritik film juga berkembang pesat di tahun 1950-an. Bahkan Zainal AN mencatat “sejarah kritik film di Indonesia baru dimulai sekitar awal tahun ’50-an.” Semakin banyak media yang menaruh perhatian pada perfilman. Soal film di antaranya banyak ditulis di media cetak macam majalah Aneka. Zainal menyebut kritikus film tahun 1950-an antara lain Usmar Ismail (selain jadi sineas, Usmar juga aktif menulis soal film), Hamildy T. Djamil, Bus Bustami, Rasyid Abdul Latief, Lingga Wisnu, Misbach Yusa Biran, Purwana dan lainnya.
Antara akhir 1950-an sampai pertengahan 1960-an, kritikus film juga lahir dari dunia pers. Dalam catatan Zainal, penulis kritik film masa itu antara lain Zulharmans, Chaidir Rachman, Hadikamajaya, Harmoko, J.S. Hadis, Setia Darma, Setyadi Tryman. Sedangkan media yang memberi tempat pada kritik film antara lain Berita Minggu, Pos Indonesia, Hari Minggu, Berita Republik, Pikiran Rakyat, Indonesia Raya, Abadi, Siasat, Star Weekly, Surat Kabar Pedoman dll. Lalu ada pula Gayus Siagian. Ia sineas (menulis skenario beberapa film-film Usmar Ismail) yang juga kritikus film.
Memasuki masa Demokrasi Terpimpin situasi politik yang memanas merambah perfilman. Film sebagai karya seni individual mendapat tentangan keras dari politisi dan seniman berhaluan kiri (baca: PKI dan Lekra). Bagi golongan kiri, seni—dan demikian juga film—harus didedikasikan bagi “revolusi yang belum selesai.” Di sini politik jadi panglima bagi setiap ragam seni. Apa yang digelorakan seniman Lekra dan PKI itu mendapat reaksi lewat Manifes Kebudayaan (lazim disebut Manikebu) pada 1963.
Seniman masa itu terbagi dalam dua kubu, pengusung “politik adalah panglima” dan aliran realisme-sosialis-nya dengan penganjur Manikebu dan pandangan humanisme universal-nya. Film pun tak luput dari sasaran tembak. Film yang dianggap “beraroma” humanisme universal ditentang keras media milik golongan kiri. Karenanya, kritik film era itu, terutama di media berhaluan kiri atau yang resmi milik PKI, mengecam film-film yang mengandung pesan—entah tersirat atau tersurat—dari “golongan Manikebuis”.
Contoh jelasnya terjadi pada Pagar Kawat Berduri (1963). Harian berhaluan kiri Bintang Timur (edisi 14 Maret 1963) mengkritik film Asrul Sani itu dengan judul “Kita Minta Perhatian Serius Bung Karno Terhadap Film Pagar Kawat Berduri” yang dinilai sebagai “… mempertegas watak tanggapannya tentang Revolusi Indonesia… dan jahatnya prinsip ‘Humanisme Universil’-nya Asrul mengebiri patriotisme dan heroisme pejuang-pejuang revolusi…” Harian Warta Bhakti menulis begini: “Dalam Pagar Kawat Berduri ada pembela imperialis dan kolonialis… (Film itu) harus dinilai kembali supaya tidak telanjur banyak yang merasa terhina.”
Filmnya kemudian disita dan diteliti militer—bahkan diteliti Sukarno sendiri. Namun kemudian boleh beredar luas tanpa gunting sensor sedikitpun. Hiruk pikuk “politik adalah panglima” ini berakhir seiring peristiwa G30S di tahun 1965, pembubaran PKI, pembunuhan massal dan pemenjaraan anggota serta simpatisan PKI (termasuk seniman-senimannya) selama 1965-1967, dan lahirnya Orde Baru.
Ketika Orde Baru Soeharto mencapai stabilitasnya di tahun 1970-an film Indonesia berkembang pesat. Stabilitas politik dan ekonomi (apalagi setelah Indonesia dapat untung dari booming harga minyak di tahun ’70-an) menyuburkan industri film dari segi kuantitas. Film Indonesia diproduksi puluhan judul per tahun. Lantas, bagaimana kualitasnya?
Nah, di sini kritikus film berperan. Kritikus banyak mengalamatkan kritik tajam pada film-film Indonesia. Goenawan Mohamad menulis, “film-film Indonesia masa ini [tahun ’70-an—pen.] terkenal karena kostum cemerlang hingga mengesankan suasana butik dan lalu-lintas peragawati, juga mobil-mobil gemerlap, juga rumah-rumah yang dipajang dan dilengkapi benda-benda kemilau, juga hiburan malam yang lazimnya berlangsung di sekitar night-club, dan juga lanskap kota—biasanya Jakarta—yang mengandung simbol ‘metropolitan.’” Film Indonesia telah kembali pada “dosa asal”-nya, hanya sebagai barang dagangan yang menghibur. Hiburan ini utamanya pula buat kaum miskin di perkotaan. Mereka disuguhi mimpi jadi orang kaya lewat film.
Kondisi ini menimbulkan rasa khawatir. Salim Said, kritikus film yang bergiat di tahun ’70-an, menulis di tahun 1975, “maju mundurnya kritik tergantung sepenuhnya pada maju mundurnya sang objek… Lewat karya-karya seni yang makin matanglah seorang kritikus bisa memerlihatkan kebolehannya.” Artinya, bila film-film yang lahir melulu film-film hiburan penjual mimpi, sulit muncul kritik yang bermutu. Yang muncul malah kritik yang menggerutu. Itupun hanya dianggap angin lalu.
Alhasil, kritik film juga mengalami kemundurannya di zaman Orde Baru. Asrul Sani menulis di tahun 1990 kalau “kritik film kita belum berhasil menemukan sikap yang tepat yang sesuai dengan tugasnya, yaitu menjadi pandu untuk orang banyak dalam memilih film baik dan membantu seorang sineas menyadari kekurangannya.”
Lalu, dalam sejarah film dunia sejumlah pertumbuhan gaya baru pembuatan film justru dimulai dari kritik film. Dalam sinema Perancis gerakan New Wave (gelombang baru) atau Nouvelle Vague dimulai kritikus film Francis Truffaut dan kawan-kawannya yang kemudian dibuktikan lewat membuat film sendiri. Hal semacam itu tak pernah terjadi dalam sejarah kritik sinema kita.
Yang kita lihat kini sebuah keriuhan. Media sosial memungkinkan kritik film muncul dalam 140 karakter di Twittter, atau dalam bentuk posting di Path dan Facebook. Sekarang semua orang adalah tukang kritik. Tapi, bila hanya jadi tukang kritik, buat apa? ***
Bahan Bacaan
Asrul Sani, “Perkembangan Film Indonesia dan Kualitas Penonton”, dalam Prisma No.5, Tahun XIX 1990.
Goenawan Mohamad, “Film Indonesia: Catatan Tahun 1974”, dimuat dalam Goenawan Mohamad, Seks, Sastra, dan Kita, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1981.
JB Kristanto, Katalog Film Indonesia 1926-2007, Penerbit Nalar, Jakarta, 2006.
Salim Said, Pantulan Layar Putih, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
Zainal AN, tulisan tanpa judul dalam Festival Film Indonesia: Buku Kritik Film Indonesia 1982-1983, PWI Jaya Seksi Film, Teater, dan Kebudayaan—Badan Pelaksana FFI 1983, Jakarta, 1983.
CATATAN:
*) Artikel ini saya tulis untuk dimuat di buku Usmar Ismail Awards 2017. Di ajang pemilihan film terbaik oleh wartawan tersebut, saya menjadi salah satu jurinya.
0 notes