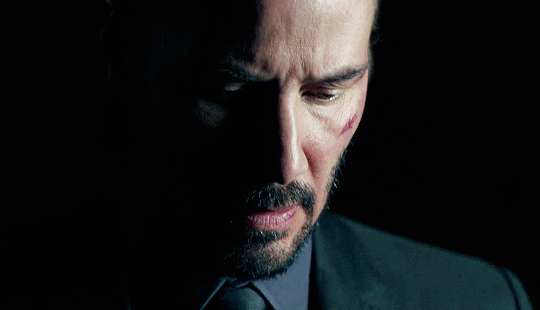Text
The Christmas Card
It was already late as I found myself inside the mall that night, all alone, feeling lost among the rush of outgoing shoppers. They are on the electric staircases, in the elevators, along the hallways, at the cinema door.
I am never a big fan of malls, crowds make me nervous. Sad thing, because these are the only places the city people could mostly turn to when they love the city, when they loathe the city, when they have no idea what to do with the city. Christmas was about a week away. These places seem to be ready to explode anytime. Not like they ever explode—they contain us most of the time—which makes me keep wondering. There are red and green and white everywhere, and woolen hats, and pine trees. The plastic ones, of course, which is kind of sad, too, plastic trees. All the corners you turn to you might also bump into one of these old men with that thick silver beard.
I didn’t know where to go.
But record store, of course.
He never really said anything about it, it was me all along. Not that I actually thought about it all the time either, I did not. The only thing come to mind when I have to give someone a present is a book. I gave him books, as a present, twice. I could do it again, but at one point I just thought perhaps a change would be great. I thought a book might be wonderful, but as wonderful as it might for him if he gets me a—Barca’s football jersey. I got him a CD for his last birthday, songs of my own compilation. This was one of the few things we both have in common, music. One of those little things we find peace at, regardless of all the differences we have to cross; the distance between our ages, between Mars and Venus, between books and football. His was the only birthday I can think about getting a present which is not a book.
And I think about him all the time.
The record store was closed.
I saw them tying a chain at the door, locking it with a padlock when I got there. The rolling door was half down. Through the glasses I could see it; the blue behind that pair of wings on the cover. Coldplay, Ghost Stories. I only want to have one of those, that one. It might only take five minutes. Could you please—no, they won’t. Because it will include opening the door again, turning all the lights on, rebooting the computer at the cash register, and getting the money, and the waiting, so, forget it.
I left for the bookstore, like I always leave for. They were still open. At first I thought they might sell CDs, which I knew was not likely, but I went to the miscellaneous sections anyway. No music except the player, no CDs except for language practices. Another plastic tree, red hats and old man with thick silver beard. Then I found those Christmas cards.
It took me a few minutes to spin the card shelf around, seeing all that were on display, the reds, the pinks, the golden bells and the silver crosses, and I knew they might be closing the store anytime now. I saw the white doves, the snowflakes, and the pine trees—I suppose they represent the real ones—things I never took time to look at this close, not once in my life. That was when the realization struck me.
I am buying someone a Christmas card for the first time in my entire life.
***
I was born and raised as a Muslim, in a good Muslim family, a loving one. I went to an Islamic school, I wore hijabs once in a while, I read and learn Arabic. I am proud of where I come from and never intend to alter a single fact of it.
He came to my life without wishing he would, either.
I knew that.
I remember one of those rainy days we first saw each other. He came to my work place, riding a scooter one of his friends had lent him, and picked me up to eat somewhere. I cut my finger from zipping my bag as he handed me the helmet, it bled. We rode to this dining place, and all the way there, and to our table, he tried to cover my bleeding finger with his own, and never let go until the time our food arrived. The hands finally parted only when we had to come back to ourselves, pray in our own ways, and I finished first. I stole a glance at him in the middle of his prayer, because starting eating alone would be rude, and he was long. That was when it came to my surprise; how I loved what I just saw. Him, with his silence, his eyes closed and his face down, and peacefulness.
I thought, I felt fine this way.
I thought to myself how often would it be in your life, somebody would care that much—so much they would cover the cut on your skin to stop the bleeding, seal all your heart breaks in the past, see you as who you really are without feeling they have to change anything regardless of the distance they have to go through. It had, at first, crossed my mind that probably this was not it, he was not the one, that I should wait a little longer for someone better. Someone with more similarities, and therefore more understandings. It would be easier to understand something more familiar, you see; familiar social background, familiar history, familiar religious tenets.
It would not take that much of effort, it would cost less devastation.
It would be more affordable.
But he went across the distance for me.
It had taken him those efforts, and wounds, and devastation, just to understand why I have to do what I do, why I have become the girl that I am now. None of us have any idea whether we would end up together, but I thought to myself, several times, why I had to trade these with something else from someone else, just because they are ‘familiar’.
I haven’t found the answer yet.
***
The rain fell lightly as I left the mall that night. It was cold, I bought some coffee and took a cab home. It was a Friday, traffic would be the worst in the whole week, and I wouldn’t be seeing him the day after—he would have church. But I have already got something burning inside my bag with the light of happiness and a tingle of surprise. A Christmas card. And, something else.
I hope he likes it.
18 notes
·
View notes
Text
The Princess Saves Herself
Bab Satu - Six Degrees of Separation
Kairo
Ternyata aku sudah kenal Alexandria selama sembilan tahun. Dia tidak pernah berubah, wow. Dari tahun kedua di SMA—tahun kepindahanku ke kota ini—sampai wisuda. Mungkin berat badannya hanya bertambah dua ons dan tingginya segitu-gitu juga. Jaket almamater SMA kami masih muat dengan sempurna di tubuhnya, dan dia masih mengenakannya sekampus-kampus. Setiap kuingat itu, ya ampun. Padahal di kampus kami sudah punya jaket almamater baru. Semua orang jadi tahu aku dan Al satu SMA. Teman-temanku yang laki-laki mulai bertanya asal-usul anak itu, alamat rumahnya, nomor teleponnya, makanan kesukaannya (ketika semua makanan adalah kesukaan Al), akun Instagram dan nomor KTP bila mungkin, dan terutama apa dia sudah punya pacar.
Alexandria selalu berambut panjang, katanya itu keturunan (seolah-olah saat lahir rambutnya langsung panjang). Dia memang begitu, sabar ya. Dia punya lelucon-lelucon teraneh yang kadang-kadang aku tak mengerti. Beberapa kali aku terlonjak kaget saat ada yang tiba-tiba terbahak-bahak karena cerita lucu Al. Padahal kurasa itu karena Al tertawa oleh leluconnya sendiri. Tawanya menular. Orang-orang itu tidak mendapati yang semacam Al setiap hari. Al bisa tertawa sampai terbahak-bahak karena leluconnya sendiri bahkan sebelum ceritanya selesai. Bahkan sebelum sempat mengerti aku bisa tertawa karena melihat mereka tertawa. Positivitas yang luar biasa, salut. Sabar, ya. Suki teman kami menyukai Al karena ini. Positivitasnya yang menular itu. Bidi, pacarku selama separuh masa di universitas, juga begitu. Kalau kamu terbiasa berada di dekat Alexandria, kamu akan terbiasa juga.
Ah, ya. Rambut Al.
Kurasa satu hal yang akan selalu indah adalah rambut Alexandria. Aku harus bilang itu, dan kamu akan setuju. Bidi dan Suki senang sekali menyentuh-nyentuhnya. Aku sudah pernah melihat Alexandria baru bangun tidur kering-kerontang tanpa terbasuh air saat kami di atas gunungdan aku pernah menyaksikan Al berdarah-darah di hari terburuk menstruasinya. Aku sudah pernah menyaksikannya nyaris di segala kondisi, kecuali demo. Bukan demo masak yang kumaksud. Demo aksi mahasiswa, yang Alexa selalu menolak untuk ikut berpartisipasi tanpa alasan yang kuyakini betul. Poinku, perempuan tidak bisa selalu terlihat cantik, itu tak mungkin. Kecuali mereka menikah dengan pangeran Wales. Namun bahkan di hari-hari terburuk Al—saat liurnya menetes di sudut mulut ketika tidur mendengkur pun—rambutnya tetap selalu indah dan pemandangan itu selalu menghibur. Aku tak akan menyangkal.
Saat Erik mulai berpacaran dengan Alexandria, orang pertama yang tahu adalah aku. Tentu saja.
Waktu itu Erik melesat ke dalam garasi rumah kami di atas skuter Vespa merah (milikku) dan naik ke kamarku dengan masih mengenakan helm. Dalam jaket dan helm dan sepatu botnya yang malas ia lepas, ia mendorong pintu hingga menjeblak terbuka dengan mengagetkan. Aku butuh beberapa detik untuk mengenalinya, kukira dia Densus 88. Atau Robocop. Baru setelah kuingat aku tak menyimpan ganja di kamar atau sedang merakit bom dan ia duduk meraih console PS di depan televisi, kusadari itu Erik yang sedikit sinting.
Ia membisu hingga satu permainan habis dan dia kalah (helm masih di kepala), sebelum berkata dengan nada tenang, “Gua jadian ama Alexandria.”
What the fuck.
Di antara semua mahasiswa di kampus: anak ini. Cinta pertama Alexandria: Erik. Apa Alexa ini baik-baik saja?
Kukira dia mempertahankan kejomloannya selama ini dalam rangka mempersiapkan diri untuk seseorang semacam... Keanu Reeves. Alexandria dulu pernah bilang, kalau dia punya pacar, dia mau laki-laki seperti Aditya Sigma (karena Keanu Reeves sudah jadi pacar semua orang di internet). Bukan Aditya Sigma sendiri, melainkan yang seperti dia. Aku tak tahu kenapa, tapi saat itu kukira hanya karena Aditya Sigma sudah punya pacar. Aditya Sigma adalah senior kami, sang milenial modern, di tahun ketika tinggal satu angkatan milenial yang tersisa di kampus sebelum tersapu oleh kami para Generasi Z. Saat itu rasanya dia keren sekali. Rasanya milenial terlihat keren sekali (presiden bahkan punya tim yang disebut “Staf Khusus Milenial” kendati tak ada yang mengerti apa sebenarnya fungsi mereka). Aditya selalu terlihat santai dengan sejumlah wingmen tim sepakbola (sepuluh orang yang setiap hari saling menggantikan posisi seperti bola bilyar), berjalan melewati para mahasiswa seantero kampus dengan segenap ide cemerlang di kepalanya. Adit selalu punya sesuatu untuk disampaikan, dan selalu menyampaikannya dengan cara yang jelas dan sederhana. Ciri-ciri orang pintar—tanpa perlu menyebutkan dia juga menyenangkan. Dan atletis. Adit dan Erik hampir seperti langit dan bumi.
Namun, malam itu, negara api bisa menyerang dan dunia bisa jungkir balik di depan Erik dan dia tidak akan peduli. Ketenangannya luar biasa. Ia melepas helm itu dan memandangku dengan senyum selebar trotoar jalan M.H. Thamrin.
“Lo nembak Alexa?”
“Gak. Ntar mati, dong.”
Itu lelucon garing dari zaman Firaun masih SD masih laku ya hari ini? Hih. Bikin emosi.
“Kok bisa bilang jadian?”
Dia masih cengengesan, malah semakin lebar. Aku tahu aku seharusnya hanya bilang, gue senang buat lo, bro. Tapi ini seperti mendengar Freddy Mercuri hidup lagi dan makan di warteg pecel Kang Donny di belakang kampus.
“Dia ngirim gue puisi. Gue udah manggil dia sayang.”
Jangan tertawa.
“Terus dia manggil lo apaan?”
“Hei.”
Huahahahahaha.
Tetap tenang.
“Gue senang buat lo, bro.”
Dua minggu setelah itu, kampus seperti menjadi milik Al dan Erik. Mereka bahkan punya ship name: Erixandria. What a cringe. Tapi Erik jadi lebih ganteng. Lebih bersih dan wangi dan bercukur dan kadang-kadang bersisir dan bajunya disetrika sampai licin. Satu-satunya saat aku melihat Erik setampan itu hanya saat ia bekerja sebagai bartender untuk acara gala di sebuah hotel, dan itu karena grooming wajib dari hotel tersebut. Sekampus tiba-tiba jadi sadar dia ganteng (dan memang biasanya di saat seperti inilah orang ketiga muncul karena orang selalu sadar kamu menarik setelah kamu punya pacar, dan bukan waktu kamu masih jomlo). Kurasa itulah masa paling indah dalam hidup Erik di kampus.
Itu lima tahun yang lalu, sebelum negara api menyerang.
Lima tahun berselang dan aku tak pernah tahu persisnya kapan mereka putus. Hal itu menjadi misteri bagi begitu banyak orang hingga begitu lama. Namun Erik kembali seperti semula. Tidak tercukur, tidak bersisir, kadang-kadang tidak mandi, dan naik ke kamarku lewat garasi sambil masih mengenakan helm.
Seperti malam ini.
Malam ini, aku sudah siap untuk menghabiskan set demi set permainan di layar PS hingga pagi atau salah satu di antara kami tertidur ketika sebuah kotak percakapan muncul di layar ponselku. Dari Irvin.
“Njul, lo punya temen yang namanya Alexandria?”
Ini kali pertama nama Al disebut dalam setahun. Aku tak pernah bertemu Alexandria lagi sejak wisuda, tak pernah mendengar tentangnya lagi sebab tak ada alasan. Aku tak tahu bagaimana Irvin bisa kenal Al. Aku berusaha keras mengingat apa mereka pernah bertemu, sementara Erik beringsut mundur sedikit dari layar PS.
Aku membungkuk, memastikan ia tidak ikut memperhatikan layar dan kolom percakapan, lalu mengetik.
“Kenapa emang?”
Tak ada balasan setelah itu, meski kutunggu-tunggu. Set baru permainan sudah dimulai. Mataku terus-menerus melirik ke ponsel. Ketika layar menyala dan kotak itu muncul lagi, itu bukan Irvin.
Melainkan Alexandria.
“Njul, punya temen berapa orang sih yang namanya Irvin?”
Hei, kamu pernah dengar tentang six degrees of separation?
Bukan lagunya The Script, melainkan teori psikologi yang muncul sekitar tahun 1920 yang menyebutkan bahwa semua orang di dunia ini sebenarnya saling terhubung dengan satu sama lain dengan jarak maksimal enam orang di antara mereka. Bila kamu bisa menelusuri keenam orang itu, kamu tak pernah perlu mengenal orang dari awal. Bila salah satu di antara keenam orang itu terhitung dekat dengan kalian berdua, maka secara praktis kalian sudah saling kenal. Birds of a feather flock together. Jodoh tak pernah terlalu sulit bila kamu paham betul teori ini (dan beberapa hal lain).
Namun, kukira, tidak seperti ini juga. Aku tak pernah berharap bahwa satu dari enam orang yang menghubungkan Alexandria dengan orang-orang baru dalam hidupnya adalah aku. Erik sudah cukup. Tak perlu terjadi berkali-kali.
Aku berupaya memisahkan pikiran dan percakapan ini dari Erik sepanjang malam itu. Tak ada satu pun di antara teman-teman kami yang tahu Erik ada di mana saat ini. Ia tak pernah mengungkapkannya, tapi aku yakin Erik sendiri tak ingin diketahui.
Tulisku kepada Alexandria, “Banyak, Al. Lebih dari tiga. Kenapa emang?”
Tak ada balasan dari kedua-duanya sejak malam itu hingga akhir zaman.
*
6 notes
·
View notes
Text
The Princess Saves Herself
Prolog
Pada sepertiga terakhir tahun 2019, berita tentang Alexandria tersebar seperti saat kami masih menghabiskan setiap hari bersama. Seperti dulu, setiap hari dan sepanjang hari selama enam tahun.
Sepertiga terakhir di tahun itu adalah bulan-bulan ketika jalanan Jakarta nyaris tak pernah kami tinggalkan. Pada hari terakhir bulan Septermber, kami telah memadati jalanan delapan jam lamanya. Ini hari ketujuh aksi. Kian malam tampaknya kian tak mungkin surut. Jalanan basah seperginya mobil-mobil tangki yang dikawal pasukan Brimob, setelah menyemburkan air lewat selang-selang raksasa kepada para pengunjuk rasa. Sebab para personil di balik perisai kepolisian sudah tak mampu memukul kami mundur lagi. Sebab mereka sudah kalah banyak.
Langit menghitam oleh residu gas air mata, matahari yang tenggelam, serta bayang-bayang teman-teman kami yang tewas dan tertangkap. Gedung-gedung pemerintahan dan korporat mulai menyalakan lampu-lampunya. Layar-layar neon iklan berkilau di sepanjang jalan. Bisnis dan kekuasaan yang terus bergulir, seolah sengaja menunjukkan bahwa mereka akan tetap demikian kendati hari ini. Kendati kami yang kini basah kuyup, kelaparan, letih dan babak-belur di tepi-tepi. Beberapa di antara kami bertengger di pucuk-pucuk pagar, memanjati atap halte bis, membentangkan kain dan papan-papan yel yang sudah buram. Tersulut oleh perlakuan diam dan sadar bahwa kami mungkin tidak akan pulang hingga malam. Esok kembali mengulangi hal yang sama dan demikian seterusnya.
Sebelum hari benar-benar gelap, seorang peserta aksi di tengah kerumunan berseru sesuatu yang tak mampu kudengar jelas, dan tiba-tiba gelombang massa terhalau mundur seperti air laut tersapu angin. Letupan-letupan gas air mata memenuhi udara. Pasukan berperisai telah kembali maju di balik gelombang itu.
Kami berlari menaiki tangga jembatan penyeberangan jalan, segera memenuhinya dari dua arah. Lampu-lampu telah mengganti cahaya matahari, tapi tiga demonstran—dua laki-laki dan satu perempuan—jatuh terjerembab ke jalan. Sepasang petugas berseragam meraih mereka dan kekerasan selanjutnya sudah dapat diduga. Pukulan tongkat karet di kepala, jambakan rambut, tendangan sepatu bot, sodokan popor senjata di perut sebelum mereka diseret ke pinggir untuk interogasi.
Aku menyadarinya ketika itu.
Desas-desus tentangnya telah beredar selama beberapa hari, hanya saja aku tak percaya. Tak pula ingin percaya dan tak terlalu peduli dan tak ingin peduli. Mereka berkata ada seseorang yang sedang dicari di antara massa itu, dan ia diinginkan dalam keadaan hidup. Aku mengenalnya; orang itu mengenakan jaket alma mater SMA-ku (itu sebabnya berita itu sampai padaku).
Ketika melihat Alexandria, dalam sekejap potongan-potongan cerita pun menggenap sebagai gambar yang utuh.
Ia satu dari yang berlari memanjati tangga jembatan dari seberang tempatku berdiri. Tiga orang yang terjatuh di bawah membuatnya menoleh dan berhenti, tapi ia tahu ia tak bisa berada di sana terlalu lama. Aku tahu itu Alexandria, sebab aku tahu. Bila itu Alexandria aku pasti tahu. Ia mengenakan topi bisbol dan menggulung seluruh rambutnya ke dalam topi itu, mengenakan jaket yang kukira jaket SMA kami, dan tampak seperti dia. Alexa. Al.
Sudah berapa lama sejak kulihat dia terakhir kali?
Ia ada di sini. Alexa yang kukenal selama tahun-tahun panjang itu, meski aku mengira aku tak pernah mengenalnya. Aku berlari memanjati sisa tangga dan menyisipi sosok-sosok peserta aksi yang berlari berlawanan arah. Sedikit lagi. Sebentar lagi. Beberapa langkah lagi akan kujelang dia.
Kelak, di kemudian hari, aku akan tahu bahwa ternyata pergerakan ini tak akan bertahan terlalu lama. Seperti banyak perjuangan sebelumnya. Seperti pengkhianatan yang saat ini sedang kami lawan, hari ini pun nanti akan dikhianati. Namun aku tak tahu ini pada hari itu. Seperti yang lain aku memberikan tekad yang kupunya. Aku tak tahu aku akan menghabiskan hari-hari mencari-cari alasan mengapa aku bersedia dan bersusah-payah ada di sana. Dan dalam terpaan lelah, lapar dan luka, aku hanya memiliki setitik harapan bahwa, saat ini, aku dan Alexa memercayai hal yang sama.
Harapan itu menggerakkanku.
*
3 notes
·
View notes
Text
“Thoughts could leave deeper scarring than almost anything else.”
— Madam Pomfrey (Harry Potter and the Order of the Phoenix)
109 notes
·
View notes
Text
The Right Distance
Ada kenyataan sederhana yang dulu sempat sulit kuterima, yaitu bahwa semua orang tak akan pernah memiliki jarak yang tepat dengan kita. Semua orang, siapapun, hanya akan mampu menjadi terlampau jauh atau terlampau dekat. Terlampau jauh sebab tak ada irisan hidup yang menyatukan kita dengan mereka dalam diagram Venn itu, atau terlampau dekat hingga kita tak sempat menyimpan rahasia. Itu sebabnya banyak dari kita yang memilih sendiri. Tak satu pun dari dua jenis hubungan ini yang membuat nyaman.
Aku terlahir sebagai anak tengah dari lima bersaudara. Kami, aku dan saudara-saudaraku berjarak rata-rata lima tahun kecuali aku dengan adik laki-laki di bawahku persis. Kami terpisah dua tahun setengah. Tak seperti saudara-saudara yang lain, aku tak sempat menjalani peran anak bungsu terlalu lama, dan sebagai anak laki-laki pertama saat itu adikku ini segera merebut semua perhatian. Anak-anak laki-laki pertama di keluarga lain mungkin begitu juga. Aku tak pernah bermasalah dengan ini, tak tahu bagaimana harus mempermasalahkannya saat itu, tak tahu apa itu sebuah masalah. Maka sejak begitu kecil aku terbiasa menemukan jalan sendiri. Tumbuh terpisah dari semua orang, dan aku menyebutnya: growing apart. Selalu sibuk sendiri, terbiasa berpuas hati dengan keberhasilan proyek-proyek kecil yang kubuat sendiri sejak kecil. Lukisan, gaun boneka, tanaman baru, tugas sekolah. Banyak di antaranya gagal juga, tapi ide proyek lain akan selalu memberi semangat baru lagi seolah kegagalan sebelumnya tidak pernah ada. Tak perlu membutuhkan orang lain untuk merayakan keberhasilan. Tak pernah merasa perlu untuk menjelaskan diri sendiri, tak tahu itu untuk apa. Aku tidak merasa begitu butuh untuk diterima, sebab tidak diterima juga tidak apa-apa. Ini menyenangkan, sebab kita memegang kendali dan kuasa akan hidup sepenuhnya. Siapa yang tidak suka akan kendali dan kuasa? Banyak yang sudah mati demi kedua itu.
Aku tak peduli akan validasi orang lain.
Validasi yang kubutuhkan hanya dari diri sendiri.
Seharusnya, dengan keadaan dan kemandirian ini, berada dalam jarak yang terlalu jauh dengan siapapun tak perlu membuatku bersedih. Memang demikian pula yang terjadi, selama puluhan tahun. Ini terasa nyaman sebab aku tak perlu membagi rahasia. Setiap rahasia yang kau bagi selalu berpotensi untuk disalahmengerti (dalam kasusku, hampir setiap kalinya), atau bahkan dibagikan lagi dengan sudut pandang yang jauh berbeda kepada orang lain yang sama sekali tak akan mengerti sedikit pun. Ini runyam, dan ini alasanku tidak membagi terlalu banyak hal. Mereka tak akan mengerti. Maka bila mereka terlampau dekat, yang perlu kulakukan hanya menjauh. Tidak membalas pesan, tidak mengangkat telepon, memblokir, atau memutus setiap serat tali-tali penghubung itu hingga habis sama sekali bila perlu. I keep pushing people away—dengan atau tanpa menyadarinya—dan aku melakukan ini bahkan lebih banyak dan lebih sering belakangan. Setiap terjadi, aku selalu merasa jauh lebih damai. Selalu. Good riddance. Begini lebih baik. Sendiri, terpisah, penuh kendali dan rahasia selalu lebih baik.
Inilah jarak yang tepat. The right distance.
Demikianlah selalu dan seterusnya… hingga aku mengenal dan belajar bagaimana rasanya benar-benar mencintai.
*
Kurasa, itu sebabnya bagiku mencintai terasa lebih baik. Aku memilih untuk mencintai dan bukan dicintai bila harus memilih di antara keduanya (aku sudah menanyakan ini kepada ratusan orang dan sangat sedikit yang berani memilih yang pertama). Sebab itu satu-satunya kesempatan, satu dalam kurun waktu yang biasanya begitu-teramat-sangat lama, aku tak tumbuh terpisah. For once, I grow into somebody; dan pada akhirnya sadar akan semesta yang lain selain dari yang selama ini berputar mengelilingi diriku saja. Ledakan bintang supernova yang terjadi waktu itu masih berlangsung hingga sekarang, kata William Hakim. Semesta ini terus mekar-melebar tanpa batas, jarak orbit kita akan terus menjauh. Di antaranya, miliaran partikel lain terus meletup-letup menciptakan dunia kecilnya masing-masing. Dunia-dunia kecil yang lain ini senantiasa menakjubkan, tak henti-hentinya.
Namun, aku sadar bukan begini cara kerja sebuah hubungan. Serat-serat tali-temali itu tidak berkelindan dalam pola infatuation atau rasa takjub belaka. Tidak seperti cerita dalam roman. Bila kamu menulis roman, atau menulis apapun, segala elemennya harus masuk akal dan pas dan itu sebabnya menulis itu sulit. Hidup tidak seperti itu. Banyak elemen yang tidak masuk akal dalam hidup dan sayangnya ini bahkan membuatnya lebih sulit lagi.
Aku hanya sesekali berpikir—di atas hubungan-hubungan yang dulu tak berhasil—andai aku punya satu contoh saja yang dilakukan dengan benar. Satu contoh benar saja. Sehingga, bisa kuhentikan tepat waktu apa-apa yang tidak pada tempatnya, yang tidak sesuai patokan, dan berkata pada orang itu, please easy down a bit (I need my old self to figure things out). Itu tak akan terlalu sulit. Sesekali aku juga berpikir, mungkin di antara yang kukira good riddance itu ada yang tak perlu kulakukan. Di antaranya mungkin ada satu contoh yang benar yang bisa kujadikan patokan. But sometimes you wound the good and trust the wicked (—Taylor Swift), and then again, how are you supposed to know?
Here is a thing about those who never feel love; they never know if it is not there (—Alyssa, The End of The F***ing World), dan itu berlaku untuk segala hal yang lain. Kita tidak akan tahu kebencian itu bagaimana bila tidak pernah menemukannya. Tak ada yang lahir dengan rasa benci, kita diajari untuk membenci. Itu sebabnya mereka bilang, hurt people hurt people. Orang bisa menyakiti karena sudah pernah disakiti sebelumnya. Kita juga cenderung mencintai dengan cara yang persis sama sebagaimana kita dicintai. Melakukan sesuatu yang tak pernah dicontohkan itu mustahil, seperti harus membuat masakan yang tak pernah kamu cicipi sama sekali. Mustahil, semahir apapun kamu.
Namun, lagi-lagi. Bila telah kutemukan satu contoh yang baik saja, maka formula itu akan berhasil dan aku tidak akan perlu melakukannya lagi untuk kedua kalinya, kan?
*
Maka, yang kumiliki kini hanyalah contoh-contoh yang buruk.
Dan bila yang kau miliki hanya itu, kurasa inilah yang bisa kamu lakukan: yang sebaliknya. Dengan sekuat tenaga berupaya untuk tidak menjadi cermin dari kekeliruan-kekeliruan yang telah dilakukan orang lain kepadamu, dan justru menampilkan versi lawan dari itu (aku tak yakin juga apa ini analogi yang pas, sebab kalau kita bercermin bukankah tampilan itu arah dan sudut pandangnya sudah berlawanan—never mind, though).
Lalu aku ingat akan validasi tadi. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa yang kamu lakukan sudah benar? Biasanya ada validasi, penilaian, atau semacamnya (di sekolah ‘kan caranya begitu). Saat inilah kusadari bahwa mungkin di antara baris-baris di kolom percakapan yang tangkapan layarnya kamu simpan berbulan-bulan, di antara perbincangan di kedai kopi dulu, di dalam takarir foto Instagram dan tweet dengan ikon di bawahnya yang berwarna merah dan hijau, ada pertanyaan yang jawabnya kita damba-dambakan. Am I doing it right? Have I done it right? Validasi. Sayangnya, seringkali tetap saja jawabnya tidak ada, betapapun sahnya itu bagi orang lain. Garis hidup tidak bisa di-copy-paste. Aku sering mendengar ujaran bahwa yang tersulit dari mencintai seseorang itu adalah melihat orang itu mencintai orang lain, dan sejak awal tak paham akan ini. Beberapa di antara kita sudah belajar melepaskan apa yang seharusnya jadi milik mereka sejak usia tiga tahun. Dalam kasusku, dua tahun setengah. Jadi, apa sulitnya? Beberapa di antara kita tumbuh terpisah, dengan kekuatan yang lebih besar untuk melepaskan daripada mempertahankan.
Beberapa dari kita benar-benar tumbuh begitu terpisah.
Sebegitunya sehingga harus bergelut dengan keberanian untuk membiarkan diri mereka dicintai. Untuk sekadar membiarkan orang balas mencintai diri mereka dengan cara mereka sendiri, dengan apa adanya, dan sebagai diri mereka sendiri. Dengan trauma masa lalu, luka masa kecil, terbuka dan telanjang dengan rentan dan bebas dan tak peduli. Di antara kita, bagi mereka, inilah bagian yang tersulit. Sebab miliaran gigabit dan jutaan megapiksel data yang datang secara konstan, setiap hari, mampu dengan mudah menyesatkanmu dalam penilaian, harapan-harapan dan anggapan-anggapan orang lain. Terkadang kau baru akan menyadari itu setelah puluhan tahun terlewat. Namun siapa dirimu bukan datang dari anggapan orang lain—people don’t tell you who you are; you tell them.
Di antara kita ada yang berjuang mengenal rasa aman ini sebab memang tak pernah mendapati itu. Rasanya seperti memberanikan diri untuk jatuh terlentang ke belakang dengan bebas dan penuh rasa percaya bahwa itu tak akan menyakitkan. Karena kau benar-benar dicintai sebagai dirimu.
Bagaimana jarak yang hanya sejangkauan lengan dengan orang lain mampu terasa dekat dan di saat yang sama tetap terasa cukup? Ada di antara kita yang berupaya menghitung algoritma ini. Aku tak punya algoritma ini, sebab aku satu di antaranya.
Namun aku tahu, yang bisa kulakukan untuk memulai adalah mencintai diriku sendiri dahulu. Dan aku baru memahami jawaban itu belakangan. Tersadar bahwa ini akan menjadi perjuangan yang konstan—karena memang begitulah hidup—maka kukira tak apa bila aku melakukannya perlahan. Sedikit demi sedikit memaafkan, menerima, memberi, memaklumi, mengerti, bagi diri sendiri maupun orang lain. Sedikit demi sedikit saja. Dan untuk sementara itu, tetap berada dalam jarak yang selayaknya. Dengan diri sendiri maupun orang lain. Terkadang itulah yang kita butuhkan agar dapat bertahan hidup. Itu pula yang kita butuhkan, dalam arti yang sebenarnya, ketika bencana dan kematian melanda seluruh dunia pada hari ini.
Maka, seperti spasi di antara setiap kata yang membuat kalimat menjadi berarti, pertahankan jarakmu. Sebab, akan ada saat-saat ketika hanya itulah pertahanan yang kamu punya.

14 notes
·
View notes
Text
Unsent
Akan ada beberapa hal tentang rasa sakit yang akan selalu sama, kurasa. Di antaranya adalah bahwa ia tak pernah segera terasa ketika kau jatuh. Ia akan menunggu beberapa hari, dan biasanya hadir dengan perlahan di suatu pagi setelah tidurmu yang lelap. Setelah itu barulah ia menyiksamu.
Will terlelap sepanjang malam di hari ia tiba. Aku akan selalu mengingat Boston Memorial sebagai lorong-lorong putih dalam kesunyiannya yang pekat dan khas. Langkah kaki para perawat seolah berada dalam gerak lamban. Ritme lelah usai menit-menit gawat darurat yang menegangkan, layaknya baris koda dari sebuah lagu. Bulan Februari di luar jendela masih berwarna putih. Lampu-lampu kota menyilangkan sinar-sinarnya menembus pepohonan gundul yang ikut tertidur, menunggu matahari bersinar kembali. Malam akan berjalan lebih cepat mulai sekarang, dan siang akan mulai merangkak lebih lamban.
Hanya bagiku tak ada bedanya.
Aku masih berdentam-dentam, mengikuti detak jarum jam di dinding serta irama tetesan infus yang jatuh ke dalam selang dan mengalir ke bawah kulitnya. Rambutnya mulai tumbuh panjang hari itu, ia hanya mengguntingnya satu kali sejak hari terakhir di SMA. Ikal-ikal meliuk kecil menutupi lubang telinga dan membelit selang ventilator yang bertengger di hidungnya. Dalam skrub hijau rumah sakit aku berharap ia tetap hangat. Adikku pasti akan sembuh, pasti, pasti, pasti—detak jarum jam dan cairan infus itu ikut merapalkannya—dan aku tak ingat kapan mantra ini menidurkanku.
Hingga pada suatu detik segalanya seolah berhenti.
“William?”
Aku tak tahu aku atau dirinyakah yang lebih dulu terjaga. Dalam keremangan bangsal rawat matanya membuka dan bersinar terang, seperti setiap pagi buta di hari-hari sekolah di masa kecil kami. Aku mengerti diazepam hanya melumpuhkan reseptor periferal hingga beberapa jam, tapi ini belum saatnya ia terjaga. Ia tak seharusnya terjaga dengan cara seperti ini.
Sebelum aku sempat beranjak untuk memanggil perawat, kusadari ia hanya menatapku.
“Penghuni bangsal ini sebelumnya meninggal, Nicolas. Jatuh waktu berjalan keluar dari kamar mandi itu.”
“Apa?”
Namun hanya itu yang ia ucapkan. Aku menunggu kelanjutan yang seperti sinyal lemah di ujung telepon, dan ia hanya diam. Kutinggalkan kursi dan beranjak mendekatinya, dan saat itu mulai tak kuyakini apa kedua matanya benar-benar menatapku. Ia masih menatap, tetapi dengan sorot yang seolah menembus ke belakang kepalaku. Aku ikut menoleh ke belakang dan hanya mendapati dinding putih yang mengarah ke kamar mandi yang ia maksud. Apa yang Will lihat?
“Will—“
“Nicolas.”
Sinyal lemah itu masih berkedip pelan. Ia ingin mengucapkannya, dan aku mungkin tak akan mendapatkan saat ini lagi. Maka kukira aku hanya perlu mendengar, tak peduli itu hal paling absurd dari hal-hal absurd yang pernah ia lontarkan. Lengannya terangkat untuk menggapaiku; segera kuraih dan kuletakkan kembali. Nadinya harus tetap lebih rendah dari selang infus—aku bahkan tak ingat apa aku mengutarakan itu pada diriku sendiri atau hanya mengucapkan dalam hati dan ia ikut mendengar.
Di sisi ranjang rawatnya aku membungkuk. “Ada apa, Will?”
“Ingat suatu kali Ayah cerita sepulang berlayar?” bisiknya. “Dia diikuti tiga lumba-lumba di Selat Melaka, sepanjang laut, sampai kapal tiba di pelabuhan berikutnya. Kita belum lama pindah. Kamu dua belas tahun, gue sembilan. Di seberang rumah kita ada pohon kelapa yang tiap pagi dan sore dihinggapi burung yang sayapnya putih. Kadang-kadang di sana sepanjang hari.“
Suaranya serak dan rendah, tetapi ia tenang dan yakin dengan urgensi seolah harus menyampaikan segalanya saat itu juga. Hanya pemakaian kata ganti yang tidak konsisten itu, dan jeda-jeda yang tidak seharusnya yang membuatku yakin ia masih berada di bawah pengaruh obat bius. Dan aku sama sekali tak mengerti yang ia maksud. Masa kecil kami, dalam kenanganku, adalah rumah-rumah yang kami tinggalkan sebelum terlalu lama kami tempati dan kenangan akan kepergian dan kedatangan itu berlapis-lapis banyaknya. Aku ingat pohon kelapa itu, tapi hanya itu. Aku membutuhkan lebih lama untuk menggali rincian sisanya.
Sebelum segalanya hadir, Will telah kembali padaku lebih cepat. Kedekatannya terasa nyata dengan sorot mata yang kini benar-benar jatuh padaku, tidak lagi kepada bayanganku atau bayangan apapun di belakang sana yang sempat menciutkanku beberapa saat tadi. Will kembali, kini dengan kesadaran sepenuhnya.
“Aku tau kenapa burung itu ada di sana, Nick,” ucapnya.
Kurasa aku melihat kenangan itu lewat penglihatannya; pohon kelapa yang tinggi menjulang, pelepah-pelepah daunnya yang mengering dan menjuntai—satu embusan angin saja pelepah-pelepah itu pasti jatuh—dan buah-buahnya yang bundar dan hijau. Lalu seekor burung putih berparuh panjang di pucuknya. Hari itu Rabu, Will kecil dalam seragam sekolah berhenti di seberang rumah kami. Burung itu dari kemarin di sana, ujarnya kepada ibu kami.
“Burung itu dari kemarin di sana,” ulang Will. “Dia menunggu kawanannya.”
Seakan sebuah kelanjutan dari kisah yang membutuhkan sebelas tahun untuk ia tuntaskan. Kelegaan usai kisah itu menenggelamkannya kembali ke dalam ranjang rawat, selang-selang infus dan ventilator serta detak jarum jam. Aku melihat dadanya kembali naik dan turun dalam irama yang sama dengan tetes infus dan ia pun tertidur.
Aku tertinggal di sisi ranjang rawatnya, sendiri dihantui kenangan masa kecil kami.
*
Ayah pertama kali melihat mereka di perairan Sumatera; melompat-lompat di antara buih ombak, melayang dan tenggelam dalam lingkaran-lingkaran di ujung teropong di buritan kapal. Laut tenang dan kapal melaju pelan dengan sinyal kapal lain yang akan melintas dari arah pelabuhan. Ia akan mencapai daratan segera. Ada selang beberapa menit ketika ketiga mamalia itu menghilang. Kapal mengurangi kecepatan, tetapi sebelum Ayah meninggalkan buritan, larik-larik buih putih muncul di atas permukaan air dan tiba-tiba ketiganya telah begitu dekat. Melompat dari dalam air, dan melengkung tajam di udara sebelum kembali tenggelam. Pagi baru menjelang. Bila matahari sedikit lebih tinggi saja, sekumpulan ikan kecil yang mengikuti mereka akan terlihat tak jauh dari permukaan air.
“Small fish swim in schools, large fish swim alone,” ujar Ayah kepada kami.
“Lalu kenapa lumba-lumba berenangnya bertiga?” tanya Will. “Mereka kan besar.”
“Lumba-lumba bukan ikan, mereka mamalia,” jawabku sok tahu.
William, sembilan tahun, ingin ikut ayah berlayar untuk bertemu lumba-lumba ini. “Nanti pas libur sekolah,” pintanya. Tentu saja itu tak mungkin, kalau pun terjadi mereka tak mungkin masih di sana. Aku sudah cukup besar untuk mengerti. Aku pun sudah menghabiskan cukup waktu dengan ayah sejak sebelum ia hadir—satu hal yang Will tak miliki. Will lahir setelah ayah menjadi kapten dan waktunya di laut lebih banyak daripada waktunya di darat. Tahun-tahun ketika hubungan Will dan ayah menjadi sulit kuingat dengan lebih jelas, sebab terasa lama. Sebagai gantinya, ia dan ibu kami memiliki kedekatan yang tak bisa kumiliki.
Aku mengetahui cerita tentang burung putih itu dari Bunda.
“Kamu dengar itu, Nick?” ujar Bunda. Aku baru saja membuka buku PR dan ia berdiri di tengah jendela dapur, dengan leher terjulur ke luar. Sosoknya menghalangi cahaya. “Benar kata Will, burung itu di sana seharian, sepertinya di pohon kelapa yang itu. Lihat? Dengar suaranya? Uwu, uwu, uwu.”
Suaranya benar-benar seperti itu dan Bunda benar-benar menirukannya. Aku menatapnya dengan kening berkerut tak percaya. Aku tak mendengar apa-apa dan aku hanya ingin mengerjakan PR. Aku selalu mengira Will dan Bunda memiliki teritori sendiri, di mana mereka berdua dapat saling mengerti. Teritori itu tak bisa kumasuki sebagaimana yang menurut Will kumiliki dengan ayah. Maka, kubiarkan segalanya berlalu. Namun, beberapa malam setelah hari itu Will merayap naik ke tempat tidurku sesaat sebelum aku terlelap. “Dengar ‘kan, Nick? Burung itu lagi.”
Aku tahu kita membutuhkan kesunyian untuk benar-benar mendengar. Namun di tengah malam itu, saat polusi suara lesap dan frekuensi terkecil pun terasa dekat, kau mungkin tak yakin apakah suara itu benar-benar ada atau hanya gaung dari dalam kepalamu sendiri. Aku melawan kantuk selama Will menatapku lekat-lekat dalam penantiannya akan sebuah pengiyaan, sambil berupaya merasakan irama yang ia dengar. Mungkin benar-benar ada. Mungkin yang kurasakan hanyalah irama Will menirukan suara itu dalam hati, seperti ketika Bunda melakukannya. Maka aku pun mengangguk. “Uwu, uwu, uwu,” kataku. Ia tersenyum dengan kepuasan di matanya, senang sebab ia terbukti dan tak sendiri dengan pikirannya.
Will, adikku.
Tatapannya yang lekat itu—yang masih terasa seperti saat ia sembilan tahun—adalah yang terakhir kulihat ketika mereka menutup pintu bangsal rawatnya dan mendorongku keluar. Subuh bahkan belum menjelang, dan aku sudah membangunkan seisi rumah sakit. “Another relapse,” ia mengerang saat terbangun. Yang kutahu adalah Will ingin aku ada di sana. Namun, dalam kegesitan yang tak mampu kulawan, paramedis dan dokter dalam skrub hijau melesak masuk dengan arus yang menyeretku ke arah sebaliknya.
Ia membisikkannya lagi sambil menatapku pergi. Wajahnya terangkat kepadaku di antara bahu sepasang perawat, “Did you hear the bird, Nick?” lalu mereka merebahkan tubuhnya.
Di depan wajahku, pintu bangsal rawat berayun dan menutup rapat.
Rasanya seperti pengkhianatan. Rasanya seolah semua yang pernah kau cintai di dunia ini tiba-tiba berbalik membencimu.
*
William tak pernah sembuh, tapi tentu saja itu baru kuketahui lama kemudian.
Sweeney, perawat yang menutup pintu Will di depan wajahku itu kini hadir di lorong. Ia menarik pintu itu lagi hingga menangkup di belakangnya, kemudian duduk di bangku di sisiku dan berkata, “Istirahatlah, Mr. Hakim. Anda butuh itu dan nanti William juga. Biar para dokter dan perawat menangani adik anda untuk sekarang.”
Aku sudah mendengar itu berkali-kali meski tanggalan baru saja berganti.
Kuangkat wajahku, menatapnya. “Apa benar penghuni bangsal Will yang sebelumnya meninggal? Jatuh waktu keluar dari kamar mandi?”
Seketika kedua mata perawat itu menyala seperti jendela-jendela rumah di tengah malam yang mengerjap karena alarm berbunyi. Segera kusadari Will lagi-lagi benar, seperti tentang burung putihnya. Never mind, tukasku padanya segera.
Namun ia enggan melepaskannya. “Anda kenal Mrs. Montgomery?”
Don’t think about it, ma’am, ulangku. “Will pasti dengar itu dari perawat lain, dia memperhatikan dan mengingat semua hal. Saya terkejut tadi dia tiba-tiba menyinggung itu, itu saja. Saya kira dia melihat hantu di belakang saya atau apa.”
“Mr. Hakim, kami tidak membicarakan riwayat pasien di depan pasien lain,” ucapnya. “Dan William kehilangan penglihatannya beberapa saat sebelum serangan ini.”
Harusnya aku menyadarinya saat itu.
Harusnya segera kuterima kenyataannya; segalanya tak akan sama lagi. Will tak akan sembuh dan waktu yang disisakan bagiku untuk bersamanya mulai sekarang akan berjalan mundur, kembali lagi kepada saat kami belum sedekat ini, lalu kepada saat ia tak ada di dunia. Harusnya kusadari agar dapat kuhabiskan setiap detik sebesar-besarnya, merentangkan relativitas waktu sejauh-jauhnya. Kami bisa melintasi malam kota Brussel di dalam trem hingga pukul tiga pagi, seperti yang kulakukan untuknya setelah serangan pertamanya di SMA. Kami bisa pergi menonton Red Sox lagi, dengan tiket di baris depan seperti musim lalu. Ia selalu ingin menempuh perjalanan Road 66—harusnya kuluangkan waktuku di musim panas itu. Akan kuterangi setiap malamnya bila aku bisa, dan aku seharusnya memberi lebih banyak lagi. Namun, setelah malam itu, tahun-tahun yang terasa semakin pendek tetap tak membuatku sadar. Kukira ia akan terus ada.
Itulah hari-hari ketika doa-doaku tak terkirim.
William dilepaskan oleh Memorial setelah delapan hari perawatan, dengan jadwal terapi yang membuatnya tetap harus kembali secara berkala. Bulan Maret tiba, tetap putih, tapi matahari bertahan lebih lama. Kami mengemasi barang-barangnya dalam dua tas duffel yang akan kami bawa masing-masing. Ia kehilangan empat pon berat badan, berjanji untuk segera makan banyak, dan berupaya menutupinya dengan berlapis-lapis kaus dan jaket.
Di sisi jendela bangsal rawat itu ia mendorong binder birunya kepadaku.
Ini kali pertama ia mengizinkanku membacanya. Isinya Kalkulus; phi, alpha, beta, sigma yang penuh angka serta simbol-simbol algoritma. Apa-apa yang ia tulis di tempat tidur itu di malam dan siang ketika ia seharusnya tidur.
“Setiap simbol ini mewakili gerak semesta, iya kan, Nick?” ujarnya. “Massa, volume, kecepatan, luas. Phi bagi apapun yang melingkar, square bagi yang melipatgandakan diri. Kita percaya semesta luasnya tak terbatas, terus bergerak dan melebar sejak ledakan bintang tapi bila dikombinasikan dengan persisi tertentu, simbol-simbol ini membantu kita membaca arah dan pola pergerakannya. These are law.”
“That’s some finding,” kataku segera membaca apa yang ingin ia sampaikan. “Jadi apa hubungannya ini dengan burung putih di pohon kelapa di seberang rumah?”
“Lumba-lumba yang ikut ayah pulang waktu itu, Nicolas.”
Kedua matanya bersinar-sinar cerah, dan itu membuatku percaya ia telah sembuh. Binder biru tebal itu tergeletak di atas kasur di antara kami, dan aku akhirnya ikut duduk. Aku masih punya empat puluh menit sebelum kuliah berikutnya, maka kutunggu ia menyelesaikan teori ini.
“Waktu itu musim migrasi dan hewan berpindah ke tempat yang lebih menjamin kelangsungan mereka. Survival instinct—small fish swim in schools, large fish swim alone, remember? Pasti ada lebih banyak lumba-lumba, mamalia atau ikan besar lain yang tiba di pelabuhan di musim itu. Bukan hanya tiga yang mengikuti kapal ayah. Ikan-ikan besar ini membaca arus musim dan memilih perairan yang cerah dan tenang. Ikan-ikan kecil mengikuti mereka. Burung laut, yang ada di rantai makanan berikutnya, bermigrasi mengikuti perubahan suhu dan pergerakan ikan-ikan ini. Tapi di satu atau saat lain dalam migrasi itu, akan ada satu-dua yang tercecer dari kawanan. Glitch—malfungsi kecil sekalipun alam sudah berpola dengan sendirinya. Harusnya sudah ada algoritma yang mengukur pola malfungsi ini.”
Burung itu menanti teman-temannya, rombongan migrasi berikutnya. Siang dan malam bertengger di atas pohon kelapa itu karena itu puncak tertinggi di mana ia dapat didengar. Will mendengarnya. Bunda ikut mendengar. Aku tidak. Selamanya tak pernah tahu bagaimana ia menemukan jalan pulang atau pernahkah ia benar-benar pulang. Tidak ambil pusing. Bahkan ketika jawaban itu tiba di hadapanku di hari itu, yang kupikirkan adalah bagaimana Will sampai memikirkannya. Di sini, sekarang, dan di malam-malam ketika ia setengah tidur dan berada di bawah pengaruh obat bius.
“Dia menunggu kawanannya,” ia menegaskannya lagi, mengulang yang ia ucapkan di malam ia tiba seolah memastikan pintu belakang kisah itu telah benar-benar tertutup. Setelah belasan tahun, sebuah closure.
Ah, William.
“Tapi selama hari-hari itu, tidak ada yang datang.”
Lalu aku pun mengerti.
Aku melihatnya sejelas-jelasnya; sakit yang mendera Will dalam terpejam, denyut di belakang kepala, kegelapan di segala arah, dengan kebingungan haruskah ia menegar rasa nyeri itu dan bertahan. Atau inikah akhir? Hampir bisa kurasakan kalkulasinya akan peluang hidup yang sedang ia perjuangkan, melawan malfungsi yang harus ia jalani. These are law—akan tetapi malfungsi tertentu kadang tetap terjadi. Ia benar-benar berjuang. Will menghitung peluangnya sendiri hingga ia merasa tersesat seperti burung yang ia temukan waktu kecil. Terpisah dari kawanan migrasi, tak tahu haruskah ia melanjutkan perjalanan atau sudahkah saatnya pulang atau ke mana ia harus pulang. Dan kisah Ayah, beserta tiga lumba-lumba yang membuntutinya pulang hadir di waktu yang setepatnya; seperti setiap kenangan yang tak pernah keluar dari istana memori Will.
Tanyaku kemudian, “Terus lo dapat cerita soal Mrs. Montgomery dari siapa?”
Ia langsung menatapku dengan kening berkerut tajam. “Siapa itu Montgomery?” tukasnya, sepenuhnya bingung.
Jawaban itu tak pernah kutemukan.
Aku pun melepaskannya. Pasti perawat selain Sweeney, pikirku, atau pasien lain yang ia temui selagi aku tak ada. Sebab tak mungkin membuktikan kebenarannya juga. Seperti kisah tentang burung putih itu, aku tak menganggapnya penting. Dan seperti kisah tentang burung putih itu juga kurasa jawabnya baru akan kutemukan belasan tahun lagi.
Namun, aku benar akan satu hal. Rasa sakit akan selalu sama; ia tak segera datang ketika kau jatuh dan baru akan menyiksamu beberapa lama setelahnya. Hanya saja, bila kau beruntung dan benar-benar berjuang—seperti William ketika sosoknya melintasi lorong menuju elevator rumah sakit—lama-kelamaan kau akan ikut mencintai rasa sakit juga. Sebagaimana ia mencintaimu.
Kini aku yakin burung putih itu benar-benar ada. Aku tahu ia tak pernah menemukan kawanannya kembali. Tak pernah pulang. Pada akhirnya, dengan sekuat tenaga menciptakan habitat baru dalam keterasingan, berkawan dengan segala yang memungkinkan kelangsungan hidupnya.
Sebab keteguhan itulah yang membuat Will bertahan hingga begitu lama.
*

23 notes
·
View notes
Photo

The Charles River Monster! Regram via @epekho #boston #bostondotcom #summer http://ift.tt/2bPeptH
38 notes
·
View notes
Photo

💖 💚 ❤ 1stlovescotland ❤ 💚 💖
Kilchurn Castle, Scotland
3K notes
·
View notes
Text
destroy the idea that intermediate goals aren’t important. maybe you can’t play the entire piano piece yet, but you can play the right hand and that’s good. maybe you haven’t figured out your major yet, but your minor or your field and that’s progress. maybe you can’t hold a full conversation in your target language yet, but you can ask for directions and that’s fine. setting high goals is good, but don’t diminish the small goals you achieve on your way there. they are just as important.
53K notes
·
View notes
Photo

“August rain: the best of the summer gone, and the new fall not yet born. The odd uneven time.“
Sylvia Plath
2K notes
·
View notes