Text
Why I’ve been gone for so long ....
I'm currently working on a personal project on Wattpad. Kalau tertarik baca fiksi remaja, silakan berkunjung!
1 note
·
View note
Photo



The World Is Spinning
narator, hendery
1096 words
gif by 1aeil
a/n: terinspirasi dari individual teaser hendery
“My dream is to defeat all the bad guys.
But the way I want to do it is a bit different.
It’s through the strongest robot in all the earth.
The biggest, invincible robot.”
Dunia berputar di luar sana, tapi kamu tidak pernah keluar dari garasi.
Kamu sudah hidup di ruang sempit yang hanya cukup memuat satu mobil truk itu selama hampir dua tahun masa studimu. Di titik ini, teman-temanmu tidak pernah lagi menawarkan kepadamu berbagai pilihan apartemen atau shared room. Sejak pertama kali memutuskan akan tinggal di sebuah garasi, kamu sudah yakin kamu tidak akan pernah pindah.
Aku membantumu mencarikan informasi; apakah ada dan di manakah ada seseorang yang menyewakan garasinya untuk dijadikan tempat tinggal di sekitar institut teknologimu? Setelah berbagai usaha, salah satunya merayu orang-orang yang garasinya kautaksir tapi tidak mau menyewakan garasi mereka untuk ditinggali seorang mahasiswa, kita pun menemukan seorang pria Amerika paruh baya berbadan tambun yang mau menyewakan garasinya karena dia membutuhkan kehadiranmu untuk memastikan dia hidup dengan baik, sebab di rumahnya kini dia sendirian. Anaknya yang juga laki-laki dan seumuranmu sudah setahun ini merantau ke luar provinsi, kuliah di sebuah universitas nasional di jurusan ekonomi. Sebenarnya pria yang kelak memperlakukanmu seperti anaknya sendiri itu menawarkan kamar kosong di dalam rumah, tapi kamu lebih membutuhkan garasinya.
"Saya seorang mekanik," katamu di pertemuan pertama kalian, berusaha menunjukkan lebih banyak alasan agar pria itu mau merelakan garasinya. "Saya lebih nyaman tidur di garasi daripada di kamar. Barang-barang saya tidak untuk diletakkan dan disimpan di kamar. Anda akan tahu setelah saya membawa barang-barang saya ke sini."
"Tunggu, Nak, tunggu," kata pria yang rambutnya sudah beruban itu, masih berusaha mencerna. "Lalu nanti kau akan tidur mana? Garasiku sudah kecil. Kalau tempat tidur ditaruh di sana, nanti ruang gerakmu jadi sedikit sekali."
Kamu sudah mengantisipasi jawaban itu sejak lama. Kamu tersenyum, lalu berkata, "Anda pernah dengar bed sofa?"
Lalu pria itu menghubungi anak laki-lakinya, mengatakan padanya bahwa SUV di rumah mereka boleh dia bawa pergi kuliah. Anak laki-lakinya sangat senang dan dengan cepat meluangkan waktu untuk menjemput mobil itu. Kamu berkenalan dengannya. Kalian cepat akrab seperti saudara sepupu. Pria Amerika itu semakin menyukai kehadiranmu. "Tolong jaga ayahku, ya. Kalau dia merokok lagi, tonjok saja perutnya," kata anak laki-laki yang kelak menjadi teman akrab barumu itu sebelum pulang ke rantauan. Kamu mengangguk dengan senyum terlebar yang pernah kulihat.
Pria itu senang mendapat teman, anak laki-laki itu senang mendapat mobil, kamu senang mendapat garasi, dan aku senang melihatmu bahagia. Awal perkuliahan yang bagus, bukan?
Namun, semakin lama, semakin kaulupa bahwa ada kehidupan yang berjalan di luar garasimu.
Kamu mengambil kelas-kelas yang dosennya sering mengadakan kelas online. Kamu mengandalkan rekaman video, rekaman suara, atau catatan dari teman-teman sekelasmu untuk belajar, lalu pergi ke kampus hanya untuk mengikuti kuis dan ujian. Kamu senang mempelajari hal-hal baru dari semesta mekanika yang kamu cintai, tetapi kamu selalu melakukannya dengan cara-caramu sendiri. Rajin kuliah bukan salah satunya. Kamu mengurung diri di dalam garasi kecilmu untuk merakit robot. Kamu terobsesi pada Big Hero 6, Real Steel, Iron Man, Pacific Rim, dan Transformers. Kamu ingin menciptakan robot-robot yang bisa dipertarungkan. Kamu perlu berjuang keras membuat rakitanmu bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Kamu masih perlu berjuang jauh lebih keras lagi agar rakitanmu itu bisa menggerakkan tangan dan kakinya untuk meninju, menendang, dan melakukan lompatan menghindar.
Kemeja-kemejamu tidak ada yang tidak kumal. Kaus-kausmu tidak ada yang tidak belepotan noda hitam, cat, dan oli. Bahkan wajahmu pun kusam, dan aku sudah lupa kapan terakhir kali rambutmu terlihat beraturan. Seharusnya kamu menjaga si pria Amerika, tapi sekarang si pria Amerikalah yang harus memperhatikan kehidupanmu. Dia memasakkan makanan-makanan enak untukmu, membuatkanmu kopi atau susu, membelikanmu kudapan-kudapan dari supermarket, dan menyewa DVD film-film fiksi ilmiah untuk ditonton bersama agar kamu setidaknya keluar dari garasimu ke ruang keluarga dan menghabiskan waktu bersama seseorang di luar semesta mekanikamu, meski ujung-ujungnya kamu jatuh tertidur di tengah film.
Untungnya pria itu tidak keberatan dengan ini semua. Beliau bilang padaku, kamu justru memberinya a sense of life. "Sejak istriku meninggal, putraku berjuang mati-matian menjadi anak yang mandiri. Aku selalu menjadi orang yang diurusnya, dan aku membiarkan dia melakukan itu karena dulu aku memang harus diatur. Aku sempat kacau karena kehilangan wanita yang paling kucintai. Setelah anakku pergi, aku banyak merenung dan menyadari bahwa selama ini aku belum menjadi ayah yang baik. Aku belum melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan seorang ayah kepada anaknya, dan ketika aku ingin melakukannya, anakku sudah tidak ada di sini. Mungkin karena itulah aku sangat senang memanjakan Hendery. Dia membangkitkan lagi gairah hidupku dan membuatku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba menjadi ayah yang baik."
Tahukah kamu dia berpikiran seperti itu? Rasa sayang telah tumbuh di hatinya untukmu, Hendery. Kamu harus lebih banyak masuk ke rumah dan menghabiskan waktu bersamanya, jangan mendekam seharian di dalam garasi saja.
Kamu harus lebih banyak keluar agar kulit dan rambutmu tersentuh udara segar. Kamu harus lebih banyak keluar agar orang-orang tahu kamu masih hidup. Kamu harus lebih banyak keluar agar aku bisa mengajakmu ke tempat-tempat menarik yang kutemukan. Kamu harus lebih banyak keluar agar kehidupan tahu kamu masih berjalan bersamanya.
Untuk itulah, hari ini, aku memutuskan untuk membawamu pergi. Aku sudah cukup percaya diri dengan kemampuan menyetirku (kamu belum pernah melihatku membawa mobil kan?), dan sebuah villa yang dipesan Ten sudah menunggu kita di pinggir danau. Kamu harus keluar dan bertemu dengan teman-teman kita. Aku yang akan melakukannya untukmu kalau kamu tidak mau.
"Aku belum menyelesaikan kepalanya," keluhmu saat aku datang menginvasi garasimu. Rencananya, selama kita menginap dua hari satu malam, ayahmu akan memanggil jasa bersih-bersih untuk membersihkan lantai dan dinding di dalam garasimu. Dia akan memastikan tidak ada barang yang berpindah letak karena itu pasti akan membuatmu marah.
"Kepala itu bisa menunggu," kataku tidak mau tahu seraya memasukkan baju-bajumu ke dalam ransel. "Kita hanya pergi sebentar. Kamu masih punya banyak waktu setelahnya untuk menggua di dalam tempat ini lagi sampai pergantian abad."
Kamu membuat suara-suara mengerang seperti seseorang yang baru bangun tidur.
"Selain itu," tambahku, "kamu harus keluar untuk merasakan bumi masih berputar."
"Bumi masih berputar walau kita hanya berdiri saja di sini."
"Ayo!" Aku tidak menghiraukan gerutuanmu dan menarikmu keluar. Kamu akan duduk di sampingku selama dua jam perjalanan, tidak melakukan apa-apa selain memandang ke luar jendela, menyimak berita-berita internasional di radio, atau tertidur dengan kepala miring.
Aku tidak keberatan. Aku sudah cukup senang merasakan bangunan-bangunan menghilang ke belakang dan pemandangan berubah menjadi pepohonan hijau dan langit biru sejauh mata memandang. Aku sudah cukup senang melihatmu berada di dalam lukisan alam itu meskipun kamu sendiri tidak tampak antusias, sebab kini kamu keluar dari kotakmu dan aku merasa tidak ada lagi sekat yang membatasi duniaku dengan duniamu. Aku sudah cukup senang kita berada di tempat yang sama, di dalam mobil ayahku dan di villa pinggir danau yang terbuka, bukan aku di dalam kamar asramaku dan kamu di dalam garasimu.
Aku sudah cukup senang kamu keluar dari garasi dan dunia kita sekarang berputar bersama-sama.
a/n: might be the beginning of a new au. we’ll see~
3 notes
·
View notes
Photo



Not Over You
hanjin, keane
916 words
gif cr.
a/n: this was fun to write. i think it’s my first time writing a story with a theme of broken-up lovers? i got to explore new feelings and insights i haven’t ever written before even though just briefly. still counted as a new experience tho :) also, it’s my very first fic of kun! i’m proud of how it turned out.
Hanjin sudah hampir mengitari toko baju ini. Sudah selesai keliling melihat-lihat setiap gantungan dan tumpukan. Sudah capek deg-degan dan dengan putus asa berharap tubuhnya punya kemampuan menangkal rasa gugup. Setiap beberapa saat ia selalu melihat ke arah kerumunan yang lewat di sekitarnya. Jangan-jangan dia sudah datang tapi diam-diam? Ini pasar malam Sekaten, lho. Di alun-alun. Tempatnya luas dan terbuka. Ada banyak tempat untuk bersembunyi di dekat tenda toko baju di mana Hanjin menunggu. Dia pasti mau ngagetin, batin Hanjin yakin, kayak dulu.
Lalu Hanjin sadar, memangnya dia masih mau melakukan itu?
Sudah beberapa waktu berlalu dan ia masih merasakan hal yang sama saat akan bertemu dengan laki-laki itu. Membuat Hanjin merasa bodoh dan ajaib di saat yang sama. Bodoh karena ternyata laki-laki itu masih berefek baginya, dan ajaib karena perasaan ini bisa tak terpengaruh oleh waktu, seakan-akan membeku di ruang yang sama di tempat Hanjin terakhir kali meninggalkannya.
Ponsel Hanjin berbunyi, menerima pesan yang ia tunggu-tunggu sejak tadi. Kamu di mana? Aku udah di deket toko baju yang kamu sebut. Hanjin celingukan sekali lagi, dan kali ini berhasil menemukan sosok yang ia tunggu di luar tenda toko baju. Rambut cokelat gelap, jaket denim, dan jins hitam yang sangat familier. Hanjin menenangkan diri sebentar, lalu menghampiri laki-laki itu.
"Keane," sapa Hanjin.
Keane menoleh, tersenyum pada Hanjin--senyum bergaris dan berlesung yang ramah dan akrab yang selama ini selalu meyakinkan Hanjin kalau semuanya akan baik-baik saja sampai akhirnya senyum itu sendirilah yang terluka--dan lepas dari semua yang telah terjadi, Hanjin senang bisa melihat senyum itu lagi. Hanjin senang senyum itu terarah kepadanya lagi.
"Ah, di situ kamu," Keane menyambutnya. Setelah itu, mereka jalan-jalan keliling pasar malam Sekaten. Keane bilang dia hanya ingin lihat-lihat, sebab sudah lama dia tidak ke sini. Pengin tahu apa saja yang sudah berubah, katanya. Lalu Hanjin bertanya, “Emang kapan terakhir kali kamu ke sini?” Pertanyaan itu seperti mengingatkan mereka kalau waktu sudah berlalu lumayan jauh. Tetapi Keane menjawab, “Dulu, sama kamu, sebelum aku pindah.” Dan tiba-tiba, hari itu kembali terasa seperti kemarin. Hanjin ingat mereka berburu baju murah, membelikan oleh-oleh untuk saudara Keane, membeli gorengan untuk cemilan mencicil tugas, dan membawa pulang permen kapas.
Malam itu adalah malam yang indah.
Hanjin bertanya lagi, “Trus, kenapa kamu tiba-tiba balik?” Itu pertanyaan yang ia pendam semenjak teman lamanya pertama kali memberitahunya kalau Keane sedang mencari kontak barunya yang bisa dihubungi. Keane, yang sejak mereka berpisah Hanjin kira sudah lupa padanya dan tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Sayangnya Hanjin mengutarakan pertanyaan itu di saat yang kurang tepat. Pertanyaannya keluar di saat ia dan Keane berjalan di tempat yang ramai dan harus berpisah sebentar memberi ruang bagi pengunjung lain untuk lewat di tengah mereka. Keane tidak mendengarnya.
Hanjin memutuskan untuk berhenti berusaha dulu. Belum waktunya. Nanti saja, kalau suasananya lebih kondusif, pikirnya. Lalu melupakan pertanyaan itu untuk sementara. Lagi pula, tidak terjawab hari ini juga tidak apa-apa. Malam ini ia hanya akan membantu teman lamanya--si Keane itu--menemani jalan-jalan di pasar malam Sekaten. Mungkin sebaiknya ia fokus di situ dulu.
“Kangen, ya,” kata Keane. Mereka duduk bersebelahan di kursi plastik, menunggu sosis bakar. Keane sedang memandang jauh ke arah area wahana bermain yang suasananya lebih gemerlap daripada area pertokoan tempat mereka berada. Lampu-lampu dan tenda-tenda warna-warni tampak kontras dengan langit malam. Gelombang-gelombang manusia mengaliri setiap celah di antara tenda-tenda dan lapak-lapak penjual. Asap bebakaran jajanan ringan bertabrakan dengan gelembung sabun yang ditiup anak-anak kecil. Suara ribuan manusia bertumpukan dengan gemuruh mesin-mesin wahana bermain. Semarak dan berisik. Hanjin tidak yakin ia baru saja mendengar Keane bilang sesuatu yang terdengar seperti “kangen”.
“Hm? Apa?” tanyanya, sedikit mendekatkan kepala untuk mendengar lebih jelas.
Keane juga mendekatkan kepalanya sehingga dia mengulang perkataannya tadi di depan telinga Hanjin. “Kangen!” sahutnya.
“Kangen?!” Hanjin balas menyahut karena tiba-tiba toko alat dapur di belakang mereka berpromosi keras-keras pakai speaker. “Ooh! Iya! Aku juga baru kali ini ke Sekaten lagi!”
“Bukan sama Sekaten!” Di saat Hanjin berpikir Keane mungkin bermaksud bilang kangen suasana kota ini, Keane menambahkan, “Sama kamu!”
Hanjin menatap Keane. Keane tertawa. Tawa yang membuat garis di pipinya semakin terlihat. Lalu Hanjin ikutan tertawa--ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana lagi. Mau ngomong juga susah saking berisiknya tempat ini. Setelah sosis bakar mereka matang, dibungkus, dan dibayar, Keane mengajak Hanjin pergi. Katanya mau cari tempat makan yang lebih sepi (yang juga berarti tempat yang lebih nyaman untuk mengobrol. Hanjin jadi berpikir, mungkin mengajaknya ke Sekaten hanyalah cara Keane untuk mencairkan suasana canggung di awal reuni kecil mereka ini). Mereka akhirnya jalan kaki meninggalkan kawasan alun-alun. Motor Keane diparkirkan agak jauh dari sini, sengaja cari yang lengang. Sesampainya di sana, sebelum Hanjin memakai helm yang sudah dibawakan Keane untuknya, Keane menyodorkan ponsel ber-case merahnya yang sudah tersambung dengan sepasang earphones putih.
“Apa?” tanya Hanjin bingung.
“Dengerin lagu ini sampai kita sampai di tempat makan,” kata Keane, masih dengan senyum yang lama-lama membuat Hanjin ingin lumer seperti mentega di loyang martabak. Kali ini senyum itu terlihat malu-malu sedikit.
“Lagu apaan, sih?” Hanjin berusaha bersikap santai.
“Tadi kamu nanya kan, kenapa aku balik ke sini,” kata Keane. “Jawabannya ada di lagu itu.”
Mampus, ternyata dia denger. Hanjin seketika deg-degan lagi. Keane tidak menunggu lebih lama. Dia menggenggamkan ponsel dan earphones ke tangan Hanjin, lalu mengenakan helm dan mengeluarkan motornya dari area parkir.
Hanjin membuka layar ponsel Keane, menemukan hanya ada satu lagu di playlist berjudul “Hanjin”. Kalau bisa berubah jadi martabak, Hanjin benar-benar ingin melakukannya sekarang juga. Satu-satunya lagu di playlist itu adalah Not Over You-nya Gavin DeGraw. Lupakan martabak. Hanjin ingin berubah menjadi gelembung sabun dan melayang ke angkasa.
and if i had the chance
to renew
you know there isn't a thing i wouldn't do
i could get back on the right track
but only if you'd be convinced
so until then
if you ask me how i'm doin'
i would say i'm doin' just fine
i would lie and say that you're not on my mind
but i go out
and i sit down
at a table set for two
and finally i'm forced to face the truth
no matter what i say
i’m not over you
not over you
1 note
·
View note
Text
memperkenalkan: didit

lovebug
mucha + didit
271 words
based on @semestakatarsis‘s drabble
“heh. cowok rambut milo.”
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
didit pura-pura tidak dengar, matanya fokus ke buku di tangannya, tapi tetap menyunggingkan senyum lebar yang mucha suka. yang memanggil datang mendekat, menyikutnya pelan. baru didit menoleh, alisnya naik, masih senyum, matanya seperti bertanya— apa, cha?
Keep reading
2 notes
·
View notes
Photo



Anak Laki-laki Berambut Cokelat Pastel
mucha (@duniamucha), didit
696 words
gif cr. nctwinwin
Anak laki-laki berambut cokelat pastel itu baru saja selesai memperlihatkan aksi-aksi tari akrobatik tradisional yang berhasil memukau orang-orang yang duduk di sekitar panggung terbuka. Begitu musik gaduh yang mengiringinya berhenti, semua orang bertepuk tangan. Bertopang dagu, Mucha memperhatikan bagaimana anak laki-laki itu minggir dari panggung dan tersenyum pada temannya yang memberinya sebungkus tisu dan sebotol air putih. Senyumnya lucu sekali, Mucha berkomentar dalam hati. Pencahayaan di pinggir panggung terbuka tempat anak laki-laki itu dan teman-temannya berkumpul agak remang, tapi rambut anak laki-laki itu tetap terlihat sedikit lebih terang dibanding rambut anak-anak lainnya. Warna yang selalu mengingatkan Mucha pada susu Milo. Mucha tersenyum, terbayang segelas Milo hangat.
Anak-anak klub teater tradisional Asia tak terlihat lagi di panggung terbuka. mereka kini berkumpul di dekat kolam kodok di belakang panggung terbuka yang tak terlihat oleh Mucha. Evaluasi latihan hari ini, mungkin. Sudah jam dua belas malam lebih. Mucha duduk terkantuk-kantuk di bangku bermeja di depan perpustakaan. Masih berusaha mengerjakan tugas review yang deadline-nya dua hari lagi.
Lingkungan di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi padang bunga. Mucha berputar-putar di sana. Ratusan kelopak bunga ikut berputar bersamanya, lalu beterbangan di angkasa. Bulan bersinar terang sekali, tapi cahayanya pucat, seperti lampu yang bersinar redup. Mucha melihat anak laki-laki berambut susu Milo tadi sedang duduk di atas batu besar. Senyum Mucha mengembang lebar. “Didit!” panggilnya. Didit ikut tersenyum.
Hal terakhir yang Mucha ingat adalah ia berlari ke arah Didit; kelopak-kelopak bunga beterbangan di sekitar kakinya. Tetapi tiba-tiba Mucha merasa dirinya memudar, dan dagunya yang meluncur dari tangan yang menopangnya mengagetkannya sampai terbangun dari mimpi.
Hal yang pertama Mucha lihat dan dengar adalah anak laki-laki berambut susu Milo tadi sedang tertawa di depannya. Melihat Mucha terbangun, dia berkata, “Udah bangun, Cha?”
“Eh--Iya, iya, udah,” Mucha menjawab linglung. Butuh beberapa detik baginya untuk menyadari ia masih duduk di bangku kampus dalam usaha menyelesaikan tugas. Lalu ia meraup wajah dan menghela napas keras. “Astaga… Sempet-sempetnya ketiduran.”
Terdengar Didit tertawa lagi. Dia sudah duduk di depan Mucha entah sejak kapan, bercanda dengan teman sesama anggota klubnya yang sekarang sudah pergi ke arah Plaza Gedung C. Baju didit sudah bukan lagi kostum latihan teater, melainkan jaket yang dilintangi tali tas selempang. Masih ada beberapa orang selain mereka yang tampaknya akan lebih memilih menginap di ruang-ruang sekre malam ini daripada pulang ke kos. Mucha harus segera pulang sebelum menjadi salah satu dari mereka.
“Minggu ini kamu begadang terus, Cha,” celetuk Didit.
Mucha menghela napas. “Kamu tau nggak sih, Dit? Udah empat hari ini aku hidup kayak zombie. Empat hari!” Mucha menekankan dengan keempat jarinya. “Tidur, kuliah, nugas, repeat. Kayak gitu terus sampe-sampe berenti bentar liat langit aja nggak sempet. Dari kos berangkat sambil merem, di kelas merem, pulangnya juga sambil merem.”
“Trus kapan, dong, meleknya?”
“Nih.” Mucha mengacungkan bundelan kertas yang harus ia review. “Pas nugas.”
“Sama satu lagi.” Didit ikutan mengacungkan jari telunjuk. Lalu, jari telunjuk itu ditunjukkan ke arah wajahnya sendiri. “Pas liat muka aku.”
Bundelan kertas Mucha serta-merta ditepukkan ke kepala Didit. Mereka tertawa.
Setelah itu, Didit mengajak Mucha pulang. Mereka berjalan bersama sampai melewati bunderan dan menyeberangi jembatan, lalu Mucha harus belok ke kanan. Didit belok ke kiri. Mereka berpisah di pertigaan. Tinggal jalan sedikit lagi, Mucha sudah sampai di kosnya. Tiga warung yang ia lewati masih sama-sama buka. Anak-anak kos sekitar sini biasanya nongkrong di sana untuk begadang. Wangi kopi yang mengudara di jalan kecil itu seharusnya membuat Mucha lebih terjaga. Tapi ia sudah capek sekali. Tinggal merem saja ia bisa tidur sambil berjalan.
Ketika baru saja sampai di depan kos, ponsel Mucha berbunyi. Didit menelepon.
“Halo, Dit?”
“Oh, jawab ternyata,” kata Didit di seberang sana. “Kirain jalan sambil ketiduran.”
Mucha tersenyum. “Udah sampe kos?” tanyanya sambil membuka gembok gerbang.
“Lagi pesen nasi goreng di warung. Aku denger suara gerbang dibuka.”
“Iya, ini aku baru nyampe kos.”
“Langsung tidur, ya. Biar besok bisa melek lihat langit.”
Mucha kira Didit masih mau mengobrol, tapi ternyata setelah Mucha bilang “Iya, iya” sambil tertawa, Didit bilang “Dah, ya” lalu menutup telepon.
Mucha masuk ke kos sambil senyam-senyum. Ia memutuskan untuk menyeduh segelas Milo, tapi begitu kepalanya menyentuh bantal, ia kembali menari-nari di padang bunga yang tadi dan Milonya menjelma menjadi seorang pangeran yang rambutnya cokelat pastel bernama Didit.
3 notes
·
View notes
Photo



A Day in the Theme Park
cindy, winwin
1289 words
gif cr.
a/n: personal favorite ♡
Cindy tidak tahu lagi siapa yang sedang bete di sini. Mereka datang ke taman hiburan ini karena Winwin minta ditemani main-main. Pengin memperbaiki suasana hati yang jelek seharian, katanya. Seharian apanya kalau sebelum dua puluh empat jam saja dia sudah tertawa-tawa lagi menikmati apa pun yang menarik perhatiannya di tempat ini. Cindy ditinggal-tinggal terus seakan-akan dia hanya datang sendiri. Tiap kali Cindy bilang mau pulang saja, Winwin mencegahnya. Cindy jadi tidak tahu lagi apa yang sebenarnya ia lakukan di sini. Mengasuh bayi?
Demi Tuhan, Cindy kira mereka berpacaran.
Setelah puas memotret gerbang wahana rumah hantu yang atraktif, Winwin menghampiri Cindy yang duduk di bangku dengan tangan bersedekap dan kaki menyilang. Antara tidak menyadari dan tidak peduli suasana hati Cindy yang gantian memburuk, Winwin berkata, “Aku pengin es krim. Ayo temani aku beli es krim.”
“Ayo temani, ayo temani,” ulang Cindy sebal. “Dari tadi juga kamu pergi-pergi sendiri. Kenapa masih harus ditemani?”
Winwin tidak mendengar itu. Dia sudah berjalan duluan mencari penjual es krim. Sambil mengerang, Cindy berdiri dan pergi menyusulnya. Mereka menemukan ice cream truck berwarna pink di dekat kolam air terjun berpatung putri duyung. Winwin langsung mengantre. Cindy mengatakan rasa yang ia inginkan, lalu menunggunya sambil bersandar pada pagar kolam air terjun.
Tak lama kemudian, Winwin selesai membeli dan sekarang menggenggam secontong es krim cokelat-vanila yang dia sesap-sesap dengan puas.
Cindy kebingungan. “Es krimku mana?”
Winwin juga ikut kebingungan. “Kukira kamu mau membelinya sendiri?”
Wah… Ingin sekali rasanya menceburkan cowok ini ke kolam air terjun.
“Bodo, ah. Lupakan saja,” kata Cindy, mengibaskan tangan lelah sebelum membalikkan badan dan mencari jalan menuju pintu keluar.
“Cindy! Mau ke mana?” Winwin menyahut.
“Pulang!”
“Hei, hei! Aku bercanda!” Secepat mungkin, Winwin kembali ke ice cream truck. Dia langsung ke konter dan mengambil es krim lainnya, lalu dengan hati-hati berjalan cepat menghampiri Cindy. “Aku beneran bercanda. Sudah kubelikan dari tadi, tapi seharusnya kamu bertanya aku bohong atau tidak.”
Cindy menerima es krim yang diberikan Winwin. “Aku benar-benar merasa seperti membuang-buang waktu, tau ngga sih? Dari tadi kamu keluyuran sendiri, aku ditinggal di belakang.”
“Maaf. Aku hanya sedang merasa membutuhkan waktu sendiri, tapi tidak ingin sendirian. Maafin aku. Ayo, sekarang kita pergi bersama.”
Winwin menggunakan tangannya yang tidak memegang es krim untuk menggandeng tangan Cindy. Dia berulang kali menoleh ke arah Cindy dan menatapnya dengan senyum bersalah, seperti sedang mengecek apakah Cindy masih marah. Sedang membutuhkan waktu sendiri tapi tidak ingin sendirian, katanya tadi. Seharusnya dia mengajak Cindy ke tempat lain yang lebih privat kalau memang itu yang dia inginkan, seperti yang biasanya mereka lakukan kalau sedang ingin bersantai. Duduk-duduk di kafe, nonton film di bioskop, nonton drama di apartemen Cindy, tidak melakukan apa-apa di apartemen Winwin (Cindy yang tidak melakukan apa-apa--mungkin hanya membaca atau browsing atau apa pun itu sementara Winwin main game). Bukan taman hiburan yang menyita banyak energi dan membuat Cindy merasa tak nyaman kalau ditinggal sendirian.
Tapi setelah membeli es krim, Winwin tidak keluyuran seenaknya lagi. Malah cenderung mengajak Cindy ke mana-mana dan mulai lebih banyak bicara dibanding sebelumnya.
Mereka tidak berniat naik atau masuk wahana apa pun karena Winwin hanya ingin sightseeing. Menurutnya taman hiburan juga bisa dinikmati dengan cara itu karena warna-warnanya yang saling tabrak sudah merupakan keindahan tersendiri. Balon, permen kapas, es krim, badut, aneka mainan, patung-patung karakter, makanan dan minuman ringan yang bisa dinikmati sambil jalan, wahana-wahana yang desain dan eksteriornya unik-unik. Apalagi ketika sudah sore begini. Lampu-lampu mulai dinyalakan dan menambah pemandangan yang sudah indah dengan kerlip-kerlip cahaya yang cantik. Cindy jadi terpesona. Maksudnya, terpesona pada Winwin yang kelihatan sangat menikmati dan tersenyum terus sejak tadi.
Di saat langit mulai terbagi warnanya menjadi kebiruan di sisi timur dan kekuningan di sisi barat, Cindy kira ini sudah waktunya untuk pulang. Namun, Winwin malah berkata, “Tunggu dulu. Aku harus memfoto sunset dari tempat yang tinggi dulu.”
Cindy mengerjap heran. “Tempat yang tinggi? Menara kastel?” Ada wahana kastel ala kerajaan negeri dongeng yang punya menara dan benteng tinggi. “Tapi bukannya kamu takut ketinggian?”
“Makanya aku butuh bantuanmu. Ayo.”
Winwin menggandeng Cindy lagi. Bukan ke arah kastel, melainkan bianglala raksasa yang lampu di sekujur rangkanya sudah dihidupkan. Cindy terbelalak. “Mau naik itu?!” pekiknya di tengah keramaian pengunjung.
“Dari atas sana, kita bisa lihat matahari tenggelam di laut!” sahut Winwin.
Selama mengantre, malah Cindy yang gugup. Ia menatap Winwin dari samping. Cowok itu lebih sibuk melihat-lihat koleksi fotonya di galeri ponsel ketimbang mengkhawatirkan apa yang mungkin terjadi di dalam bianglala nanti. Sebagai pacarnya, Cindy sering mengklaim dirinya sebagai orang yang paling mengerti Winwin di depan anak-anak kampus. Makanya banyak teman mereka yang berkonsultasi pada Cindy ketika harus berurusan dengan Winwin. Bagi mereka, Winwin itu dingin dan galak. Bikin segan. Cindy beruntung telah menyaksikan lebih banyak sisi Winwin yang lebih baik dan lucu daripada itu, tetapi ada kalanya ia masih sulit mengerti kemauan dan jalan pikiran cowok itu. Seperti sekarang ini, misalnya. Sudah tahu takut ketinggian, masih mau naik bianglala demi foto sunset? Memang bianglala taman hiburan ini sangat tinggi dan terkenal overlooking pemandangan pesisir pantai dan lautan yang mengagumkan, tapi seharusnya Winwin tidak perlu memaksakan diri.
Tiba giliran mereka untuk naik.
“Winwin, kayaknya kamu nggak harus seniat ini, deh,” Cindy berusaha membujuk.
Winwin malah memejamkan mata dan mengulurkan tangannya. “Pegang tanganku,” suruhnya. “Cepat,” katanya lagi saat Cindy hanya terdiam tak mengerti. Cindy akhirnya menurut. Ia sudah tidak tahu lagi apa yang sebenarnya dilakukan cowok ini. Mereka masuk ke kompartemen bianglala yang sudah terbuka untuk mereka. Sampai duduk berhadap-hadapan dan bianglala mulai berputar, Winwin tidak membuka mata. “Beri tahu aku kalau kita sudah berhenti di atas,” katanya.
“Kamu nggak bermaksud merem terus sampai giliran kita selesai kan?”
“Aku hanya akan membuka mata untuk memfoto sunset.” Winwin terdengar penuh tekad. “Ngomong-ngomong, kamu ingat anak yang kacamatanya ketinggalan di kelas waktu ujian?”
Cindy mengerti Winwin memulai pembicaraan random supaya pikirannya teralihkan. Dia pasti sudah belajar dulu caranya mengatasi rasa takut akan ketinggian, Cindy menyimpulkan. Winwin pernah cerita, dia pernah naik bianglala bersama temannya (seorang senior di kampus) dan berakhir freaking out karena mentalnya kurang persiapan. Cindy memutuskan untuk menggenggam tangan Winwin dan mengaitkan jari-jari mereka supaya Winwin tahu dia tidak sendirian di atas sini. Lama-lama Winwin memain-mainkan jari-jari Cindy sebagai pelampiasan rasa gugup sambil terus mengobrol dengan mata tetap terpejam.
Bianglala berhenti bergerak. Cindy memberi tahu Winwin mereka sudah di puncak. Winwin membuka mata dan langsung menoleh ke arah matahari. Pada saat itu Cindy mesti menahan napas sesaat karena pemandangan di depan matanya sangat menakjubkan. Timing mereka pas sekali; matahari sudah menggantung tepat di atas horizon, menyiram lautan dengan warna oranye kemerahan. Permukaan air yang terus berombak membuatnya tampak berkilauan. Yang lebih memukau lagi adalah pemandangan Winwin memotret sunset itu. Cindy sampai mengeluarkan ponselnya sendiri untuk mengabadikannya.
“Ngapain, sih,” Winwin tertawa. Makin semangat Cindy memfotonya. Kamu cakep banget, Cindy bilang dalam hati, sampai-sampai bisa saingan sama sunset.
Mereka menghabiskan sisa waktu untuk selfie sampai akhirnya bianglala berputar lagi dan Winwin harus memejamkan mata lagi.
“Kamu kayaknya motret-motret untuk special occasion. Buat kado seseorang yang ulang tahun, ya? Siapa?” Cindy membuat Winwin mengobrol seperti tadi.
Winwin menggeleng sambil tersenyum. “Nggak ada. Sudah kubilang, ujianku ada yang nggak lulus satu. Aku hanya ingin menghibur diri dan kebetulan lagi pengin motret-motret. Sudah lihat blog Johntography? Fotonya keren-keren.”
“Hmm. Memang nggak perlu special occasion, sih, untuk bersenang-senang. Tapi kalau lagi jalan sama orang lain, jangan nyuekin dia terus.”
Winwin tertawa kecil. “Iya, maaf.”
“Aku sampai pengin pulang beneran tadi.”
“Iya, maaaaf, Nona Cindy! Kan aku udah minta maaf.” Winwin meremas tangan Cindy gemas.
“Maaf, maaf. Harusnya kamu minta maaf waktu aku hampir hilang di dekat korsel tadi.”
Cindy mengulang-ulang curahan kekesalannya, membuat tawa Winwin semakin panjang. Setelah keluar dari bianglala, Winwin merangkul lengan Cindy sekaligus menggenggam tangannya erat seakan-akan takut Cindy mungkin akan hilang kapan saja. Mereka memutuskan untuk makan malam dulu sebelum pulang. Tadi Cindy merasa seperti mengurus bayi. sekarang ia merasa seperti orang paling bahagia sedunia.
2 notes
·
View notes
Photo



Under the City Lights
naz, jaehyun
993 words
gif cr.
Mereka selalu lewat di jalan yang sama, dan selalu ke arah yang berlawanan. Naz sudah cukup lama memperhatikannya. Mantel cokelat, tas hitam, sepatu Converse kuning. Sepatu itu yang paling mencolok. Sepatu itu juga yang membuat Naz dengan mudah mengenalinya setiap kali mereka berpapasan, terutama ketika laki-laki itu sedang mengenakan masker. Lama-lama yang Naz hafal tidak hanya sepatunya. Naz hafal figurnya, tatanan rambutnya, wajahnya, senyumnya. Yang belum Naz tahu adalah suaranya. Mereka tidak pernah saling sapa, apalagi mengobrol. Kenal saja tidak. Dan Naz tidak tahu di mana lagi mereka bisa bertemu kalau bukan di jalan itu.
Naz membiarkan ini. Di saat ia baru menyadari soal laki-laki yang sama yang selalu berpapasan dengannya di jalan yang sama ketika ia baru pulang dari kesibukan yang membuatnya baru bisa keluar menjelang tengah malam, Naz sempat ingin tahu lebih banyak tentang laki-laki itu. Ia pernah satu kali mencoba mengikutinya untuk mencari tahu ke mana laki-laki itu pergi, tetapi laki-laki itu selalu mengakhiri perjalanannya di daerah ini dengan naik bus. Naz tidak seberminat itu menguntitnya. Terlebih ia sudah tahu bus yang ditumpanginya itu pergi ke mana saja. Menurut Naz, itu sudah cukup. Semenjak saat itu, Naz memutuskan untuk membiarkan ini. Ia menikmati momen-momen berpapasan itu tanpa mengharapkan apa-apa. Seakan-akan, itu sudah menjadi rutinitas kecilnya yang terjadi hampir setiap malam. Rasanya seperti punya rahasia bersama seseorang yang terlalu asing untuk dianggap teman, tapi terlalu familier untuk dianggap orang asing.
Hingga pada suatu hari, mereka bertabrakan.
Keduanya sama-sama tak memperhatikan jalan. Laki-laki itu tertunduk memainkan ponsel, Naz terlalu sibuk mencari kunci apartemen di dalam tas. Bahu mereka akhirnya saling tabrak dengan tidak begitu keras, tetapi cukup keras untuk menjatuhkan ponsel yang Naz pegang ke permukaan trotoar. Ponsel laki-laki itu juga jatuh, terlepas dari earphones yang tersambung di ujungnya dan meluncur bebas ke bawah. Lalu keduanya sama-sama terpana melihat layar ponsel mereka yang tergeletak bersisian.
Mereka sedang mendengarkan lagu yang sama.
When I Fall in Love-nya Nat King Cole.
Sampai sepuluh detik berikutnya, mereka terlalu terpukau untuk melakukan apa pun. Itu adalah sepuluh detik teraneh yang pernah terjadi dalam hidup Naz. Bertabrakan dengan orang yang tak dikenal dan mengetahui mereka ternyata sedang mendengarkan lagu yang sama? Lagu yang bahkan tidak sepopuler lagu-lagu pop yang didengarkan jutaan orang di dunia. Sebutkan apa pun yang lebih aneh dari ini.
“I’m sorry,” kata laki-laki itu cepat. Dia membungkuk mengambil ponselnya dan juga ponsel Naz. Pada saat itu Naz menyadari Converse kuning yang dia pakai. Butuh dua detik tambahan baginya untuk memproses apa yang baru saja laki-laki itu katakan. I'm sorry? Dalam bahasa Inggris? Oh, tentu saja. Naz tidak terlihat seperti orang Korea.
“Tidak apa-apa,” balas Naz dalam bahasa Korea sambil berusaha keras menahan senyum.
Butuh dua detik tambahan pula bagi laki-laki itu untuk menyadari Naz bisa menggunakan bahasa yang sama dengannya.
“Maaf, saya salah karena tidak memperhatikan jalan,” dia berkata lagi, kali ini dalam bahasa Korea. Dia menyodorkan ponsel Naz.
“Tidak apa-apa. Saya juga tidak memperhatikan jalan. Terima kasih,” kata Naz sambil menerima ponselnya.
Seharusnya setelah itu mereka beranjak dari momen ini dan kembali berjalan seakan-akan tidak ada yang terjadi. Tetapi entah mengapa mereka masih berdiri berhadapan. Laki-laki itu terlihat seperti masih ingin berbicara, makanya Naz menunggunya. Ini kali pertama Naz memandangnya dalam jarak dekat dan dalam kondisi tidak bergerak, dibantu penerangan dari lampu-lampu di sekitar mereka. Laki-laki itu ternyata tampak lebih muda dari yang Naz kira. Patah sudah dugaan Naz tentang umurnya yang mungkin beberapa tahun lebih tua. Kini Naz berpikir mereka mungkin sebaya. Dan dia jauh lebih tampan dari yang selama ini Naz lihat.
Oh, dan suaranya… Laki-laki itu punya suara yang rendah dan dalam.
“When I Fall in Love-nya Nat King Cole....,” laki-laki itu akhirnya berbicara lagi. “Kamu suka lagu itu?”
Mau tak mau Naz tersenyum. “Suka,” jawabnya. “Kamu juga, sepertinya.”
Laki-laki itu tersenyum, membuat mata Naz melebar sedikit menatapnya. Senyumnya agak malu-malu, menampakkan sepasang lesung pipi yang tidak pernah Naz sadari ada di sana sebelumnya. Itu senyum yang manis sekali.
Lalu ponsel laki-laki itu berbunyi. Berakhir sudah momen ini. Mereka mengucapkan selamat tinggal penuh basa-basi, yang sebenarnya tidak perlu-perlu amat seandainya laki-laki itu tidak membuka topik tentang lagu yang mereka dengarkan. Naz pulang ke apartemen. Laki-laki itu naik bus. Setiap kali When I Fall in Love terputar di music player ponsel mereka, hanya momen lucu waktu itulah yang terkenang dalam pikiran mereka.
Ada kalanya Seoul terasa seperti menyimpan kekuatan ajaib. Lampu-lampu yang menyala sampai pagi yang Naz lihat setiap malam sambil mendengarkan lagu-lagu slow lewat earphones membuatnya memikirkan banyak cerita romantis. Tak heran kota ini menghasilkan banyak romance drama yang ditonton orang sedunia. Namun, Naz pikir, itu hanya perasaannya saja. Kadang, ia hanya terlalu senang berkhayal.
Tetapi, interaksi yang terjadi setelah kejadian ponsel jatuh itu bahkan melebihi khayalan tertinggi Naz. Di hari berikutnya, ia dan laki-laki itu berpapasan lagi di jalan. Kali ini mereka menyadari keberadaan masing-masing dan bertukar senyum. Sampai beberapa malam selanjutnya, hanya itu yang bisa mereka lakukan, seakan-akan keduanya terlalu sibuk untuk interaksi lainnya. Atau, terlalu takut untuk mengubah interaksi ini. Hingga akhirnya, tiba hari di mana mereka bertemu di tempat yang berbeda untuk pertama kalinya. Masih sama-sama di jalan, tetapi di jalan yang berbeda. Keduanya saling sapa seperti sudah kenal lama. Padahal, pada saat itu, mereka baru dapat waktu yang tepat untuk berkenalan.
Jung Jaehyun, namanya.
Kali ini, untuk pertama kalinya pula, mereka berjalan ke arah yang sama. Converse kuning itu melangkah di samping Naz. Mereka mengobrol sampai Naz tidak bisa lagi memperhatikan lampu-lampu yang menerangi tengah malamnya Seoul sambil mendengarkan lagu. Ini lebih dari yang pernah Naz khayalkan. Ia tak hanya tahu bagaimana suara laki-laki itu dan ke mana dia pergi setiap malam setelah mereka berpapasan. Ia juga tahu namanya, musik favoritnya, tempat favoritnya di Seoul, riwayatnya pernah tinggal di Amerika, dan hal-hal kecil lainnya yang tidak pernah terbayang dalam pikiran Naz sebelumnya. Dan ia menikmati itu semua, setiap pertemuan pendek mereka di jalan, sampai akhirnya pertemuan itu menjadi janji-janji bertemu di kafe, dan lampu-lampu yang menerangi tengah malamnya Seoul menyaksikan Naz memulai kisah romantisnya sendiri.
3 notes
·
View notes
Text
I’m a pantser– or as I prefer to call it, a discovery writer.
I convinced myself that plotting would be GREAT for me, and that I’d get so much more done with detailed outlines and a pre-written synopsis that adhere to conventional novel structure.
I was wrong.
I was a plotter for about a year, and wrote up all these really cool outlines for ideas I was super excited about and subsequently got no writing done because I just couldn’t write to an outline.
Moral of the story?
Listen to your gut. Try out new writing advice that you come across if you’re curious, but don’t force yourself to keep going with something that isn’t working because a it’s worked so well for someone else.
There is no one correct way to right, but there might just be one way to write that suits you more than the rest.
525 notes
·
View notes
Photo

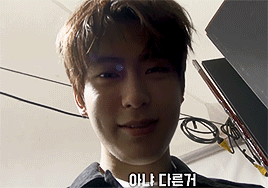

Pasar Setiap Pagi
kiki, jaehyun
1347 words
gif by renjunhuang
Akhir-akhir ini aku senang pergi ke pasar. Aku rela bangun pagi-pagi untuk itu. Sebenarnya agak sayang juga. Beberapa jam waktuku yang bisa kugunakan untuk tidur sampai siang atau spa mandiri di kamar mandi jadi terbuang sia-sia. Iya, sia-sia. Sebab apa yang kulakukan di pasar itu adalah perbuatan tersia-sia sedunia. Jauh lebih sia-sia daripada internetan seharian melihat foto cowok-cowok ganteng di linimasa Twitter. Paling sia-sia dari yang bisa dilakukan seorang Kiki.
Aku sudah cukup kesal menyadari waktuku yang berharga itu kusia-siakan untuk hal seperti ini. Tapi aku lebih kesal lagi ketika badanku tetap saja bergerak bangun pukul setengah enam pagi, mandi sebentar, berdandan kasual yang cantik, lalu berjalan ringan ke pasar dengan lagak ingin berbelanja sayur-sayuran (aku bahkan membawa tas khusus untuk itu, demi Tuhan!). Padahal, masak di rumah saja jarang. Tanteku sampai heran melihatku memberinya beragam sayur-mayur setiap pagi. “Buat apa sayur-sayur ini? Di kulkas kan udah banyak,” keluh tanteku. Keponakanku memelihara kelinci di belakang rumah. Om juga punya kambing. Tanteku seharusnya bersyukur aku tidak membuang sayur-mayur itu ke kandang mereka. Tapi aku hanya mengangkat bahu. “Yang jual ganteng, Tan. Aku jadi kasihan sama dia,” kataku santai sambil melenggang ke ruang depan.
Tanteku semakin bingung. “Apa hubungannya ganteng sama kasihan?”
“Kasihan cowok seganteng itu jualan sayur di pasar. Harusnya kan jadi artis.”
Tanteku melongo. Aku pun duduk di depan televisi dan menonton Doraemon bersama keponakanku.
Aku tidak berbohong. Aku benar-benar kasihan pada penjual sayur itu sampai rasanya ingin melarisi dagangannya setiap pagi. Siapa tahu aku sebenarnya sedang berkontribusi membantunya mengumpulkan biaya untuk pergi ke ibu kota dan ikut audisi agensi kan? Mungkin setahun lagi, foto-fotonya akan berkeliaran di linimasa Twitter-ku sebagai anggota boyband. Di saat itu terjadi, aku pasti bangga sekali.
Walau begitu, bukan berarti perbuatan yang sia-sia ini menjadi berguna. Bagaimanapun juga, bangun pagi-pagi setiap hari itu melelahkan. Apalagi mesti jalan kaki ke pasar juga. Aku memilih jalan kaki karena memikirkan diriku membuang-buang duit untuk ongkos kendaraan umum atau beli bensin hanya semakin membuatku kesal. Memangnya siapa si tukang sayur itu, membuatku berkorban sampai sebanyak itu???
Aku tidak tahu siapa dia. Yang kutahu, dia hanya penjual sayur. Yang ganteng.
Hari ini, aku bertekad akan mengakhiri perbuatan sia-sia ini sebelum menjadi kebiasaan. Ngeri rasanya mengakhiri hari setiap malam dengan pikiran “Aku harus tidur sekarang supaya besok bisa bangun pagi untuk ketemu abang sayur kesayanganku” lalu melewatkan update-update penting tentang artis kesukaanku di Twitter yang banyak muncul di malam hari. Hah! Talk about priority. Maka dari itu, kuputuskan untuk mencari tahu lebih banyak hal tentang penjual sayur itu supaya aku tidak penasaran lagi. Kupikir, mungkin, selama ini, yang membuatku ketagihan melarisi dagangannya itu tidak hanya karena menurutku dia deserves better, tapi juga karena aku senang menikmati momen-momen berinteraksi dengannya tanpa tahu namanya, anak siapa dia, dan dari mana dia berasal. Momen-momen yang misterius dan menggelikan, juga sia-sia dan tidak berguna, tapi terasa magis.
Pagi ini dia mengenakan gaya busananya yang biasa. Kaus longgar lusuh kegedean yang saking gedenya sampai kerahnya melorot ke bahu kiri dan memperlihatkan kulitnya yang seputih susu. Warnanya abu-abu, dan sudah bolong-bolong sedikit di sekitar kerah. Celananya juga longgar, warna putih kusam selutut dan bagian sampingnya ternodai entah apa yang warnanya kehitaman. Dengan penampilan yang menyedihkan seperti itu, bagaimana mungkin hatiku yang rapuh ini tidak tersentuh? Dia biasanya berdiri di belakang meja yang memajang sayur-sayuran jualannya. Kalau sedang tidak ada pembeli, dia duduk sambil mengobrol dengan ibu-ibu yang berjualan di sebelah kanan dan kirinya. Kedua ibu-ibu itu pasti senang mengobrol dengannya karena dia adalah pedagang terganteng di pasar ini. Aku senang melihatnya senyam-senyum ramah dan menanggapi mereka dengan sopan.
“Pagi, Mas,” sapaku kalem ketika aku sudah sampai di depan meja dagangannya. Dia langsung berdiri dan tersenyum lebar.
“Pagi juga, Mbak. Hari ini mau beli sayur apa?” tanyanya riang.
“Mmm. Bayam.”
“Bukannya itu udah kemarin?”
“Oh, iya. Kangkung aja, kangkung.”
“Itu udah dua hari yang lalu kan?”
“Sama wortel, Mas.”
“Wortel udah tiga hari yang lalu kan?”
Aku berdecak dan menatapnya datar. “Yang mau beli siapa?”
“Kamu.”
“Ya udah! Kangkung sama wortel. Pilihin yang paling seger.”
Dia akhirnya menurut dan mulai memilah-milah (sambil senyam-senyum tidak jelas). Aku tidak akan memberi tahunya kalau kangkung dan wortel itu kubeli untuk pakan kelinci keponakanku.
Lalu tibalah saatnya untuk kepo.
“Mas dari mana, sih?” tanyaku sekasual mungkin.
“Bukan dari sini, Mbak. Saya di sini karena lagi liburan. Nginep di rumah Pakde-Bude.”
Lho, kok sama sepertiku.
“Kok jualan di sini?”
“Ngisi kegiatan, Mbak. Sebenarnya saya jualan di sini sama Mas Sepupu. Tapi dia biasa datangnya nanti, agak siang.”
Aku mengangguk-angguk dengan mulut membentuk huruf o. Aku juga bukan orang sini dan baru datang beberapa minggu lalu untuk liburan. Kukira pasar ini memang sudah lama punya penjual sayur yang ganteng. Ternyata dia sendiri bukan orang sini. Itu lumayan menjelaskan kegantengannya yang terasa agak out of place berada di kota kecil ini.
Dia sudah membungkus kangkung dan wortelku. Aku bertanya lagi, “Trus, Mas aslinya asal mana?”
“Saya aslinya dari ibu kota, Mbak.”
Hah?
“Kok--” Secara tidak sadar aku langsung memandanginya dari atas ke bawah, judging hard penampilannya yang seperti gembel itu. Dia menyadari itu dan tertawa. Tawa lepas yang membuat matanya sampai menyipit, lesung pipinya muncul, pipinya terangkat, dan aku tidak berkedip menatapnya.
“Nggak keliatan kayak orang ibu kota, ya, Mbak?” candanya.
Kurang ajar. Jangan-jangan selama ini dia adalah artis. Atau anak orang kaya. Atau keluarga presiden. Atau keturunan ningrat. Dan dia berdagang di pasar ini sebagai kegiatan berderma! Itu lho, seperti pangeran-pangeran yang menyamar jadi orang biasa untuk membaur dengan rakyatnya. Aku merasa tertipu dan tambah kesal. Jadi selama ini aku membuang-buang waktu dan tenaga yang berharga setiap pagi bukan untuk berkontribusi membantu seseorang mengubah nasib? My whole life has been a lie.
Malah akulah yang telah menyia-nyiakan nasib untuknya. Talk about top 10 anime betrayals.
Aku tidak ingin mengobrol lagi setelah itu. Aku membayar dengan uang pas karena sudah tidak mau lagi berlama-lama berada di sana. Aku kecewa padanya dan juga pada diriku sendiri, dan hanya ingin segera pulang.
Tapi sebelum aku pergi, penjual sayur jadi-jadian itu tiba-tiba menyahut, “Ke sini lagi, ya, besok!”
Aku mempercepat langkah.
“Mbak belum nanya nama saya siapa, lho!”
Kayak aku pengin tahu aja!
Selama tiga hari setelah itu, aku demam. Rasanya seperti habis ketampakan jin. Nggak, sih. Sore hari setelah ketemu si penjual sayur jadi-jadian itu, aku kehujanan dalam perjalanan mengambilkan wadah minum keponakanku yang ketinggalan di sekolah. Akhirnya jadi demam dan tidak bisa ke mana-mana selama tiga hari. Bukan salahku kalau penjual sayur itu merasa terkhianati karena aku tidak datang lagi. Lagi pula siapa suruh menyamar menjadi gembel dan mempermainkan kepercayaanku.
Tetapi, nyatanya, mungkin karena sudah takdir atau gimana, setelah sakitku sembuh dan malah menular ke tanteku, aku harus pergi ke pasar lagi. Tanteku yang sakit itu menyuruhku berbelanja. Sebagai orang yang numpang tinggal di rumahnya, aku tidak sampai hati untuk menolak. Aku meringis melihat daftar belanja yang memuat beberapa nama sayur-mayur. Mungkin aku akan membelinya di tempat yang berbeda saja nanti. Kan, yang jual sayur di pasar bukan hanya si anu doang.
Tetapi, selama tiga hari sakit, aku banyak berpikir di kamar. Mungkin memang benar si anu itu artis atau anak orang kaya atau pangeran yang sedang berderma. So what? Malah bagus dia senang berbaur dengan rakyat kecil. Dia toh tampak tulus melakukan itu. Dan bukankah ini malah bisa jadi kesempatanku untuk mengubah nasib?
Maksudku, kalau bisa jadi istrinya….
Pagi ini aku melangkah ke pasar dengan lebih gugup sekaligus berbunga-bunga dari seharusnya. Gugup mau bertemu si anu lagi, berbunga-bunga memikirkan kehidupan berlimpah harta. Dia juga tampak senang melihatku. Aku memberi tahunya kalau selama tiga hari sebelumnya, aku sakit. Dia langsung bertanya bagaimana perasaanku sekarang. Tentu saja aku menjawab baik-baik saja. Aku juga entah kenapa memberi tahunya kalau aku di sini juga untuk liburan sepertinya, asalku dari kota lain, aku tinggal bersama keluarga tante, hobi baruku adalah membeli sayur-mayur yang berbeda setiap hari, dan keponakanku memelihara dua kelinci berbulu cokelat dan putih di belakang rumah. Dia menanggapi semuanya dengan penuh minat, bahkan tertawa lepas seperti yang kulihat waktu itu. Lalu dia berkata kalau namanya adalah Jaehyun dan bertanya siapa namaku.
Namaku? Namaku Kiki.
Dan di pasar itu, aku jatuh cinta pada penjual sayur jadi-jadian.
2 notes
·
View notes
Photo



The Boy on the Roof
nct dream 00 liners au
words: 1,006
[part 1]
Jadi, anak itu sudah bercerita pada teman-temannya tentang peristiwa beberapa hari lalu. Itu yang Renjun pikirkan ketika ia melihat Jeno dan dua anak laki-laki lainnya bermain balap mobil RC di jalan depan rumahnya. Malam-malam, di waktu Renjun biasa duduk di atap rumah untuk menulis. Renjun tahu Jeno. Kakeknya yang memberi tahunya. “Ada anak laki-laki yang tinggal di sebelah rumah, seusia kamu juga. Kakek ingin kamu berhati-hati padanya.” Begitu kata Kakek yang tadi sore berangkat naik kereta ke luar kota untuk mengikuti tur tentang studi mainan tradisional mendampingi mahasiswa-mahasiswa antropologi. Renjun tidak pernah benar-benar memperhatikan Jeno. Tidak begitu tertarik. Masih lebih menarik suara-suara dan cahaya-cahaya yang selalu ia dengar dan saksikan malam-malam di atap rumah. Namun, peristiwa beberapa hari lalu mengubah itu. Jeno tiba-tiba memanggilnya dari jendela. Renjun menoleh, mereka bertatapan sebentar, lalu Jeno bersembunyi dan tidak keluar lagi. Aneh, pikir Renjun. Ia bukannya tidak tahu Jeno sering mengintipnya. Kenapa dia tiba-tiba mencoba mengajak Renjun bicara?
Renjun juga bukannya belum pernah memperhatikan Jeno. Agak sulit mengabaikan anak laki-laki seusiamu yang tinggal tepat di sebelah rumah dan sering kamu lihat lewat di depan rumah dari balik jendela ruang keluarga. Jeno, anak laki-laki yang dalam jurnalnya Renjun deskripsikan sebagai “anak tetangga Kakek yang kalau tersenyum matanya ikut tersenyum, dan entah mengapa jadi mirip kucing putih yang pernah lompat-lompat mengejar kupu-kupu di halaman belakang rumah yang rumputnya belum dipotong.” Sejujurnya, Renjun agak tak menyangka Jeno akan menceritakan soal dirinya pada teman-temannya. Tidak, Renjun malah sudah yakin Jeno pasti sudah melakukan itu dari lama, tetapi baru kali ini saja anak itu membawa teman-temannya dan menyaksikan sendiri bagaimana Renjun senang duduk di atap rumah. Renjun kira, saling memperhatikan diam-diam itu hanya rahasia mereka berdua. Meskipun selalu menunjukkan kalau dirinya tidak peduli, sebenarnya Renjun menikmatinya. Renjun jadi merasa tidak begitu kesepian.
Kini Jeno telah membagi rahasia itu pada orang lain. Dia dan kedua temannya sudah dua malam ini datang untuk bermain mobil RC di jalan depan rumah. Mereka membicarakan hal-hal yang tidak Renjun mengerti (sesuatu tentang tugas sekolah bernama kliping yang tak kunjung selesai, tren-tren mainan RC, film, dan orang-orang yang tidak Renjun kenal tapi Renjun yakini sebagai teman-teman sekolah mereka). Gara-gara itu, Renjun jadi tidak bisa mendengar suara dan melihat cahaya dengan tenang. Gara-gara itu pula, Renjun jadi sering terdistraksi dari rutinitasnya menulis di jurnal. Selain itu, Renjun juga diganggu perasaan diperhatikan. Jeno dan teman-temannya tahu Renjun ada di atap rumah. Mereka berusaha keras terlihat asyik bermain, tapi Renjun tahu mereka senang mencuri-curi pandang ke arahnya. Walau begitu, Renjun juga sering mencuri-curi pandang ke arah mereka. Ia kini tidak lagi saling memperhatikan diam-diam dengan Jeno seorang, tetapi juga dengan dua anak laki-laki lainnya. Dua anak laki-laki itu, yang berambut oranye seperti bulan purnama selalu mengganggu yang lain, dan yang satunya lagi sangat kalem dan punya senyum yang menawan. Jeno seperti berada di tengah-tengah mereka sebagai orang yang selalu tersenyum dan bereaksi pada guyonan-guyonan si rambut bulan purnama, tidak terlalu berisik tapi juga tidak terlalu pendiam.
Di malam ketiga, mereka tidak lagi saling memperhatikan diam-diam, sebab teman Jeno yang berisik dan berambut bulan purnama tiba-tiba mendongak ke arah Renjun dan bertanya, “Kamu nggak mau turun dan bermain dengan kami?”
Suaranya lantang. Lebih keras dari sayup-sayup dengung mesin kendaraan bermotor yang lewat di rimba jalan di sekeliling rumah Renjun. Jauh lebih keras dari deru air sungai yang tidak pernah Renjun saksikan sendiri letaknya ada di mana sebab ia belum pernah pergi melihatnya. Sama sekali tidak seperti suara Kakek yang selalu berbicara dengan volume yang cukup terdengar bagi pendengarnya saja. Suara anak ini bisa terdengar sampai ke kota sebelah, sepertinya.
Ini kedua kalinya orang selain Kakek berbicara pada Renjun. Yang pertama kali sudah dilakukan Jeno waktu itu.
Renjun menggeleng. “Tidak.”
“Kenapa?” tanya Jeno, kali ini terlihat lebih berani dari sebelumnya. Justru Renjun yang ingin bertanya “kenapa” padanya. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia membawa teman-temannya ke sini?
Belum Renjun menjawab, teman-teman Jeno menimpali:
“Kamu lebih suka bermain dengan anak-anak perempuan?” tanya teman Jeno yang kalem dan bersenyum menawan. Bahkan ketika sedang tidak tersenyum, dia tampan sekali.
“Apa kami terlalu jelek untukmu?” tanya teman Jeno yang berisik dan berambut bulan purnama. Dia merangkul si kalem di sebelahnya. “Lagi pula apa serunya duduk di atas sana sendirian? Mending di bawah sini rame-rame sama kami.”
Selama ini aku baik-baik saja di sini sendirian. Kenapa kalian tiba-tiba mengusikku? Renjun membalas dalam pikirannya. Ia menatap Jeno, tiba-tiba merasa kesal padanya. Gara-gara dialah ini terjadi.
“Namaku Haechan,” teman Jeno yang berisik dan berambut bulan purnama tiba-tiba memperkenalkan diri. Anak laki-laki ber-hoodie putih dengan senyum tampan dalam rangkulannya ikut berkata, “Dan aku Jaemin.”
Mereka berdua menatap Jeno. Jeno balik menatap mereka bingung. Haechan harus melotot padanya dulu sebelum Jeno sadar apa yang harus dilakukan. “Ah,” ucapnya dengan senyum gugup. Sambil menunduk dan menendang-nendang aspal tanpa tujuan, dia berkata, “aku Jeno.”
Haechan melihat ke arah Renjun. “Bagaimana denganmu? Apa kau punya nama?”
Tentu saja aku punya nama, pikir Renjun. Tapi ia tidak tahu apakah memberikan namanya pada orang asing adalah sesuatu yang bakalan disetujui Kakek. Kakek bilang ia harus berhati-hati pada Jeno. Kalau dengan Jeno yang tetangganya saja ia harus berhati-hati, apalagi dengan Haechan dan Jaemin yang tidak ia kenal sama sekali kan? Renjun menimbang-nimbang. Ia memang harus berhati-hati. Ada alasan mengapa ia tak diperbolehkan meninggalkan rumah dan hanya bisa menikmati dunia dari atap saja. Kakek pernah bilang, dunia di luar sana, kalau kau terlalu jauh bersenang-senang, bisa membunuhmu di momen yang paling tidak pernah kauduga. Renjun tidak mau dibunuh. Ia ingin bertahan hidup walau dunia yang bisa ia jangkau hanya sebesar rumahnya yang kecil.
Tapi, tidak perlu pergi jauh dari rumah kan untuk bertemu Jeno, Haechan, dan Jaemin? Buktinya, Renjun berinteraksi dengan mereka tanpa perlu sejengkal pun meninggalkan spot favoritnya di atap rumah.
“Renjun,” kata Renjun setelah beberapa saat. “Namaku Renjun.”
Tiga anak laki-laki di bawah sana terlihat cukup puas. Haechan mengatakan sesuatu pada Jaemin dengan suara yang terlalu pelan untuk terdengar sampai ke atas, dan Jaemin mengangguk-angguk menyetujuinya seperti pajangan dasbor mobil buatan Kakek. Renjun menatap Jeno yang senyumnya tampak kurang sempurna. Anak laki-laki itu selalu berusaha menghindari kontak mata dengannya.
to be continued
5 notes
·
View notes
Photo



The Girl Who Doesn’t Reply
Taeyong, Ten, Gaby (oc), NCT 127
words: 5.4k
a/n: at last! i’m back! ini terinspirasi dari mango taeyong melon ten yang gemes banget, rasanya harus banget nulis mereka berdua. kemudian gaby nyaut di tweetku dan aku mendapatkan ide untuk cerita ini. aku sangat menikmati nulis sosok gaby. semoga gaby suka~ i’m sorry if this is too long and boring ;_; (also the ending feels kinda rushed cuz honestly idk anymore)
Jaket putih Taeyong yang agak kebesaran membuatnya terlihat seperti gundukan salju ketika duduk bersila di salah satu sudut lantai satu gedung Michelangelo, terlebih tudungnya diangkat menutupi kepala. Dinding di belakangnya dan sofa yang didudukinya pun berwarna putih. Paha kanannya sudah setengah jam ini dijadikan landasan menulis. Kertas yang ditulisinya sudah setengah terisi. Taeyong masih mau memikirkan beberapa kalimat lagi untuk mengakhiri surat ini dengan perasaan yang menyenangkan. Meskipun pada akhirnya penolakanlah yang akan ia dapat, Taeyong ingin merasa senang telah berani menyampaikan ajakannya.
Jangan sampai teman-temannya tahu. Mereka akan mengejeknya kalau tahu Taeyong masih menggunakan cara klasik seperti ini alih-alih bicara langsung atau mengirim pesan lewat internet. Habis, mau bagaimana lagi. Gadis yang Taeyong ajak bukan termasuk gadis-gadis yang pernah benar-benar berinteraksi dengannya, dan ada kalanya Taeyong enggan memikirkan langkah-langkah praktis mendekati seorang gadis yang tidak begitu ia kenal. Sudah lima tahun ia lulus dari sekolah khusus laki-laki dan gadis-gadis masihlah menjadi makhluk misterius dan tak tertebak baginya. Taeyong tidak begitu suka menghadapi sesuatu yang misterius dan tak tertebak seperti itu, apalagi kalau yang akan ia lakukan nanti hanya bertindak ceroboh dan canggung karena gugup.
Taeyong menatap sekeliling untuk memikirkan kata-kata selanjutnya, lalu menunduk untuk menulis ide yang ia dapat. Dari depan, wajahnya jadi tak terlihat karena tertutupi tudung jaket. Dua orang gadis yang sama-sama mendekap buku berjalan melewatinya.
“Sudah coba ajak Lee Taeyong? Pasti seru banget datang ke festival seni berpasangan dengan Visual King-nya Spring Hills,” kata salah satu gadis itu.
Gadis satunya menanggapi, “Aku nggak yakin, deh. Reputasinya selain sebagai Visual King kan banyak. Temanku yang sejurusan dengannya pernah bilang, dia kaku banget kalau sama cewek.”
“Itu, sih, bisa diurus. Yang penting kan datang sama cowok ganteng dulu.”
“Sialan. Kalau Seungcheol gimana? Aku dengar dia....”
Taeyong memandang gadis-gadis itu berjalan menjauh tanpa benar-benar mengangkat wajahnya. Setelah mereka keluar dari gedung lewat pintu kaca, Taeyong menghela napas dan menyandarkan bagian belakang kepalanya di dinding, wajahnya menengadah, menatap langit-langit yang putih bersih. Untuk kali kesekian ia sadar kalau selama ini tidak semua orang memandangnya sebagai Lee Taeyong yang Lee Taeyong. Orang-orang seperti dua gadis tadi hanya mengenalnya sebagai Lee Taeyong yang dijuluki Visual King-nya Spring Hills University of Arts. Mereka mempertimbangkannya sebagai pasangan ke festival seni bukan sebagai Lee Taeyong yang senang menyamar menjadi gundukan salju dan menulis surat untuk mengajak seseorang pergi berkencan, melainkan si Visual King yang tampan, punya tatapan tajam yang memikat, jagoan fakultas Dance, dan kerap kali dijadikan trofi pemenang oleh para gadis. Popularitas itu justru bisa memudahkannya mendapatkan teman kencan, tapi bukan teman kencan yang akan memandangnya sebagai “Lee Taeyong yang Lee Taeyong”.
Karena itulah, Taeyong menulis surat untuk Gaby.
Dear Gaby,
Halo. Aku tidak yakin kamu mengingatku. Kita hanya pernah bertemu satu kali. Tanggal 13, hari Selasa, di Velvety Candy Shop dekat kampus. Aku datang untuk menghirup aroma manis vanilla dan karamel. Ingat? Dengan canggung aku mencoba mengajakmu bicara, lalu dengan tak kalah canggung kamu bertanya apa yang kulakukan di candy shop itu. Kujawab, “Aku... datang ke sini untuk... menghirup aroma manis vanilla dan karamel.” Itu terdengar bodoh sekali. Aroma manis vanilla dan karamel yang kuat memang memenuhi napasku saat itu, tapi seharusnya aku bilang aku datang untuk membeli cokelat. Aku merasa telah berbohong, dan perasaan bersalah menguntitku ke mana pun aku pergi. Surat ini harus kutulis untuk meluruskan hal ini.
Baiklah, maaf, aku berbohong lagi. Aku tidak menulis surat ini untuk meluruskan apa pun. Aku hanya merasa... ingin mengatakan sesuatu padamu... dan mendengar lebih banyak ceritamu selama menjadi mahasiswa pertukaran pelajar di universitas ini, kalau bisa. Aku sempat menguping pembicaraanmu dengan temanmu di Velvety. Karena ketahuan mengupinglah aku jadi terpaksa mengajakmu bicara dan mengatakan hal bodoh. Maafkan aku. Kalau tidak salah, kamu dari Malaysia, ya? Cerita-ceritamu tentang manisan itu terdengar menarik. Karena berasal dari negara lain, kamu memandang segala sesuatu di sini dengan sudut pandang yang berbeda, dan kamu membawa sudut pandang lain tentang manisan yang belum pernah kudengar sebelumnya. Kamu bercerita kalau manisan-manisan dari negaramu terbuat dari bahan-bahan alami yang nama-namanya belum pernah kudengar sebelumnya. Kulepon ubi? Golang-galing? Aku tidak tahu bagaimana tulisan yang benar, tapi aku masih ingat beberapa nama yang kausebutkan waktu itu. Aku suka memasak, aku juga suka sekali manisan. Mungkin karena itulah kita bertemu di candy shop. Mungkin karena itu jugalah aku ingin sekali mendengar lebih banyak ceritamu. Aku punya banyak teman yang juga mahasiswa asing, tapi mereka tidak pernah setertarik itu pada manisan. Aku berasumsi kalian telah bertemu di pertemuan rutin ISS Spring Hills. Familier dengan nama-nama ini? Johnny, Ten, Yuta. Kudengar kamu mengikuti mata kuliah-mata kuliah teori seni. Mungkin kamu pernah sekelas dengan Johnny.
Ah, sudah sepanjang ini, tapi aku belum memperkenalkan diri. Namaku Lee Taeyong [Taeyong menulisnya dengan hangeul], atau Taeyong Lee [Taeyong menulisnya dengan alfabet Latin] dalam bahasa Inggris. Kita beda fakultas. Aku dari fakultas Dance, jurusan Choreography. Dari pembicaraanmu dengan temanmu di candy shop, aku menebak kamu dari fakultas Korean Traditional Arts, tapi aku tidak tahu konsentrasi jurusanmu. Kudengar mahasiswa asing dari program pertukaran pelajar lebih banyak terdaftar dalam fakultas itu daripada fakultas lain di kampus ini. Kamu beruntung sekali, bergabung dengan kami di musim gugur ketika pepohonan Spring Hills akan meledakkan warna-warni emas, cokelat, dan merah. Dua minggu setelah daun-daun mulai berubah warna, festival seni tahunan kami diadakan. Akan ada penampilan-penampilan hebat dari setiap jurusan, juga hiburan-hiburan dari klub dan bintang tamu. Kabarnya, tahun ini kami mengundang Crush dan Akmu. Kamu harus datang.
Dan aku sedang bertanya-tanya... apa aku bisa datang bersamamu?
Terungkap sudah tujuan utamaku menulis surat ini. Maaf, aku tidak bisa melakukannya seperti kebanyakan orang. Aku harus menulis surat, karena... kurasa... aku tidak hanya ingin mengajakmu? Aku juga ingin... menyampaikan sesuatu... supaya aku tidak terlihat seperti orang aneh. Tapi kurasa menulis surat justru membuatku terlihat seperti orang aneh? Maafkan aku. Ini sangat canggung. Tapi sejujurnya, cara ini lebih mudah bagiku.
Kurasa kamu tidak perlu membalasnya. Aku akan sangat berterima kasih kalau kamu bersedia. Kamu bisa menitipkannya pada Kim Doyoung, barista Decressendo Coffee Shop (dia teman baikku, dan kau pasti tahu kafe ini kan? Tidak ada mahasiswa Spring Hills yang tidak tahu Decressendo). Kuharap aku mendapat jawaban yang baik.
Lee Taeyong
P.S.
Rambutmu indah sekali. Awalnya kukira warnanya hitam legam, tapi cahaya lampu Velvety mengungkapkan nuansa cokelat yang berkilauan. Itu juga yang membuatku memperhatikanmu di candy shop. Aku juga jadi menguping pembicaraanmu karena memperhatikan rambutmu. Maaf, aku aneh sekali. Kau mungkin tidak akan mau pergi ke festival seni dengan orang aneh sepertiku.
Taeyong tidak yakin tentang ide berkencan dengan Gaby. Maksudnya, berkencan yang seperti... sepasang kekasih. Ia belum memikirkannya sejauh itu. Yang ia tahu, kalau ia harus menghabiskan waktu di festival seni bersama seseorang, ia lebih memilih melakukannya bersama seseorang yang memandangnya sebagai “orang aneh di toko permen” alih-alih sebagai si Visual King Spring Hills. Lebih baik menikmati acara itu dengan diselingi pembicaraan-pembicaraan bermakna tentang manisan dan kisah-kisah dari negeri yang jauh (tempat Gaby berasal) ketimbang hanya digandeng, dipeluk, dan dipamerkan sebagai trofi. Taeyong harap Gaby orang yang tepat untuk itu.
Setelah surat itu selesai ditulis, Taeyong mencangklong tasnya dan meninggalkan gedung Michelangelo. Masih menutupi wajahnya dengan tudung jaket, Taeyong menyusup ke gedung administrasi tempat kantor International Student Service (ISS) berada dan menitipkan surat itu pada seorang staf wanita yang menyambutnya dengan wajah mengantuk. “Permisi, seseorang menjatuhkan surat ini di depan pintu,” katanya.
Staf wanita berusia tiga puluhan yang terlihat seperti baru bangun tidur itu memperhatikan nama yang tertulis di surat, lalu mengangguk-angguk dan berkata, “Ah, ini mungkin milik salah satu mahasiswa pertukaran pelajar. Kami akan menyampaikannya padanya nanti.”
Taeyong berterima kasih dengan sopan, berusaha keras menyembunyikan senyumnya. Sekeluarnya dari kantor, senyum itu mengembang lebar secerah langit musim gugur hari ini. Ia harap Gaby benar-benar memberinya jawaban yang baik.
Langkah Ten lebar dan cepat melintasi halaman-halaman kampus. Ia baru dari gedung fakultasnya. Kelas terakhir baru saja selesai. Kemeja hijau pinusnya yang terbuka berkibar-kibar, memperlihatkan kaus hitam lengan panjang yang dirangkapinya. Tas selempangnya terguncang-guncang terkena gerakan kakinya. Pandangan Ten lurus ke depan, dan di situ ada api berkobar-kobar.
Ten sampai di Decressendo Coffee Shop di mana Johnny sudah menunggunya di lantai dua. Ia berderap menuju tangga tanpa menghiraukan Doyoung yang sedang membersihkan meja dari gelas kotor dan tampak heran melihat Ten mengabaikannya. Sesampainya di lantai dua, satu-satunya pelanggan yang terlihat hanyalah Johnny yang menempati tempat duduk di dekat pintu balkon. Laptop dan buku-buku teks analisis seputar literatur Inggris abad 18 memenuhi meja kayu berwarna cokelat gelap dan membuatnya terlihat sempit. Cangkir americano-nya sampai harus diletakkan di meja sebelah. Ten menghampirinya dan menggebrak meja itu.
Johnny sama terperanjatnya dengan cangkir kopi yang kemudian menumpahkan sedikit isinya di permukaan meja. Sedikit, karena Johnny buru-buru memperbaiki posisinya kembali seperti semula.
“Hey, what the—” Tas selempang Ten melayang di depan wajah Johnny dan mendarat dengan bunyi bruk di kursi kosong di sebelah Johnny. Untung Johnny refleks memundurkan kepala. Selanjutnya, pemuda itu menatap Ten dan menyadari kalau Ten sedang emosi.
“Brengsek!” Ten mondar-mandir di depan meja Johnny. “Nggak ada yang mau pergi denganku ke festival seni! Padahal aku menuliskan namaku di white board bersama Jun dan yang lain. Tapi nggak ada yang mau memilihku! Ada apa dengan orang-orang?! Aku kira mereka semua menyukaiku! Bukankah aku tampan? Bukankah aku juga berbakat? Aku juga lucu! Mereka semua nggak akan pernah tertawa di kelas teori Profesor Park kalau bukan karena lelucon-leluconku! Dan melucu di kelas teori Profesor Park itu nggak mudah! Bisa-bisanya mereka mendiskreditkanku seperti ini, hah?! Memperlakukanku seakan-akan aku anak tercupu dan terjelek di dunia, yang tidak pantas diajak berkencan! Membuatku marah!”
Johnny menghela napas keras-keras dan kembali menatap layar laptopnya. “Ya Tuhan. Aku kira kenapa.”
Ten menarik kursi dengan kasar dan duduk di hadapan Johnny. “Cewek yang namanya Jennie itu, dia menatapku dengan cara yang sama dengan seseorang menatap tong sampah di samping gedung Leonardo da Vinci! Memangnya apanya yang seperti tong sampah dari diriku ini?? Aku kan tampan, berbakat, dan pintar melucu!”
“Kapan terakhir kali kau bergaul dengan Yuta? Dia sudah banyak mempengaruhimu.”
“Memangnya dia pikir dia siapa, sih? Ratu Spring Hills?” Ten melanjutkan seakan-akan Johnny tidak pernah berkomentar. “Dia bukan anak jurusanku, tapi ikut dua kelas yang sama denganku, dan itu semua mata kuliah wajib! Aku nggak peduli apa jurusannya sampai harus ikut dua kelas wajib itu, yang jelas aku nggak suka melihatnya! What an eyesore! Aku harap nggak akan ada yang mau mengajaknya pergi kencan ke mana pun!”
Ten bersedekap menghadap ke balkon. Ngambek seperti balita.
Johnny memperhatikannya sebentar, lalu terkekeh-kekeh.
Ten menoleh secepat kilat. Tawa Johnny serta-merta berhenti, tapi tidak sepenuhnya hilang. Hanya berubah jadi tak bersuara karena dikulum dan ditahan. Johnny tampak berkonsentrasi pada draf esai yang sedang dikerjakannya, tapi wajah mengulum senyum itu jelas-jelas menunjukkan kalau dia hanya berpura-pura. Ten menendang kakinya di bawah meja.
Tawa yang dikulum Johnny keluar sebagai erangan. “What the hell, man! You’re injuring my calf,” bisiknya kesakitan sambil membungkuk dan mengelus-elus betisnya. “Ahh...,” keluhnya saat melihat tapak sepatu Ten membekas di jins hitamnya. “Dude, this pants just came out of the laundry this morning!”
“Makanya jangan menertawakan orang yang sedang menderita.”
“Siapa yang kakinya baru saja ditendang dan celananya jadi kotor? Akulah yang sedang menderita.”
“Siapa yang sudah mencalonkan diri untuk diajak pergi ke festival seni tapi nggak ada seorang pun yang memilih? Aku. Penderitaanku ini lebih emosional dan tidak bagus untuk kesehatan mentalku.”
“Siapa yang tadi mukul meja sampai kopiku tumpah dan mejanya jadi kotor? Kamu.”
“Iya, aku,” sahut Ten dengan nada menantang, dagunya diangkat. “Memangnya kenapa?”
“Dalam lima detik, kamu akan diomeli Doyoung.”
Ten menoleh ke arah tangga, bertepatan dengan munculnya Doyoung yang berjalan ke arah mereka masih mengenakan apron seragam karyawan kafe ini. Doyoung yang seangkatan dengan Ten dan sudah satu semester bekerja paruh waktu di Decressendo biasa memanfaatkan waktu luang yang dia punya di saat kafe sedang sepi untuk mengobrol dengan teman-temannya yang datang. Ten menyambar salah satu buku Johnny, berusaha menggunakannya untuk menutupi tumpahan kopi di meja. Tapi Johnny memegangi tangan Ten dan berusaha merebut buku itu sebelum ada lembarannya yang ternodai cairan kopi.
“Johnny hyung yang melakukannya! Johnny hyung yang melakukannya!” kata Ten berulang-ulang, yang malah membuat Doyoung sadar kalau ini adalah perbuatan Ten.
“Apa-apaan,” gumam Doyoung seketika saat melihat tumpahan kopi itu. Johnny berhasil merebut bukunya karena Ten lengah. Doyoung berkacak pinggang. “Sial. Aku ke sini untuk bergabung dengan kalian, bukan malah mendapat pekerjaan tambahan. Bagaimana kopi ini bisa tumpah?”
“Jangan berkacak pinggang begitu. Kamu jadi kayak ibu-ibu.”
“Menyusahkan saja. Seharusnya kalian bilang dari tadi supaya nodanya cepat dibersihkan. Jangan dibiarkan begini. Atau setidaknya lap dulu dengan tisu.”
“Iya, iya. Harus cepat dibersihkan kan? Kenapa nggak segera dibersihkan sekarang, mumpung kamu di sini?”
Doyoung menatap Ten sebal, lalu bertanya pada Johnny, “Anak ini kenapa? Dia tadi berjalan melewatiku seperti orang kesurupan setan.”
“Dia ditolak Jennie,” jawab Johnny ringan sambil kembali mengerjakan sesuatu di laptop.
Ten menyambar buku Johnny lagi dan hampir melemparnya ke wajah laki-laki yang seangkatan lebih tua darinya itu. “Woy! Siapa!”
“Ten?? Ditolak Jennie??”
“Aku nggak suka Jennie! Enak saja!” Ten mau menendang kaki Johnny lagi, tapi ternyata Johnny sudah mengamankan kakinya dengan menggeser duduknya ke samping saat Ten tidak memperhatikan. Johnny terkekeh-kekeh lagi, membuat Ten semakin kesal. “Kurang ajar! Jangan menyebar fitnah!”
“Wow, ini berita baru,” kata Doyoung terhibur sambil mengelap tumpahan kopi dengan kain lap yang selalu tersedia di kantong apron. “Kau menyatakan perasaan sungguhan atau hanya mengajak Jennie ke festival seni? Kenapa harus si Ratu Spring Hills itu di antara sekian banyak wanita di kampus ini?”
“Dia bukan Ratu Spring Hills!”
“Hyung, mau kuambilkan kopi lagi?”
“Ah, jangan. Ini sudah kopi ketigaku hari ini. Air putih saja, tolong ya.”
“Baiklah. Kau mau pesan nggak?” Doyoung bertanya pada Ten. “Orang-orang yang baru saja ditolak biasanya memesan minuman-minuman manis non-kopi di sini.”
“Aku nggak ditolak siapa-siapa, demi Tuhan. Johnny hyung itu bohong.”
“Aku nggak bohong. Ten memang baru saja ditolak semua cewek di kelasnya.”
Doyoung mendengus geli. “Itu malah lebih lucu lagi. Benarkah? Kau mengajak semua cewek di kelasmu untuk datang ke festival seni?”
“Dia mencalonkan diri di white board bersama Jun dan yang lain. Nggak ada seorang pun yang memilihnya.”
“Menyedihkan sekali. Padahal kukira kau sangat populer.”
“Aku kira aku sangat populer...,” ulang Ten pelan, lalu tiba-tiba pemuda berambut hitam itu terdiam dan memainkan-mainkan ujung buku Johnny dengan jari telunjuk dan ekspresi wajah yang sangat nelangsa. Kekesalannya—reaksi pertamanya setelah menyadari semua gadis di kelasnya sudah tidak mau menambahkan suara di papan tulis dan membiarkan bagian di sebelah namanya tetap bersih—sudah berkurang, dan sekarang perasaan lain mulai muncul.
Melihat Ten yang malah bersedih, Doyoung berkata, “Baiklah... Sepertinya kau memang membutuhkan sesuatu yang manis... Aku akan membuatkanmu cinnamon hot chocolate. Baru kemarin aku belajar resepnya.”
Ten tidak mengatakan apa pun. Doyoung pun berlalu dengan perasaan antusias karena akhirnya bisa mempraktikkan resep barunya (belum ada yang memesan cinnamon hot chocolate seharian ini). Johnny terlalu larut mengetik esainya selama beberapa saat sampai keheningan di lantai dua kafe itu menyadarkannya kalau seharusnya ada seseorang yang marah-marah dan terus mengoceh tentang penolakan yang dia dapat dari gadis-gadis sekelas. Ia melihat ke arah Ten yang sedang bertopang dagu dan mengetuk-ngetuk layar ponsel dengan wajah muram. Rupanya temannya itu sedang melihat-lihat konten Instagram story unggahan anak-anak kampus. Banyak yang berupa foto dan video pendek tentang orang-orang yang akan datang bersama mereka ke festival seni.
“Siapa, sih, yang membuat tradisi bodoh seperti ini,” gumam Ten dengan suara pelan.
Johnny menyesap sisa kopinya yang sebenarnya sudah terlalu dingin untuk diminum. “Kau tahu aku tidak akan menolak kalau kau mengajakku kan,” katanya.
Ten mendengus. “Aku bosan pergi denganmu terus,” tolaknya. “Jangan-jangan cewek-cewek itu nggak ada yang mau pergi denganku karena mengira aku berpacaran denganmu?”
Johnny tertawa sumbang. “Very funny,” gumamnya. “No, I mean, you don’t have to go with a date. Banyak, kok, yang datang bersama teman, atau bahkan sendirian. Aku yakin cewek-cewek itu tidak serius menolakmu. Mereka mempermainkanmu karena berpikir itu akan lucu, mengingat kamu juga sering melucu.”
“A very typical misfortune to happen to a class clown.”
“You’re not a class clown. You’re a happy virus.”
“Aww, that’s sweet,” Ten mencibir. Johnny mengangkat bahu acuh tak acuh.
Ten menggulir-gulir beranda Instagramnya dengan lesu. “Mereka nggak sadar kalau apa yang mereka lakukan itu benar-benar tidak sehat untuk kesehatan mentalku. Maksudku, it’s making me questioning my self-worth and all that. Why didn’t anyone choose me? Why did everyone reject me? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu lebih mengganggu daripada pilek dan sama menyusahkannya dengan sakit gigi. Mungkin memang aku lebih sering ngelawak daripada mengatakan sesuatu yang berfaedah, tapi bukan berarti mereka bisa meremehkan perasaanku kan? Merasa tertolak tanpa alasan yang jelas itu lebih menyakitkan daripada ditolak dengan alasan yang jelas.”
Johnny diam sebentar, lalu menghela napas. “Ya sudah. Pergi denganku saja. Aku tidak akan pernah membuatmu merasa tertolak.”
“Dude, you’re so gay.”
“Aren’t we all?”
Tepat setelah Ten berkata “Tapi aku sedang ingin pergi dengan orang lain” dengan nada merengek, terdengar suara ramai sekelompok orang yang naik ke lantai dua dalam waktu yang bersamaan. Doyoung muncul lagi membawakan cinnamon hot chocolate untuk Ten dan segelas air putih untuk Johnny. Pemuda bermata cemerlang itu mengobrol singkat dengan tiga orang gadis yang berjalan di belakangnya sebelum mempersilakan mereka duduk dan menghampiri meja Johnny dan Ten untuk mengantarkan minuman mereka.
“Bukankah kalian mengenal mereka? Mahasiswa-mahasiswa asing yang ikut pertukaran pelajar di sini semester ini,” kata Doyoung sembari meletakkan gelas panjang berisi cinnamon hot chocolate buatannya di meja. Mahasiswa-mahasiswa asing di Spring Hills cenderung saling mengenal atau setidaknya tahu satu sama lain berkat aneka acara eksklusif yang diselenggarakan ISS. ISS mengirimkan undangan elektronik ke alamat surel semua mahasiswa asing yang tersimpan di data mereka dan menyambut siapa pun yang bersedia hadir. Mereka juga membantu mempromosikan acara-acara yang diadakan atau hendak diikuti para mahasiswa asing, mulai dari undangan menonton pertunjukan sampai pesta pribadi. Johnny dan Ten biasanya ikut menghadiri pesta-pesta pribadi. Johnny malah termasuk kerap menjadi penyelenggara.
“Ah, mereka sekelas denganku,” kata Johnny, lalu melambaikan tangan pada tiga gadis itu. “Hi, guys!” sapanya lantang. Gadis-gadis itu baru saja duduk di tempat yang berseberangan dengan tempat Johnny, Ten, dan Doyoung. Mereka balas melambaikan tangan sambil terkikik-kikik. “I’m Johnny from Contemporary Korean Art class. Remember me?”
“Mereka bisa bahasa Korea kan? Kami tadi berbicara dengan bahasa Korea,” kata Doyoung pelan, terdengar terkejut.
Ten tidak menjawab karena ia sedang memperhatikan gadis-gadis itu. Bukankah mereka pernah bertemu di pesta penyambutan mahasiswa pertukaran pelajar? Sebagian besar peserta pertukaran pelajar semester ini berasal dari Asia Tenggara. Ten diundang karena meskipun berdarah Tiongkok, ia berasal dari Thailand. Gadis-gadis itu termasuk yang berasal dari Asia Tenggara. Mana saja, ya, persisnya? Singapura, Filipina, dan... Malaysia? Indonesia? Ten lupa-lupa ingat. Tapi ia ingat wajah-wajah itu. Ia ingat salah satu dari mereka bernama Gaby, nama termudah yang ia dengar dan bisa dihafalkan seketika dibanding nama-nama peserta lainnya. Di pesta penyambutan, Gaby mengenakan gaun selutut warna cokelat bercorak khas, berpadu selendang hitam polos dan sepatu bots semata kaki warna hitam. Rambut panjangnya yang digerai tampak lebih bervolume dibandingkan hari ini dan dihiasi jepitan bunga berwarna keemasan. Ten masih mengingatnya dengan baik karena ialah yang membantu gadis itu ketika ujung roknya tersangkut di pintu balkon, dan jepitan bunga itu terus berkerlap-kerlip terkena cahaya lampu. Ten juga ingat Gaby tertawa-tawa canggung sementara ia berusaha membebaskan ujung roknya. Setelah itu Gaby berterima kasih dengan senyum malu, dan Ten memuji bahasa Koreanya yang sangat bagus karena ia tidak tahu harus menjawab apa (dalam hati ia membatin “Damn, she’s cute” tapi itu tidak mungkin dikatakan keras-keras kan?). Lalu mereka berpisah dan tidak bertemu lagi... sampai hari ini.
Gadis yang bernama Gaby itu duduk di pinggir kanan, hanya tertawa dan tersenyum ekspresif di saat kedua temannya antusias menanggapi Johnny. Ten jadi memperhatikan matanya yang berkilauan dan rambut hitamnya yang tersembunyi sebagian di balik lilitan syal. Penampilannya yang kasual mengingatkan Ten pada teman-teman adik perempuannya yang sering main ke rumahnya di Thailand. Tiba-tiba, gadis itu melihat ke arah Ten, menatap Ten dengan sorot mengenali yang membuat Ten terbelalak dan mau tak mau tersenyum serta melambaikan tangan sok ceria. Gaby balas melambaikan tangan dengan senyum malu yang sama dengan waktu itu, membuat Ten memalingkan muka dengan wajah menghangat.
“Kurasa kamu lebih baik mengajak seseorang daripada menawarkan diri seperti orang yang menyedihkan ke orang-orang yang hanya memandangmu sebagai teman sekelas,” kata Doyoung yang rupanya sangat perseptif. Ten menyeruput cinnamon hot chocolate-nya, pura-pura tak mendengar. Tetapi, kulit wajahnya yang jelas merona malah membuat Doyoung berkata, “Aku akan membuatkan pesanan mereka. Mau titip pesan? Untuk cewek bersyal itu.”
“Nggak usah. Bekerjalah saja dengan benar.” Ten mendorong Doyoung. Doyoung tertawa mengejek sebelum turun ke lantai satu.
Diam-diam, Ten membenarkan apa yang dikatakan Doyoung. Mungkin yang perlu ia lakukan adalah mengajak seseorang, bukan malah meratap karena ditolak ketika menawarkan diri pada orang lain. Dan sepertinya... Ten sudah tahu siapa yang akan ia ajak. Ia kesulitan berhenti mencuri-curi pandang ke arah gadis bersyal itu. Ia sampai pindah duduk di sebelah Johnny dengan alasan “ingin mengintip esai yang membuatmu bisa semudah itu menganggap enteng festival seni dan mengacaukannya kalau bisa” dan mengganggu Johnny dengan berusaha memencet-mencet keyboard laptop supaya tidak terlihat mencurigakan. Ia baru menghentikan kenakalan itu saat Johnny memitingnya.
Ten tidak bilang apa-apa pada temannya itu tentang keinginannya mengajak Gaby.
Taeyong menunggu-nunggu balasan suratnya. Ia sudah sering datang ke Decressendo untuk nongkrong bersama teman-temannya, tetapi ia jadi dua kali lipat lebih sering datang setelah “mengirim” surat untuk Gaby. Gaby tidak banyak terlihat di area fakultas Taeyong, jadi Taeyong tidak bisa mendapatkan pertemuan-pertemuan tak terduga yang membuatnya mau tak mau bertanya langsung tentang balasan dari surat itu. Taeyong hanya bisa mengharapkan ada titipan untuknya di Decressendo.
Hari ini, Taeyong datang lagi ke Decressendo. Ini sudah kedatangannya yang ketiga dalam kurun waktu tujuh jam. Taeyong lebih kurang sabar dibanding biasanya karena festival seni itu hanya tinggal besok. Ia mulai berpikir Gaby mungkin menolaknya, atau surat itu tidak pernah tersampaikan sama sekali, tetapi di saat yang sama ia juga semakin gila berharap kalau akan ada surat balasan yang bisa ia jemput di setiap kedatangannya ke Decressendo. Dalam pertemuannya dengan teman-temannya yang juga menjadi kedatangannya yang ketiga dalam sehari ini, Doyoung mulai menunjukkan gelagat simpatik padanya. Hanya Doyoung yang Taeyong beri tahu tentang ajakan lewat surat ini walau Taeyong tetap menyimpan nama orang yang diajaknya untuk dirinya sendiri. Doyoung langsung bersedia merahasiakan hal ini tanpa perlu diminta.
Taeyong duduk di bar sementara teman-temannya menempati meja-kursi di dekat pintu masuk kafe, sedang ramai menyemangati Taeil dan Winwin yang akan tampil di festival seni sebagai duo. Ia memandang pintu kafe itu, dengan bodoh berharap Gaby akan lewat di depan kafe atau bahkan masuk melalui pintu kaca itu dan menemuinya secara langsung. Kafe selalu ramai di akhir minggu, jadi suasana di lantai satu jauh lebih berisik dari biasanya. Taeyong mensyukurinya karena itu berarti orang-orang sedang sibuk dengan pembicaraan mereka sendiri dan teman mereka masing-masing. Tidak ada yang memperhatikannya.
Kecuali mungkin Doyoung yang menemaninya sambil bekerja di belakang meja bar.
“Hyung benar-benar masih menunggu gadis itu?” tanya Doyoung sambil meracik kopi pesanan pelanggan yang duduk di lantai dua.
“Nggak. Nggak terlalu,” jawab Taeyong dengan kukis lemon dipegang depan mulut, berusaha tidak terlihat canggung. Suaranya rendah dan hampir-hampir terdengar datar karena keramaian kafe menenggelamkan suara intonasinya. “Nggak apa-apa kalau dia nggak mau. Aku nggak keberatan pergi sendirian.”
“Kita akan pergi bersama yang lain. Tapi mungkin aku agak telat karena ada yang harus kukerjakan dulu,” ujar Doyoung. “Tidak usah terlalu serius. Festival seni nggak akan berkurang serunya hanya karena kita nggak bawa teman kencan.”
“Aku tahu. Aku juga heran kenapa aku tiba-tiba pengin pergi sama cewek.” Biasanya kalau bukan sendirian, Taeyong selalu bersama dengan teman-temannya yang kesemuanya laki-laki.
“Cewek itu gila kalau menolakmu, Hyung. Aku yakin dia hanya sedang grogi memutuskan bagaimana caranya membalas suratmu.”
Taeyong tersenyum. Ia senang mendengar kalimat terakhir itu. “Terima kasih, Doyoung-ah,” ucapnya. Ia menggigit kukisnya dan mulai bermain-main dengan ide plan B untuk berjaga-jaga seandainya Gaby benar-benar tidak membalas suratnya.
“Hyung!”
Tiba-tiba kedua pundak Taeyong dicengkeram dari belakang. Taeyong terperanjat; kukisnya meluncur jatuh dari tangannya. Ten muncul di sebelahnya sambil tertawa. Anak itu duduk di kursi bar sementara Taeyong menggumamkan serangkaian omelan sambil mengambil kukisnya yang terkapar di lantai.
“Masa begitu saja marah. Aku bisa membelikanmu kukis-kukis lain yang lebih enak dan mahal, Hyung.”
“Jadi menurutmu kukis di sini tidak begitu enak dan murahan,” celetuk Doyoung, pura-pura tersinggung.
Ten tertawa lagi. “Bukan begitu, Doyoung-ah.”
“Jangan sok akrab denganku.”
“Bukankah kita memang akrab?”
“Enak saja,” bantah Doyoung penuh penekanan. Ten malah tertawa semakin lebar. Menggoda Doyoung memang selalu menyenangkan.
“Doyoung-ah, aku pesan kukis lagi. Kukis cokelat,” kata Taeyong. Kukis lemonnya yang remuk sudah ditaruh kembali di piring dan ia terlihat benar-benar devastated. Ten jadi merasa bersalah.
“Sebentar ya, Hyung. Aku antar pesanan ini dulu. Oh, pesan sama dia saja. Akhirnya kembali juga setelah seabad.”
Tak lama setelah Doyoung keluar dari belakang meja bar, karyawan lain masuk dari pintu kafe membawa sapu—seorang pemuda dari fakultas Visual Arts. Baik Taeyong maupun Ten sama-sama tidak terlalu mengenal rekan kerja Doyoung itu, jadi mereka tidak banyak mengobrol dengannya. Taeyong hanya memesan kukis cokelat, lalu tidak ada pembicaraan lainnya.
“Hyung sudah tahu mau pergi dengan siapa ke festival seni?” tanya Ten. “Aku sudah mengajak seseorang, tapi kurasa caraku salah. Seharusnya aku bicara langsung dengannya.”
“Memangnya kau pakai cara apa?”
“KaTalk. Aku dapat ID-nya dari temanku. Tapi sampai sekarang dia tidak membalas pesanku.”
Taeyong terkekeh. “Senasib, dong, kita.” Ternyata dengan pesan elektronik atau pesan klasik, keduanya sama saja selama orang yang dituju tidak membalas.
Ten menghela napas dramatis. “Guess I’ll end up with Johnny all over again.”
“Tidak mau coba tanya langsung dulu?”
“Dia tidak membalas pesanku. Mungkin dia sudah punya teman kencan lain.”
Taeyong mengerjap, lalu mengangguk-angguk. “Oh... Iya, ya... Benar juga.”
“Apa boleh buat. Yuta hyung bilang, kalau kita semua pergi dengan teman kencan masing-masing, siapa yang akan meramaikan penampilan Taeil hyung dan Winwin nanti?”
“Ah, iya. Aku tadi dengar dia bilang ‘Kesuksesan penampilan duo ini tergantung dari seberapa banyak pria lajang yang mendukungnya’. Aku ingin teriak ‘Cerewet!’ tapi percuma kalau tidak terdengar.”
Ten tersenyum. “Jadi sepertinya, di antara kita semua, hanya Jaehyun yang bawa cewek.”
“Jaehyun? Benarkah? Dia dengan siapa?”
Ten mengangkat bahu. “Mana kutahu. Aku tidak ingin dengar kisah romantis Pangeran Jung. Pasti terlalu menyakitkan untuk hati pria lajangku yang rapuh,” katanya sambil manyun. “Dia juga tidak menceritakan detailnya. Kurasa kita baru akan tahu saat hari H besok.”
“Aku penasaran siapa gadis beruntung itu.”
“Aku lebih penasaran dengan siapa cewek yang kuajak pergi sampai-sampai pesanku nggak dibalas. Tapi kurasa aku juga akan baru tahu saat hari H besok.”
Taeyong merangkul Ten dan menepuk-nepuk pundaknya simpatik. “Tidak apa-apa. We’re in this together.”
Dia tidak membalas pesanku. Mungkin dia sudah punya teman kencan lain, Taeyong mengulang-ulang perkataan Ten. Lama-lama, perkataan itu menyatu dengan pikirannya sendiri.
Pada akhirnya, Taeyong benar-benar pergi ke festival seni bersama teman-temannya. Ia sudah memutuskan untuk merelakan surat itu. Taeyong kecewa, tetapi juga senang karena sudah berusaha. Mungkin ia akan bertemu dengan Gaby malam ini, dan ternyata Gaby tidak pergi dengan siapa-siapa sehingga ada kesempatan dan ending yang lebih bagus untuknya. Mungkin juga Gaby datang bersama teman kencan sendiri—kemungkinan besar sesama mahasiswa pertukaran pelajar. Atau mungkin malah Gaby tidak datang sama sekali. Taeyong dan squad-nya (Doyoung, Ten, Johnny, Yuta, Jaehyun, dan Hansol) ramai-ramai bersorak, melambai-lambaikan ponsel yang flash-nya dinyalakan, dan bertepuk tangan untuk menyemangati Taeil dan Winwin (anggota-anggota squad mereka juga) yang tampil malam ini. Taeil menyanyikan Crush-nya 10cm diiringi permainan gitar akustik Winwin yang sangat terlatih. Suasana yang sebelumnya semarak berubah jadi sendu.
Taeyong memperhatikan dekorasi di sekitarnya. Kain-kain polos terjulur sangat panjang dari berbagai penjuru dan menyatu di beberapa titik, mengelilingi area penonton yang berbentuk setengah lingkaran di depan panggung. Cahaya lampu warna-warni dari panggung mengenai kain-kain itu, juga menyorot balon-balon yang melayang di semua sudut. Di luar setengah lingkaran ini adalah jajaran aneka booth. Ada yang hanya membuka jasa informasi klub tertentu, ada juga yang menjual makanan seperti crêpes. Taeyong berencana akan ke sana setelah pertunjukan Taeil dan Winwin selesai.
Tiba-tiba, pandangan Taeyong berhenti di wajah seseorang yang sedang menatapnya.
Pencahayaan yang redup tidak menghambatnya untuk mengenali wajah itu sebagai milik gadis yang tidak membalas suratnya.
Taeyong mengerjap. “Kau...?”
“Selamat malam,” Gaby membungkuk sopan—dan canggung. “Bisakah kita bicara sebentar?”
Taeyong mundur dari kerumunan dan mengikuti Gaby keluar dari area penonton.
Di tempat yang lebih sepi, Gaby meminta maaf dan menjelaskan alasannya. “Saya tidak tahu bagaimana harus membalas surat itu karena saya sudah mengajak orang lain, tetapi di saat yang sama juga takut membuat Sunbae kecewa. Maaf karena tidak menyampaikannya lebih cepat. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus membalasnya.”
“Ah... Aku juga minta maaf. Surat itu pasti konyol sekali kan? Seharusnya aku berbicara langsung denganmu,” kata Taeyong, entah mengapa merasa lebih lega karena setidaknya Gaby tidak benar-benar mengabaikannya. Taeyong juga secara otomatis memperhatikan penampilan gadis itu, dandanannya yang kasual dan riasan wajahnya yang natural, dan merasa agak senang karena kelihatannya Gaby menikmati festival seni ini. Hanya agak senang, sebab bukan ia yang menemaninya menikmati malam ini.
“Tidak... Saya suka surat itu.” Gaby tersenyum lebar. “Saya benar-benar suka. Saya akan menyimpannya sampai pulang ke Indonesia.”
“Ah, Indonesia? Maaf, aku kira Malaysia,” Taeyong tertawa paksa dan mulai merasa bodoh.
“Sunbae banyak sekali meminta maaf.”
“Iya, sepertinya begitu. Aku canggung sekali.”
“Tidak apa-apa. Surat itu sangat berarti. Belum pernah ada yang menulis surat seperti itu untuk saya. Saya sangat menghargainya. Terima kasih banyak,” ucap Gaby. “Mungkin kita tidak bisa mengobrol banyak malam ini, tapi kita masih bisa bertemu lagi di Velvety. Sunbae sepertinya sudah sering ke sana.”
“Lumayan. Ah, sebagai ganti balasan surat itu, kurasa kau harus menemaniku membeli crêpes.”
Gaby tampak terkejut mendengar ajakan tiba-tiba itu, tetapi detik berikutnya gadis itu tertawa. “Baiklah, baiklah. Sunbae suka yang rasa apa?”
Mereka kembali ke keramaian, berjalan berdampingan menuju ke booth crêpes. Walau tidak benar-benar menjadi teman kencannya, Gaby memperlakukannya tepat seperti yang Taeyong harapkan. Taeyong tidak memperhatikan hal lain selain langkah kaki mereka dan Gaby yang berjalan di sampingnya, yang berbicara padanya dengan penuh perhatian dan menanggapi perkataannya dengan senyum ramah yang hangat. Dia bahkan bilang kalau Taeyong bukan orang aneh (menyangkal apa yang Taeyong tulis di surat). Taeyong masih membayangkan betapa menyenangkannya kalau mereka bisa bersama lebih lama malam ini, tapi di saat yang sama ia juga sadar kalau interaksi kecil seperti ini saja sudah cukup. Setidaknya ia kini tahu kalau suratnya itu terkirim untuk orang yang tepat.
“Oh, itu Taeyong hyung.”
Rupanya sudah ada Doyoung, Ten, dan Johnny di depan booth crêpes. Yang barusan bicara adalah Doyoung. Taeyong dan Gaby berhenti berjalan di dekat mereka. Taeyong baru akan menanyakan keberadaan teman-teman mereka yang lain, tetapi Ten mendahuluinya dengan bertanya, “Gaby...? Kau... teman kencan Taeyong hyung?”
Hening. Semua orang tampak kebingungan dan berusaha memproses pertanyaan itu, sampai akhirnya Gaby membungkukkan sedikit badannya dan berkata, “Maaf, Ten, aku tidak tahu bagaimana harus membalas pesanmu.”
Hening lagi sebentar.
Kali ini Taeyong yang bicara duluan. “Jadi... Kau juga mengajak Gaby, Ten?”
Ten tampak tak percaya. “Hyung juga?”
“Tapi Gaby juga menolak ajakanmu?”
“Apa maksudnya ‘juga’? Gaby tidak pergi dengan Taeyong hyung?”
“Dia menemuiku untuk meminta maaf,” kata Taeyong.
Ten bertanya pada Gaby. “Lalu Gaby pergi dengan siapa?”
“Gaby!” Tiba-tiba seseorang memanggil. Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat Jaehyun sedang berlari kecil dengan riang ke arah mereka. “Oh, ternyata kalian berkumpul di sini. Yuta hyung dan Hansol hyung masih di backstage bersama Taeil hyung dan Winwin. Dan... kalian juga sudah bertemu dengan teman kencanku.”
Taeyong menatap Jaehyun tak berkedip, sementara Ten melongo.
“Sebentar, sebentar,” sela Doyoung yang memahami situasi dengan cepat. “Jadi ini maksudnya... Taeyong hyung dan Ten mengajak Gaby sebagai teman kencan, tapi Gaby menolak kalian dan pergi dengan Jaehyun...?”
Takut-takut, Gaby bergeser ke arah Jaehyun dan memeluk tangan pemuda itu. “Maaf,” ucapnya lagi dengan suara kecil.
Tawa Johnny serta-merta menyembur. Dia tertawa sampai memegangi perut. Doyoung membalikkan badan dan berusaha tidak menimbulkan suara, tapi bahunya yang berguncang-guncang jelas menunjukkan kalau dia juga tertawa. Jaehyun meringis pada Taeyong dan Ten, dan mengaku kalau ia tidak tahu apa-apa tentang ajakan mereka karena Gaby tidak pernah menceritakannya. Tetapi alih-alih menyalahkan Gaby, Taeyong dan Ten malah menyerbu Jaehyun dengan tendangan-tendangan kesal dan rentetan sumpah serapah. Terlebih, Jaehyun malah berkata “Hei, hei, bukan salahku kalau Gaby mengajakku pergi kan? Aku memang lebih keren daripada kalian.” Menghindari amukan massa, Jaehyun kabur ke area penonton. Ten mengejarnya.
“Sudahlah. Kita makan crêpes saja,” kata Taeyong, memutuskan untuk mengendalikan emosinya. Ia memelototi Doyoung dan Johnny. “Kalian bisa diam tidak?”
“Hyung, kami sudah pesan tiga,” kata Doyoung di sela-sela tawanya. “Kalau Hyung mau pesan lagi, satukan saja pesanannya.”
Johnny menghampiri Gaby dan menjabat tangannya dengan mantap. “Gaby, kau sangat hebat, bisa memancing tiga ikan sekaligus di kolam kami. Aku sangat salut.”
“A-Aku jadi merasa nggak enak....”
“Nggak apa-apa. Sudah biasa seperti ini. Nasib mereka memang selalu sial soal perempuan,” timpal Doyoung, yang kemudian mendapat tatapan membunuh dari Taeyong.
Ten dan Jaehyun kembali tak lama kemudian. Walau sempat terjadi kericuhan, pada akhirnya mereka semua duduk bersama di bawah sebuah pohon yang menyala karena dipasangi lampu fairy lights, menyantap crêpes masing-masing sambil mengobrol. Baik Taeyong maupun Ten sama-sama menikmati festival seni ini karena mereka tak hanya bersama dengan teman-teman mereka, tetapi juga dengan Gaby, gadis yang tidak membalas pesan-pesan mereka.
#x#oneshot#college au#spring hills au#nct#oc#gaby#taeyong#ten#taeten#doyoung#johnny#johnten#dotae#contemporary
1 note
·
View note
Photo



aku ingin membeli segelas kopi dan kutawarkan kepadamu. kamu akan menerimanya sambil tersenyum dan berkata, "terima kasih."
namaku tak terucap karena kau tak pernah tahu, tapi aku tahu aku baru saja membiarkan hatiku jatuh lagi untukmu.
untuk yang ketujuh kalinya minggu ini.
1 note
·
View note
Text
Write What You Love
Menyambung posting Stuck kemarin, saya ingin sharing tentang sesuatu yang bisa membuat kita menulis dengan nyaman. Terkadang, kita masih tidak menikmati menulis meskipun premis, biodata karakter, dan plot sudah matang. Komitmen pun ada, tapi kenapa, ya, kita tetap tidak bersemangat menulis?
Masing-masing penulis sebenarnya punya trigger atau penyemangatnya sendiri. Saya, terus terang, harus menyukai karakter-karakter rekaan saya dulu, baru bisa menulis dengan lancar. Sama halnya dengan saya harus menyukai tokoh dalam film atau buku dulu, baru bisa menyukai film dan bukunya.
Ketidaknyamanan menulis ini pernah saya alami. Saya tidak bersimpati dengan tokoh-tokoh saya sendiri. Akhirnya, progress saya pun melamban drastis. Memang novel itu akhirnya selesai, tapi teman-teman yang sangat mengenal saya akan berkata, “Prisca, this is so not you.” Saya tidak mengeluh, karena mereka benar. Waktu itu, sepertinya saya memang menulis bukan untuk diri saya sendiri. Saya berusaha keras menyajikan cerita yang mungkin akan disukai orang-orang tertentu, tapi bukan saya. Saya menyajikan tokoh-tokoh yang tidak ingin saya temui.
Inilah jawabannya. Inilah mengapa saya merasa berat sekali ketika menulis novel tersebut. Saya tidak bersimpati dengan tokoh-tokohnya.
Baru-baru ini, saya menyelesaikan dua novel—Alias dan Tulip. Meskipun proses Alias sangat lama—satu tahun—saya sangat bahagia saat menulisnya. I love the characters so much. Saya belum bisa membongkar siapa sebenarnya mereka; yang jelas, they’re crazy in their own way. Bukan jenis orang yang bisa kita temui setiap hari. Prosesnya sendiri lama bukan karena saya bermasalah dengan cerita atau karakternya, tapi karena banyak sekali riset dan pertimbangan yang harus dilakukan.
Sementara untuk Tulip, saya menyelesaikannya cukup cepat. Temanya mungkin umum, tentang cinta sejati. Tapi saya ingin menghadirkan kisah cinta yang saya sukai, yang membuat hati saya hangat, yang disisipi teka-teki kecil, yang membuat saya hangover sampai berhari-hari. Saya menyayangi tokoh-tokohnya. Mereka sederhana, tapi ada sesuatu dalam diri mereka yang sangat saya kagumi. Sekali lagi, saya belum bisa membocorkan. :”)
Jadi, kesenangan ketika menulis itu bergantung pada seberapa besarnya rasa suka kita terhadap elemen cerita tersebut. Penulis-penulis lain bisa jadi sangat berbeda dengan saya. Ada yang tidak masalah meskipun tidak menyukai tokohnya, yang penting menyukai setting-nya. Ada yang harus menulis dengan tema tertentu dulu baru bisa merasa nyaman.
Johnny Depp, ketika berakting menjadi tokoh tertentu, akan mengasosiasikan tokoh-tokoh tersebut dengan hal yang dia sukai. Semisal, saat dia berperan sebagai Captain Jack Sparrow, dia membayangkan gerak-gerik Keith Richards, personel Rolling Stones idolanya. Saat berperan sebagai Edward Scissorhands, dia membayangkan kesetiaan hewan peliharaan kepada majikannya. In short, semua kegiatan seni itu membutuhkan trigger, role model, semacamnya. Kita bukan Tuhan yang secara tiba-tiba mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. :)

Quote di atas benar sekali. Semisal, kita senang sekali dengan kota Surabaya. Tiba-tiba, cuma gara-gara Surabaya kurang gaul xD, kita mengubah setting cerita di Bali, padahal sama sekali tidak suka Bali (ini misalnya lho, bukan curcol xDD). Itu bisa saja mengurangi semangat ketika menulis. Kalau dalam kasus saya—kalau saya harus mengubah sesuatu yang saya sukai menjadi sesuatu yang tidak saya sukai—saya akan sangat malas menulis. Untuk apa? Untuk apa melakukan hal yang tidak membuat saya bahagia?
Kata Gustave Flaubert, “You must write for yourself, above all. That is your only hope of creating something beautiful.” Flaubert sama dengan Mendelssohn. “Ever since I began to compose, I have remained true to my starting principle: not to write a page because no matter what public, or what pretty girl wanted it to be thus or thus; but to write solely as I myself thought best, and as it gave me pleasure.” Ucapan mereka akan selalu menjadi pedoman menulis bagi saya.
*
Pada akhirnya, kunci menulis dengan nyaman itu sangat sangat mudah. Sangat sederhana. Write what you love.
Kalau sudah cinta, kita pasti akan melakukan apa pun demi yang dicintai, bukan? :)
*
20 notes
·
View notes
Photo



jeno, renjun (feat. hyung line dreamies)
The Boy on the Roof
words: 761
Seorang anak laki-laki selalu duduk di atap rumah tetangga Jeno setiap malam terang benderang. Jeno tidak tahu siapa dia. Jeno tidak pernah melihatnya di sekolah. Kalau dia tinggal di lingkungan tempat tinggal Jeno, Jeno pasti sudah lama mengenalnya seperti ia sudah lama mengenal Jaemin dan Haechan. Jeno memutuskan untuk berasumsi bahwa anak itu adalah cucu tetangganya, Mister Huang, yang berkunjung secara berkala ke sini. Setiap anak itu duduk di atap rumah, Jeno memandanginya dari balik jendela kamar. Rumah itu tidak bertingkat, sementara kamar Jeno berada di lantai dua. Ada pekarangan yang cukup lebar yang memisahkan kedua rumah itu, makanya Jeno hanya bisa memperhatikan anak itu dari jarak yang agak jauh. Anak itu duduk bersila di bagian atap yang datar, atau ongkang-ongkang kaki di perbatasan antara bagian atap berlantai semen dan bagian atap yang miring berlapis genteng. Biasanya dia memandangi langit, atau menatap ke depan, atau mengamati daun-daun pohon di depan rumah yang bergoyang-goyang diembus angin, lalu menuliskan apa pun yang dia dapat dari kegiatan itu di dalam bukunya yang kelihatannya bersampul kulit sintesis. Jeno memperhatikannya sampai mengantuk atau anak itu turun dari atap dengan tangga di sisi lain rumah yang tidak terlihat dari arah Jeno. Ini biasanya bisa sampai pukul dua belas.
Ada sesuatu dari anak lelaki itu yang mempunyai efek memikat. Mungkin itu pakaiannya yang tampak kurang wajar dikenakan di tempat dan waktu saat ini. Seragam pelaut, kemeja putih rangkap rompi perompak, setelan formal anak bangsawan, dan pakaian-pakaian lain yang terlihat out of place seakan-akan dia berasal dari belahan dunia lain atau sedang pesta kostum sendiri. Warna rambut pendeknya mengingatkan Jeno pada minuman pumpkin white chocolate yang sedang ngetren di kedai-kedai kopi dan kafeteria sekolahnya. Kalau sedang tidak ditutupi topi (sebab anak itu kerap mengenakan topi), rambut itu bergerak-gerak seirama dengan daun-daun yang digoyangkan angin, terlihat begitu halus dan lembut sampai-sampai memperhatikannya memberi perasaan menenangkan tersendiri.
Jeno selalu mencarinya ketika hari terang. Sengaja lewat di depan rumah Mister Huang dengan mata awas mencari-cari. Terkadang, ia duduk di trotoar seberang jalan rumah itu, di depan rumah Nyonya Choi si penjahit hanbok, dengan lagak menunggu Jaemin dan Haechan datang sebelum pergi ke lapangan milik satu-satunya universitas di kota kecil ini untuk main sepak bola. Namun, telah lama diketahui bahwa tidak pernah ada seorang pun yang keluar dari rumah itu setelah Mister Huang pergi pukul setengah tujuh pagi untuk membuka toko suvenir di pusat kota. Mister Huang adalah pensiunan dosen yang merangkap seorang pengrajin. Pria tua itu membuat mainan anak-anak dan benda-benda unik lainnya yang dijadikan suvenir. Setahu Jeno, Mister Huang memang tinggal sendirian. Tetangga-tetangga di kanan-kiri dan depan rumah sering dimintai tolong pria tua berambut abu-abu itu untuk mengawasi rumahnya selama dia bekerja. Jeno sering berpapasan dengannya di jalan dalam perjalanan ke sekolah karena Mister Huang pergi di waktu yang sama dengan Jeno berangkat. Jeno selalu menyapanya sebagaimana seorang anak wajib bersikap sopan dan hormat pada orang tua, terlebih kalau orang tua itu adalah tetangganya sendiri. Mister Huang mengembalikan sapaan itu dua kali lebih ramah, dengan senyum yang lebih lebar, matanya yang sudah tua tapi masih berbinar-binar menyipit dan menunjukkan kerutan-kerutan usia lanjut di setiap ujungnya. Mister Huang selalu mengenakan setelan jas yang mengingatkan Jeno pada film-film Barat abad 20. Kadang-kadang, Jeno dan teman-temannya menjulukinya “Huang Fredrickson” meskipun itu agak tak sopan, sebab perawakan pendek tapi bugar Mister Huang mengingatkan mereka pada Carl Fredrickson. Apalagi, rumah orang tua itu bergaya sama seperti rumah Carl Fredrickson, hanya saja lebih mungil, asri, dan tidak bertingkat. Namun, tentu saja, anak-anak lelaki itu tidak pernah menggunakan julukan itu untuk memanggil Mister Huang secara langsung.
Libur musim panas telah dimulai. Di pertengahan bulan, cucu Mister Huang berkunjung lagi. Seperti biasa, lewat pukul sepuluh malam, dia duduk di atap rumah. Jeno sudah bertekad akan menemuinya. Ini sudah direncanakan sejak Haechan bilang Jeno sama saja seperti kakak kelas mereka, Mark, yang hanya bisa memandang orang yang disukainya dari jauh karena tidak berani mendekat. Meskipun konteksnya sedikit berbeda, Jeno tidak mau dianggap sama payahnya begitu saja. Malam ini, ia tak akan hanya memperhatikan dari balik jendela. Malam ini, jendela itu dibuka dan Jeno–dengan badan sedikit dicondongkan ke luar–menyahut, “Hei!”
Anak laki-laki yang duduk sendirian di atap itu terperanjat.
Dia menoleh ke arah Jeno, tapi caranya menggerakkan leher membuat Jeno terpaku sejenak. Setelah itu, Jeno buru-buru menutup jendela, menggerai tirai, dan menempelkan punggung di sebelah jendela dengan dada membusung dan mata membelalak. Jantungnya berdetak cepat.
A-Apa yang….
Gerakan patah-patah itu benar-benar membuat Jeno ketakutan. Seakan-akan, leher anak itu digerakkan oleh engsel! Jeno memutuskan untuk melupakan malam ini. Aku nggak perlu memikirkan anak laki-laki yang selalu duduk di atap rumah Mister Huang setiap langit purnama dan menoleh dengan cara yang tidak manusiawi ketika kupanggil, tegasnya pada dirinya sendiri. Ia pun naik ke tempat tidur dan meringkuk di bawah selimut.
to be continued?
2 notes
·
View notes
Photo




Alienated
chara: Sara (OC), Lucas
category: one-shot, high school, neo culture school, novel-material
genre: fluff, contemporary, comedy?? kalau ada yang ketawa aja sih
words: 3.6k
inspirations: lucas’ airport previews from when he was going to return to kr??
A/N: i had sooooo much fun writing this!!! i thought i couldn’t stop because sara is so unique she’s got a huge potentials to lead a novel. i guess this has become a new au since i want to write more about her (feat. lucas). also she’s perfectly visualized by yurisa (insert love-eyed emoji here).
harusnya soccerplayer!lucas tapi aku ganti jadi basketballplayer.
let me know what you think in the message (talk to me) box~
Ada seorang anak laki-laki di sekolahku yang matanya sangat besar seperti mata kodok. Dia cukup populer. Lokernya nomor 125. Aku tahu karena itu tiga loker di sebelah lokerku. Meskipun pernah beberapa kali sekelas dengannya--sekarang pun kami berbagi dua kelas yang sama--kami tidak benar-benar saling mengenal. Lagi pula, dia sangat tipikal anak populer. Kau tahu; wajah blasteran Asia Timur dan Asia Tenggara yang tampan, tubuh jangkung atletis, dikelilingi banyak teman, jagoan klub basket. Hal-hal yang disukai banyak orang seperti itu biasanya malah membuatku tak tertarik dan mengabaikannya sama sekali. Dia hanya seorang figuran yang sesekali lewat di pertunjukanku karena kebetulan loker kami berdekatan dan kami sekelas di dua mata pelajaran yang sama.
Hingga tiba hari di mana dia memergokiku mengeluarkan sekotak rokok dari dalam loker.
Momen itu masih teringat dalam kepalaku seperti permen karet yang menempel di bawah meja. Waktu itu aku menukar barang-barangku sambil melamun; kalau tidak salah, aku sedang memikirkan betapa menyebalkannya Pak Lee guru Fisika yang mengubah tugas individu menjadi tugas kelompok seenak jidat. Aku jadi kurang waspada ketika mengeluarkan rokok yang selalu kuambil setiap menjelang kelas terakhir sebelum makan siang. Biasanya aku langsung menyembunyikannya di antara dua buku atau di dalam saku baju, tapi hari itu aku memegangnya dengan santai di tangan kiriku yang mendekap tumpukan buku, sekasual seseorang membawa sekotak cokelat. Lalu aku menoleh tanpa tujuan khusus ke arah kiri dan mendapati anak laki-laki itu sedang menatapku tanpa berkedip dengan mata kodoknya. Ih, apaan, sih? Aku mengerutkan kening dan setengah memelototinya untuk menunjukkan rasa terganggu. Lalu aku memalingkan muka dengan angkuh ke depan dan dua detik kemudian menyadari kalau yang sedang cowok itu pandangi adalah rokok di tanganku.
Aku benar-benar masih ingat apa yang terjadi saat itu. Di dalam otakku alarm tanda bahaya menyala dan meraung-raung. Hiruk-pikuk orang-orang yang mengobrol dan berseliweran di lorong tiba-tiba melambat dan mengabur. Frame yang jernih dan jelas hanya memuat bagian loker di mana aku dan cowok itu berdiri membelakangi orang-orang itu, berhadapan dengan loker kami masing-masing yang masih terbuka lebar, aku berdiri kaku dengan perasaan ingin lenyap ditelan Bumi, dan cowok itu menatapku yang mungkin hanya sebentar, tapi rasanya lama sekali. Sampai akhirnya, bel berbunyi.
Cowok itu berhenti memandangku, menutup pintu lokernya dengan satu gerakan tangkas, dan beranjak pergi seolah tak ada apa pun yang terjadi. Aku melakukan hal yang sama, tapi pergi ke arah yang berlawanan dengannya. Tanpa sadar tangan kiriku meremas kotak rokokku sampai benda itu penyok dan ingin kutelan saja. Wajahku tertunduk dalam sampai hidungku mencium ujung buku-buku yang kudekap dan orang-orang harus menghindariku supaya tidak kutabrak. Mulutku tidak bisa berhenti menggumamkan kata-kata umpatan.
Rokokku ketahuan, brengsek... Rokokku ketahuan... Rokokku ketahuan... Gagasan itu melayang-layang dalam font berukuran 72 di pikiranku. Warnanya merah elektrik dengan outline oranye pucat yang sangat jelek. Aku berusaha menenangkan diri dengan mengingat-ingat sebuah kutipan yang pernah kulihat di internet. If you aren't going all the way, why go at all? Memang akan ada saatnya perbuatan sneaky-mu ini ketahuan kan, Sara? Rahasia apa pun tidak akan menjadi rahasia selamanya. Bukankah kamu sudah lama menyiapkan mental kalau-kalau momen itu tiba di saat yang tidak terduga seperti ini? Lagi pula, hukuman sekolah tidak akan terlalu buruk. Kamu hanya akan ditegur dan menjalani detensi.
Suara lain dalam kepalaku menyahut, Tapi citramu sebagai gadis baik yang seperti boneka akan tercemar.
Detik berikutnya platform tebal ankle boots hitamku mengetuk-ngetuk lantai lorong yang sudah sepi seperti orang lari dikejar anjing ganas. Aku belok ke lorong lain dan naik tangga. Kutemukan si Mata Kodok sedang berbicara dengan seorang anak laki-laki lainnya di depan pintu kelas. Aku tiba di hadapannya dalam keadaan terengah-engah.
"M-Maaf," kataku sambil terbungkuk-bungkuk karena perutku sakit. "Aku--"
"Temui aku di tribun lapangan sepulang sekolah," sela cowok itu tiba-tiba, membuatku menegapkan badan untuk melihatnya dengan mulut sedikit ternganga. Aku kira dia bicara pada temannya, tapi dia sedang menatapku. "Perhatikan orang yang kausnya bernama Lucas. That'd be me."
Setelah itu dia masuk ke kelas, temannya pergi ke kelas lain. Aku ditinggalkan sendirian dalam keadaan bingung dan melongo.
Aku sudah tahu namanya Lucas. Kenapa dia bersikap seakan-akan kami tidak pernah sekelas? Padahal kan baru semester kemarin, dan satu semester adalah waktu yang sangat cukup bagiku untuk mengenal nama-nama sebagian besar teman sekelasku. Sekarang aku sudah lupa, sih, tapi aku tidak lupa wajah-wajah mereka. Terutama wajah si Mata Kodok yang selalu muncul tiga loker di sebelahku setiap hari. Gayanya menyebalkan sekali. Mentang-mentang anak populer.
Aku jadi sadar kalau rahasiaku berada dalam bahaya yang cukup serius. Orang seperti Lucas biasanya tidak bisa dipercaya. Menurut pengamatanku, anak-anak populer yang kebanyakan gaya seperti itu berperasaan dangkal dan senang mempermainkan orang yang tidak sederajat dengan mereka. Ini membuatku memasang perisai tak kasatmata untuk setidaknya terlihat tidak mudah diintimidasi. Aku duduk di bangku tribun nomor tiga dari atas. Bangku ini hanya ditempati aku seorang, tapi aku tidak sendirian. Bangku-bangku di bawahku ditempati beberapa anak yang sedang menonton latihan klub sepak bola; sebagian kecil kukenali sebagai adik kelas yang pernah kuwawancarai untuk proyek tabloidku (aku masih ingat nama mereka: Renjun, Jaemin, dan Haechan). Punggungku kutegakkan, daguku kuangkat, dan kakiku kusilangkan. Aku tidak tahu di mana Lucas sekarang. Tapi kalau dia mengamatiku dulu dari kejauhan, kesan yang harus dia dapatkan dariku adalah seorang gadis yang terhormat dan arogan yang tidak pantas dipermainkan.
Lama-lama, punggungku pegal dan aktingku goyah. Sial, kenapa dia nggak datang-datang, sih? Jangan-jangan, aku memang sedang dipermainkan?
Sembari menunggu, aku ikut menonton latihan sepak bola yang tengah berlangsung. Kurang lebih dua puluh anak laki-laki bergantian menggiring dan mengoper bola. Cuaca berawan dan angin lembut yang berembus membisikkan godaan-godaan yang harus kutahan: merokok dan tidur. Biasanya yang kupilih adalah merokok, sebab tidur di tempat terbuka seperti ini membuatku insecure. Uh, aku benar-benar ingin melipir ke hutan kecil yang membentengi wilayah sekolah dengan jalan raya untuk merokok. Tapi keinginan itu segera kupendam dalam-dalam mengingat situasi genting yang sedang kualami saat ini. Aku harus membungkam Lucas dulu supaya satu-satunya kegiatan escapism yang bisa kulakukan di wilayah sekolah internasional yang membosankan ini bisa terus berlanjut.
"Hei."
Akhirnya, suara itu terdengar juga. Suara Lucas mudah diingat. Untuk remaja seumurannya, dia punya suara yang sangat dalam dan berat. Dia naik ke tribun dan menghampiriku. Aku memperhatikan pakaiannya yang tidak lagi kaus merah berlapis jaket hitam dan celana jeans hitam, tapi telah diganti menjadi kaus putih lengan pendek dirangkapi jersey basket hitam-merah bernama punggung LUCAS dan celana pendek longgar berwarna abu-abu. Apa dia kabur dari latihan untuk menemuiku?
"Maaf membuatmu menunggu lama." Dia rupanya duduk di bangku di atasku. Aku harus memutar sedikit tubuhku dan mendongak untuk bisa melihatnya. Astaga, menyusahkan sekali.
"Nggak usah terlalu sopan," cetusku.
Ketegasanku mengejutkannya. "Excuse me?"
"Itu benar rokokmu?"
"Tentu saja."
Aku sangat straightforward. Lucas perlu menatapku bodoh dengan mata kodoknya yang mengerjap-ngerjap kaget dulu, baru kemudian tersenyum terhibur dan berkata, "Itu menjelaskan kalau rokok itu benar-benar milikmu. Padahal aku kira kamu hanya membawakan rokok orang lain."
Benar juga. Kenapa aku tidak berusaha mengarang alasan? Sialan.
"Tapi, sekalipun kusebarkan ke semua orang di sekolah, nggak akan ada yang percaya gadis lolita sepertimu ternyata suka merokok."
"Siapa yang gadis lolita?"
"Aku," kata Lucas, lalu menambahkan dengan wajah mengeluh, "Ya kamulah."
Wajahku menghangat. Meskipun hobiku adalah berdandan lucu seperti boneka, tidak pernah ada seorang pun yang menyebutku gadis lolita sebelumnya. Tidak pula teman-temanku yang tak seberapa jumlahnya. Mereka selalu menyampaikan rasa sayang dengan cara menghujat. Tiba-tiba, aku jadi sangat sadar diri dengan penampilanku sekarang. Hari ini aku tidak terlalu menghabiskan banyak waktu dan energi untuk berdandan. Riasan wajahku natural kecuali bagian mata yang selalu kutonjolkan dengan maskara dan warna-warna yang agak tebal. Choker hitam di leherku polos dan tidak berliontin. Atasanku hanya kemeja chiffon polos yang berkerut di area pundak dan dada, yang kuhiasi dengan dasi pita merah marun panjang agar tidak sepi-sepi amat. Bawahanku rok lipit hitam berpinggang tinggi. Rambut cokelat panjangku tergerai lurus tapi terjalin rapi di atas bahu kananku, tanpa hiasan apa-apa. Perhiasanku pun hanya anting-anting dan gelang membosankan yang selalu kukenakan kalau aku sedang malas meniru boneka. Dandananku hari ini polos sekali, tapi "gadis lolita sepertimu" itu tadi membuatku merasa sangat cantik dan menarik.
Sialan, sialan, sialan. Aku tidak datang ke sini untuk merasa tersanjung oleh komentar seseorang yang bisa meruntuhkan karier sekolah menengahku hanya dengan sekali buka mulut.
Aku berdeham. "Memangnya gadis lolita nggak boleh merokok? Suka-suka aku kan."
"Itulah yang kupelajari dari peristiwa ini. Memang nggak bagus menilai seseorang hanya dari penampilannya saja."
"Jawab pertanyaanku tadi," kataku, meluruskan pembicaraan ini. "Jangan membuatku melakukan hal-hal yang merepotkan."
"Aku sudah memikirkannya." Lucas tersenyum. "Dengarkan aku bercerita tentang sesuatu."
Giliran aku yang mengerjap-ngerjap dan menatapnya tak mengerti. "Hah? Apa kamu bilang? Mendengarkanmu bercerita?"
Lucas mengangguk-angguk. Matanya berbinar-binar dan senyumnya mengembang manis. Tiba-tiba aku ragu dia seangkatan denganku. Seharusnya ekspresi antusias seperti itu hanya dimiliki anak kecil, bukan remaja bersuara orang dewasa dan berbadan tower sepertinya. Dan lagi, mendengarkannya bercerita? Hanya itu yang perlu kulakukan untuk membuat kesepakatan dengannya?
"Memangnya kamu mau cerita apa?" tanyaku.
Melihatku menatapnya jijik, Lucas buru-buru melambai-lambaikan tangan. "Bukan, bukan! Bukan yang aneh-aneh! Sama sekali nggak aneh-aneh, kok."
"Kamu mau mencuci otakku, ya?"
"Mau rahasiamu tetap aman atau nggak, sih?"
"Dih, tiba-tiba ngancem."
"Makanya dengarkan aku dulu. Ini cerita yang hanya bisa kuceritakan pada orang-orang tertentu. Aku pernah menyinggungnya sedikit di depan teman-temanku, tapi mereka malah mengejekku."
Aku masih curiga, tapi sekarang jadi penasaran juga. Lucas pun mengalami momen menyedihkan seperti itu? Aku kira dia selalu disukai semua orang di dunia.
"Ya sudah. Cepat cerita." Aku bersedekap dan memandang ke arah lain.
Selama beberapa saat aku hanya mendengar sahut-sahutan anak-anak klub sepak bola dan dengungan percakapan orang-orang di tribun. Mengerling ke belakangku, Lucas sedang menumpu wajahnya yang tertunduk dengan tangan yang kedua sikunya ditumpukan di paha. Kaki kanannya bergerak naik-turun sangat cepat seperti orang yang sedang gelisah. Dia seperti pemain basket yang berdoa untuk meredakan perasaan gugup sebelum disuruh ikut bermain menggantikan pemain lain di arena. Cerita macam apa sih, yang sampai membuatnya gugup begitu sebelum memberitahukannya ke orang lain? Ini bukan cerita pribadi seperti soal keluarga atau masa lalu kelam atau kisah percintaan kan? Karena kalau iya, aku tidak mau mendengarnya. Bagaimanapun, kami masihlah orang asing terhadap satu sama lain. Terlebih, membongkar diri semudah itu pada orang lain adalah gejala masalah kepribadian. Atau, dia bermaksud menipuku dan menyeretku ke dalam rencana kejahatan. Ada begitu banyak hal yang bisa dicurigai sampai-sampai aku sama sekali tidak mempertimbangkan kemungkinan Lucas berkata,
"Sebenarnya, aku percaya alien dan UFO benar-benar ada di dunia."
... Aku rasa aku hampir terjungkal dari tempat dudukku?
"Serius," kata Lucas begitu melihatku menatapnya dengan ekspresi terenyak. Cowok itu benar-benar terlihat serius. Tapi, alien dan UFO setelah aku menebak persoalan keluarga sampai rencana kejahatan--dia nggak mungkin serius kan?
Lalu Lucas bercerita tentang pertemuannya dengan makhluk-menyerupai-manusia-tapi-bukan-manusia-karena-matanya-sangat-besar (seperti dirinya sendiri, dong??) ketika camping bersama keluarganya di pegunungan Thailand. Waktu itu usianya enam tahun. Dia menjelaskan dengan berapi-api tentang bagaimana makhluk aneh itu terlihat sangat nyata; bagaimana tubuhnya, bentuk wajahnya, tekstur kulitnya, caranya menatap Lucas, suaranya yang terdengar seperti orang berbicara sambil berkumur. "Pertemuan itu benar-benar nyata, dan alien itu tidak berniat jahat padaku. Kami hanya saling melihat, saling tatap, lalu dia mengatakan sesuatu yang tidak kupahami meskipun aku menguasai tiga bahasa. Aku kebingungan dan ketakutan, jadi yang kulakukan untuk menjawabnya hanya mengangguk. Setelah itu, alien itu berjalan pergi. Aku memperhatikannya sampai dia menghilang ke dalam hutan. Sampai aku dan keluargaku pulang, dia tidak pernah muncul lagi," cerita Lucas.
Aku ingin menyela, Memangnya dengan menguasai tiga bahasa, kamu bisa berkomunikasi dengan bahasa-bahasa lain juga? Tapi, aku menahannya. Aku tidak pernah melihat Lucas yang seperti ini sebelumnya, yang berbicara denganku seakan-akan dia telah lama mengenalku dan aku adalah orang yang dia percaya. Padahal, ini kan interaksi pertama kami yang sesungguhnya. Interaksi-interaksi sebelumnya tak dihitung karena tidak ada yang lebih dari senyum basa-basi tiap berkontak di kelas. Lalu, wajahnya yang tampak merana itu.... Sudah berapa kali dia menceritakan kisah yang sama tapi hanya ditanggapi dengan tawa konyol dan ejekan? Antusiasmenya tidak pernah bersambut reaksi yang baik. Sekarang pun, binar di matanya sudah meredup, seakan-akan seiring dengan semakin banyaknya kata yang keluar dari mulutnya, semakin jauh aku dari mempercayai ceritanya. Salahnya sendiri sih, menceritakan sesuatu yang sulit dipercaya seperti itu pada orang lain yang belum tentu berpandangan sama. Aku jadi kasihan.
Lucas memperhatikan wajahku untuk melihat bagaimana reaksiku. Baru kali ini aku ditatap seintens ini oleh mata kodok itu. Tiba-tiba saja adik kelas anak klub sepak bola berambut pirang yang baru saja naik ke tribun untuk menghampiri Renjun dan kawan-kawannya terlihat lebih mudah dipandang daripada bertatapan dengan mata besar itu.
"Um, menurutku," gumamku. "Kalau makhluk itu tidak berperilaku seperti manusia, bisa jadi dia memang alien...."
"Tidak berperilaku seperti manusia?"
"Alien itu makhluk hidup berakal selain manusia yang hidup di planet lain kan? Perilaku mereka pasti berbeda dengan manusia karena, uh... perbedaan kebudayaan?" Ngomong apa kamu ini, Sara. "Maksudku, mereka pasti punya bahasa dan cara-cara sendiri untuk, misalnya, menyapa orang lain. Manusia menyapa manusia lainnya dengan cara melambaikan tangan. Alien mungkin melakukannya dengan... apa, ya, menggelengkan kepala?? Aku nggak tahu, tapi menurutku itu masuk akal."
Aku melirik cowok itu, lalu menoleh sepenuhnya ke arahnya ketika melihatnya hanya menatapku dengan senyum lebar. Matanya sudah berbinar-binar lagi. "Ada apa dengan ekspresimu itu?" tanyaku bergidik.
"Aku tahu kamu memang orang yang tepat," kata Lucas puas.
Maksudnya?????
"Aku pernah membaca artikel tentang kebenaran alien dan UFO di tabloidmu. Kamu menyebutkan Kevin Hand dan penelitian microbial life-nya di satelit Yupiter dan ekosistem-ekosistem ekstrem Bumi untuk mendukung keberadaan alien. Aku baru tahu tentang itu. Setelah membaca artikel itu, kalau ada orang yang menyangsikan pengalamanku, aku bisa memberikan penjelasan berdasarkan penelitian Kevin Hand. Aku merasa harus berterima kasih padamu karena telah mempublikasikannya dan membagikan tabloidmu ke klub basket."
Aku mengerjap-ngerjap terpana. Tapi artikel itu kutulis untuk anak-anak geek karena aku kasihan pada mereka yang selalu tersingkirkan karena kalah kuasa dengan anak-anak populer?? Aku tidak menyangka salah satu anak populer itu malah membacanya?? Sekarang Lucas menatapku seakan-akan aku pernah menyelamatkan hidupnya atau apa. Matanya yang bersinar dan senyum manis kebocahannya.... Bisa tidak sih dia berhenti melakukan itu? Sebab aku mulai menganggapnya imut dan aku tidak suka merasa seperti itu terhadapnya.
"Hanya itu saja yang mau kamu ceritakan?" tukasku. "Kalau begitu, kita deal."
"Baiklah. Lagi pula nggak ada untungnya bagiku menyebarkan hobi terselubungmu itu," kata Lucas riang.
Sebaiknya aku segera pergi sebelum dia semakin membuatku kesal.
"Eits!" Tangan Lucas tiba-tiba terulur di depan wajahku. Aku baru saja berdiri. Tangan itu menghalangi jalanku. Aku hanya menghela napas dan berniat membalikkan badan untuk turun lewat undakan di sisi lain bangku, tapi Lucas cepat-cepat berkata, "Kenalan dulu!"
Aku menatapnya.
Lucas nyengir. "Namaku Lucas Wong."
"Kamu inget nggak sih, kita pernah sekelas selama satu semester?"
"Ingetlah. Siapa pun nggak akan semudah itu melupakan gadis lolita yang pernah sekelas dengan mereka. Tapi kita belum pernah berkenalan secara resmi kan?"
Uh. "Gadis lolita" itu lagi. Aku suka julukan itu, tapi aku benci julukan itu baru kudapatkan sekarang dari orang seperti Lucas. Maksudku, seharusnya aku tidak tertarik sama sekali pada orang sepertinya, tapi aku tidak tahu lagi apa yang sekarang kurasakan. Sepertinya dia tidak seburuk yang kupikirkan??
"Ayo, dong. Tanganku pegal, nih," Lucas mengeluh. Tangan kanannya sekarang disunggi tangan kiri. "Cepat, aku harus kembali latihan basket."
Kuangkat tangan kananku untuk menyambut uluran tangannya. Lucas nyengir lagi. "Aku Lucas Wong," katanya sekali lagi.
"Yoo Sara."
Cengiran Lucas berubah menjadi senyum kalem. "Aku tahu. Terima kasih sudah mempercayaiku."
"Aku tahu"? Jadi selama ini dia ingat namaku?
Sialan.
Dengan sedih harus kuberitahukan bahwa setelah hari itu, aku jadi akrab dengan Lucas. Kuanggap diriku telah ter-alienated (secara konotatif).
Setiap kali bertemu saat menukar barang di loker, cowok itu selalu menyapaku dengan "Hai" dan senyum nyengir yang riang. Dia tetap mengucapkan itu walau di antara kami ada orang lain yang juga sedang menukar barang, sampai-sampai orang itu kaget karena merasa tiba-tiba disapa. Kalau itu terjadi, biasanya Lucas akan bilang, "Oh, maaf, bukan kamu." Demi Tuhan, itu menyebalkan sekali. Aku hanya akan memutar mata dramatis dan menganggapnya tidak pernah bicara. Itu juga kulakukan di dua kelas yang sama yang kami ikuti. Lucas sekarang senang duduk di sebelahku dan secara berkala menunjukkan layar ponselnya kepadaku di balik meja kami. "Aku menemukan video penampakan UFO yang diambil saat Korea mengalami demam UFO," bisiknya sementara guru menjelaskan jenis-jenis seni rupa. Beberapa menit sebelumnya, dia menunjukkan transkripsi laporan berita CNN World Report tentang penampakan UFO itu. Aku bertopang dagu memandang presentasi yang diproyeksikan di muka kelas, berusaha cuek. "Sara, menurutmu, sedang di mana aku waktu itu?"
Pertanyaan itu memaksaku menoleh sebentar ke arahnya untuk memberinya kerutan kening dan tatapan kesal. "Demam UFO di Korea itu tahun 1996. Kamu belum lahir, bodoh."
"Tapi mungkin saja sebelum lahir menjadi manusia, aku adalah makhluk ekstraterestrial."
Di saat itulah aku memutar mata dramatis dan menganggapnya tidak pernah bicara.
Teman-temanku, para penghujat Sara, memergoki kedekatan kami dan tidak bisa berhenti menggodaku sementara aku bersikeras meyakinkan mereka kalau sikapku terhadap Lucas adalah semata-mata sebagai seorang Penghujat, bukan Pemuja. Lagi pula, kami memang hanya berteman biasa. Ada apa, sih, dengan orang-orang yang selalu menganggap dua orang laki-laki dan perempuan yang berteman akrab sebagai pasangan? Lagi pula, aku memperlakukan Lucas dengan baik karena dia memegang rahasiaku. Ini adalah situasi "mau tak mau". Lucas mungkin bilang menyebarkan rahasiaku itu tidak akan memberinya keuntungan apa pun, tapi siapa yang tahu kapan seseorang berubah pikiran? Apalagi kalau tiba-tiba dia membenciku. Aku tidak mau hidupku runyam hanya gara-gara ketahuan membawa rokok ke kampus.
Aku tidak pernah bercerita pada para penghujat Sara soal suatu momen ketika Lucas membuatku... uh... tersanjung habis-habisan. Itu terjadi di hari aku merasa suasana hatiku sangat bagus. Suasana hati yang bagus selalu memicu ide-ide dandanan lucu, maka aku merelakan sedikit waktu tidur untuk bangun lebih pagi dan mengubah diriku menjadi gadis desa abad 18 bergaya Eropa yang elegan. Aku mengkombinasikan kemeja putih lengan panjang model cuffed dengan apron dress selutut bermotif floral. Warnanya ungu thistle seperti warna bunga lilac. Gaun itu dilapisi apron putih tipis berenda yang sangat manis di luarnya. Alas kakiku kaus kaki putih semata kaki berenda dan sepatu oxford putih Grenson yang juga sangat manis--aku suka sekali warna cokelat di bilurnya. Rambutku yang sudah kucatok lurus kubiarkan tergerai; sedikit bagian di belakang kedua telinga kujalin ke belakang dan dipertemukan di belakang kepalaku, lalu diikat dengan tali rambut dan dijepit dengan pita ungu. Poninya jatuh dengan rapi dan rata menutupi dahiku. Riasan wajahku natural dan tidak terlalu tebal karena guru pelajaran Tata Susila pernah memperingatkanku untuk memilih satu saja yang berlebihan di antara pakaian atau rias wajah, sebab kalau dua-duanya berlebihan, penampilanku akan dianggap "tidak patut". Kurasa itu ada benarnya, makanya kupatuhi sampai sekarang. Meskipun membiarkan siswa-siswi berdandan ekspresif, sekolah tetaplah sekolah.
Seperti biasa, penampilanku membuat orang-orang di asrama dan kampus menoleh dan menatapku sebentar sebelum sadar kalau mereka baru saja menghabiskan beberapa detik atau menit yang berharga untuk menghakimi seseorang berdasarkan penampilannya. Aku sudah biasa dengan itu. Selama aku diperhatikan karena aku menjadi diriku sendiri dan bukan karena ritsleting bajuku terbuka atau rokku tersibak tanpa sepengetahuanku, tidak ada yang perlu kupermasalahkan. Hari itu aku tidak punya jadwal yang sekelas dengan Lucas. Seharian, aku tidak bertemu dengannya di depan loker. Kudengar dia memang sedang sibuk dengan tes-tes dari kelas-kelas yang dia ikuti, juga latihan-latihan basket menjelang turnamen. Aku mendapat pujian dari guru-guru perempuan yang muda (yang sudah agak tua biasanya memandangku sebelah mata). Dua orang adik kelas mencegatku di lorong dan memintaku berfoto bersama. Kelas-kelas yang berlangsung setelah makan siang rupanya juga mulai menghujani murid-murid dengan tes dan tugas. Aku sadar ada empat dari lima tugas yang belum kukerjakan, dan tenggat waktunya berdekatan semua. Sekarang tugas-tugas itu bertambah jumlahnya menjadi sembilan. Pusing memikirkan masa depanku di sekolah ini, hutan kecil di belakang gedung Confucius menjadi tempat yang pertama kutuju setelah bel terakhir berbunyi.
Di saat aku sudah berbaring leyeh-leyeh di rumput sambil merokok itulah tiba-tiba terdegar suara benda terjatuh ke tanah dari arah pepohonan yang bersisian dengan kampus. Bruk! Seketika aku menoleh. Di jalan yang biasa kulewati untuk masuk ke persembunyian ini, Lucas berdiri menatapku dengan wajah terpana.
"What the fuck!" teriaknya tiba-tiba seraya berderap mendekatiku. Aku langsung berdiri dan berusaha menjauhinya.
"Hei--"
"Yoo Sara!"
"Kamu kenapa, sih?!"
"You can't do this to me!"
"I can't do what?!"
"Being this cute!"
Aku berhenti kabur. Lucas berhenti mengejarku. Kami berdiri berhadap-hadapan. Dengan agak dramatis, cahaya matahari menyinari kami dengan sorotan-sorotan cahaya yang lolos melewati dedaunan di atas kami.
"You're so cute," kata Lucas memecah hening dengan suara yang lebih tenang. "Aku nggak percaya kamu manusia."
Aku sudah dipuja-puji seharian dan kubalas semuanya dengan senyum dan terima kasih yang lancar. Tapi yang ini... Tiba-tiba aku tidak tahu harus menjawab apa. Yang bisa kulakukan hanyalah mengisap rokokku dan memperhatikan Lucas yang masih memandangku seakan-akan aku memang bukan manusia. Matanya yang besar menatapku lembut tanpa berkedip hampir seperti yang dia lakukan di hari rokokku kepergok. Bibirnya melengkung tipis membentuk senyum samar yang manis. Sorot matanya sama sekali tidak membuatku merasa dinilai atau dihakimi, terlebih dia tidak memandangku dari atas ke bawah dan ke atas lagi seperti yang dilakukan semua orang. Aku merasa dia benar-benar memandangku, bukan dandananku. Lama-lama bertatapan dengannya membuat pipiku memanas dan akhirnya menggerakkan leherku untuk menoleh ke arah lain.
"Aku manusialah," kataku setelah beberapa detik yang canggung. "Memangnya kamu, makhluk ekstraterestrial?"
Lucas tertawa kecil. Tawa melengking yang selalu membuatku ingin menirukannya untuk mengejeknya. "Bukan. Maksudku, kamu mungkin seorang peri. Atau putri kerajaan. Atau bangsawan. Gosh, you really scared the shit out of me. Aku kira aku ketemu peri hutan."
Aku ingin bilang Padahal konsepku adalah gadis desa, tapi yang kulakukan hanya tertawa hambar untuk menanggapinya, lalu mengisap rokokku lagi. Tampaknya Lucas baru menyadari situasi canggung ini. Dia juga memaksakan tawa (tawa melengking yang bodoh kalau untuknya) lalu membalikkan badan untuk mengambil ransel hitamnya. Setelah itu, dia duduk di atas rumput. Untuk pertama kalinya sepanjang umurku di sekolah ini, ada orang selain teman-teman dekatku yang duduk di tempat keramatku. Giliran aku yang terpana karena Lucas yang duduk bersila di atas rumput, mengeluarkan laptop dari tas dan meletakkannya di depannya, disorot cahaya matahari dari atas, tiba-tiba terlihat...
umm...
... biasa saja, sih? Tapi tiba-tiba aku merasa ingin berhenti menghujatnya, sekali ini saja.
"Ugh, tempat ini bau rokok sekali, sih," celetuk Lucas tiba-tiba sambil mengerutkan hidung dan mengibas-ngibaskan tangan di depan wajah.
Hhhh. Lupakan.
Bacot sekali orang ini.
#x#oneshot#smrookies#nctwriters#sara#lucas#high school#high school au#neo culture international school#neo culture school#personal fav#fluff#contemporary#novel material#basketballplayer!lucas
2 notes
·
View notes
Note
Aku suka gimana kakak ngedeskripsikan karakter mereka, jadi bisa lebih hidup dan membekas banget;-; ❤
wah membekasnya gimana emang? terima kasiiiih, seneng deh kalo kamu suka~
0 notes
Photo

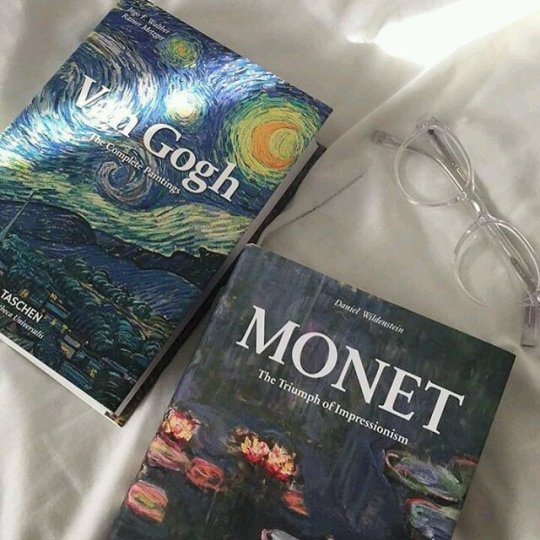


namjoon kim, philosophy & art history, writer
“i have no right to call myself one who knows. i was one who seeks, and i still am, but i no longer seek in the stars or in books; i'm beginning to hear the teachings of my blood pulsing within me.”
— demian, hermann hesse
1 note
·
View note